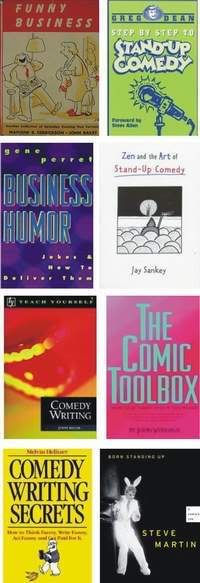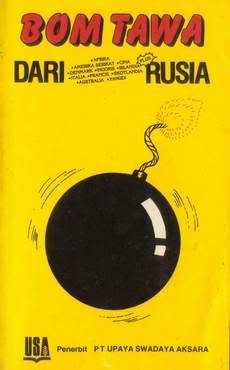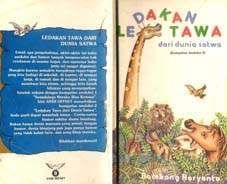Email : humorliner (at) yahoo.com
 Khotbah vs komedi. Abin selalu berangkat lebih awal ke tempat peribadatan dibanding umat lainnya. Ketika ditanya mengapa hal itu ia lakukan, ia menjawab : dengan datang lebih awal memungkinkan dirinya leluasa memilih tempat duduk yang paling belakang.
Khotbah vs komedi. Abin selalu berangkat lebih awal ke tempat peribadatan dibanding umat lainnya. Ketika ditanya mengapa hal itu ia lakukan, ia menjawab : dengan datang lebih awal memungkinkan dirinya leluasa memilih tempat duduk yang paling belakang.Cerita di atas dapat saja Anda anggap sebagai lelucon. Tetapi dapat juga Anda nilai sebagai realita sehari-hari yang jujur. Karena senyatanya mendengarkan khotbah atau pun pidato merupakan peristiwa yang tidak selalu mengenakkan. Bahkan cenderung membosankan.
Bukankah kita punya kecenderungan untuk benci dinasehati, apalagi dikuliahi ? Seorang Thomas Fuller (1608-1661), sejarawan dan pengkhotbah, pernah mengatakan bahwa “perut membenci khotbah-khotbah yang berkepanjangan.”
Albert Einstein (1879–1955) ketika mengikuti pidato yang juga berkepanjangan dalam sebuah pesta perjamuan, ahli fisika legendaris dan penemu teori relativitas itu seperti dikutip koran The Washington Post (12/12/1978) pernah berujar jengkel : “Saya baru saja menemukan teori baru mengenai keabadian.”
Komedian Inggris, Rowan Atkinson ketika berperan sebagai Mr. Bean punya resep tersendiri melawan kebosanan di tengah khotbah. Dalam film pendek yang beberapa kali diputar ulang di stasiun TV kita pernah menyajikan adegan di mana Mr. Bean mengantuk berat hingga ulahnya merepotkan umat di sebelahnya. Padahal saat itu khotbah sedang dilangsungkan.
Khotbah juga jadi cerita tersendiri bagi komedian Afrika-Amerika yang semula Nasrani dan berpindah sebagai muslim, yaitu Bryant Reginald "Preacher" Moss (41). Dia yang sudah malang melintang sebagai penulis komedi untuk Saturday Night Live, Politically Incorrect, The George Lopez Show, punya cerita menarik tentang khotbah.
Utamanya, mengapa ia punya sebutan sebagai Preacher, sang pengkhotbah, bagi nama panggungnya sekarang ini ? Cerita Moss, ia mendapat nama itu dari teman-teman masa kecilnya sesama umat gereja ibunya. “Karena saat kecil itu saya sering menirukan pendeta yang memberikan khotbahnya secara jelek.”
Begitulah, mungkin saja akibat pengalaman masa kecilnya itulah yang memicu Moss ketika dewasa berusaha menyebarkan pesan-pesan luhur Islam tidak melalui jalur khotbah. Tetapi melalui jalur komedi. Pada tahun 2004 ketika umat Islam di Amerika Serikat mendapat perlakuan berbau rasisme yang kental sebagai buntut peristiwa 11 September 2001, ia menggagas tur komedi yang bertajuk (foto) “Allah Made Me Funny : The Official Muslim Comedy Tour.”
Antara lain bersama Azeem, juga komedian muslim keturunan India asal Chicago, Azhar Usman, Preacher Moss berkeliling AS untuk menjelaskan bahwa Islam adalah agama damai melalui komedi. Menurut pengalamannya, lawakan ternyata jauh lebih efektif dibanding khotbah dalam memberikan pemahaman tentang Islam, baik bagi warga non-muslim atau pun warga muslim sendiri. "Well, if anyone issues a fatwa, they can just get up and leave," simpul Preacher Moss.
Lawakan yang mereka luncurkan bahkan tidak jarang sengaja meledeki dirinya sendiri. Sebagai contoh adalah ulah komedian solo Azhar Usman yang lulusan fakultas hukum Universitas Minnesota. Ia berkeyakinan bahwa komedi merupakan bentuk komunikasi yang canggih untuk menghilangkan mitos-mitos dalam Islam dan sekaligus untuk melawan stereotip fihak luar terhadap Islam itu sendiri. Dalam salah satu sajian komedinya ia menirukan keluhan berat seorang warga Amerika Serikat yang baru saja berpindah agama dan menjadi muslim :
“Anda yakin semuanya ini disebut Islam ? Saya tidak boleh minum minuman beralkohol, saya tidak boleh dekat bergaul dengan cewek-cewek, bahkan saya tidak boleh makan sandwich yang ada daging babinya. Semuanya itu sebaiknya bukan disebut Islam, tetapi Is-hard !”
Sebagai muslim sekaligus warga Amerika, Azhar Usman pun berujar bahwa ia memiliki kebanggaan terhadap sikap patriotismenya yang tinggi. “Untuk negara dan bangsa saya Amerika, saya selalu siap berkorban dengan meledakkan perut saya .…di kedai Dunkin’s Donat,” ujarnya.
Berbeda dibanding khotbah, begitu Moss berkeyakinan, lawakan mampu mengajak audiens untuk berpikir, berperanserta dan terlibat dalam dialog dengan komedian bersangkutan. Moss memang tidak memilih cara penyampaian pesan dengan istilah memukul kepala audiensnya, melainkan memberikan peluang agar ide-idenya meresap melalui humor.
“Biarlah terjadi proses pematangan. Karena Anda tidak dapat memaksakan mereka untuk memikirkan sesuatu. Kalau pemaksaan yang terjadi, itu disebut komedi Gestapo,” tegasnya.
Menurutnya, ”banyak orang tidak mau mendengar khotbah-khotbah tentang kebenaran, tetapi mereka berpeluang mau mendengar kebenaran tersebut bila Anda mampu membuat mereka tertawa.”
Pendekatan Moss itu mendapatkan apresiasi. Misalnya, komedian George Lopez dari The George Lopez Show (NBC) berkomentar bahwa “Preacher Moss bukan hanya komedian bagi komunitas muslim, tetapi juga sebagai guru bagi dunia.” Darrell Hammond dari Saturday Night Live (NBC), menimpali : “Seberapa sering kejadian semacam menyapa Anda ketika pertunjukan komedi mampu membuat Anda merasa sebagai orang yang lebih baik ketika usai menontonnya ?”
Bangsa pemarah. Mari kita buka kartu dan berjujur diri : bisakah kita terapkan penilaian Darrel Hammond di atas bagi krida komedian atau pun acara-acara komedi di Indonesia dewasa ini ? Juga bagi acara komedi yang didukung personil yang sudah mengenyam pendidikan paling tinggi sekali pun ?
Mungkin harapan saya itu terlalu melambung-lambung. Atau terlalu prematur ? Karena tidak jarang IQ # HQ. Kecerdasan intelektual memang bukan selalu berbanding lurus dengan kecerdasan ber-humor-ria.
Yang pasti, dengan meminjam istilah sahabat dunia maya saya Isman H. Suryaman yang seorang blogger dan penulis buku humor canggih a la Scott Adams atau Dave Barry yang hard fun berjudul Bertanya atau Mati ? (Gramedia Pustaka Utama, 2004), tayangan komedi di televisi kita terlalu belepotan dengan dimanjakan apa yang ia sebut sebagai laugh track, canned laugh, atau tawa kalengan.
Dengan merujuk pendapat Stevie Ray dalam bukunya Medium-Sized Book of Comedy: What We Laugh At and Why, Isman menjelaskan bahwa penggunaan tawa kalengan yang tepat adalah untuk menyediakan sesuatu yang disebut Stevie Ray sebagai "izin untuk tertawa".
Di Indonesia, menurutnya, humor sering digunakan sebagai kompetisi sosial. Siapa yang mengerti lelucon dianggap lebih pintar daripada yang nggak. Dan siapa yang bisa membuat orang lain tertawa itu dianggap lebih piawai daripada yang tidak. Karena itu, tak jarang seseorang perlu "izin untuk tertawa" dengan melihat keadaan sekitar. Jika ada orang lain yang tertawa, berarti aman untuk ikutan. Apalagi jika orang yang dianggap "berkuasa" sudah tertawa, berarti sangat aman.
Teori Isman ini mengingatkan saya akan adegan temu wicara yang sering dilakukan Pak Harto dengan warga Kelompencapir di masa Orde Baru. Kalau penguasa Orde Baru itu tertawa terhadap leluconnya sendiri, walau tidak lucu sekali pun, maka otomatis hadirin akan segera ramai-ramai ikut tertawa secara massal pula. Anda masih ingat adegan khas era masa Orde Baru ini, bukan ?
Dalam komedi di televisi, lanjut Isman, tawa kalengan dimanfaatkan untuk itu. Agar penonton benar-benar menangkap mana nuansa yang lucu, diberilah sinyal melalui tawa kalengan. Sekaligus izin : mari kita tertawa, atau ayolah tertawalah, karena orang lain juga tertawa.
Sayangnya di TV, menurut Isman, penggunaan tawa kalengan ini salah kaprah. Seringkali pada adegan yang tidak lucu sama sekali, tawa sudah memburai. Jadinya malah kering. Membingungkan. Membuat bertanya-bertanya. Dan sebal. "Apa yang lucu?" Hilanglah kredibilitas tawa kalengan bersangkutan.
Terima kasih, Isman.
Bagi saya, mewabahnya tawa kalengan dalam sajian komedi di televisi kita hanya menunjukkan maraknya wabah komedi Gestapo yang disebut Preacher Moss di atas. Negara kita adalah negara demokrasi, tetapi sajian lawakan di televisi memakai formula represif model polisi rahasia di era Hitler itu. Lucu yang hadir dipaksakan “dari atas” sehingga senyatanya benar-benar merendahkan kemampuan penonton untuk menangkap humor.
Dimana duta komedi Indonesia ? Walau pun demikian, cerita keteladanan Preacher Moss dkk. di atas itu pastilah masih dapat berguna sebagai cermin. Ia yang berada di tengah masyarakat yang oleh sebagian tokoh fundamentalis disebut sebagai masyarakat “kafir,” ia hadapi semua tudingan stereotip tentang Islam itu dengan solusi yang cerdas dan berani.
Bukan dengan aksi demo membakar bendera, menginjak-injak foto atau boneka presiden atau pun melilitkan bom di badannya yang siap meledak di kerumunan. Melainkan, sekali lagi, melalui jalur komedi. Untuk memperoleh pemahaman dari fihak lain, demi meraih harmoni interaksi sosial yang saling menghargai di tengah pluralitas Amerika Serikat sebagai the melting pot yang tak mungkin ia ingkari.
Kekaguman itulah yang tiga tahun lalu memicu saya untuk menulis kiprah Azhar Usman dan kawan-kawan di halaman Teroka, Kompas (18/11/2005). Pada bagian penutup saya ajukan pertanyaan : “Bagaimana dunia lawak muslim di Indonesia ? Kiranya Gus Dur, Mustofa Bisri atau Cak Nun sebagai intelektual muslim, sumber inspirasi dan pencetus lawakan cerdas, kini tak boleh lagi hanya sendirian. Sangat dinantikan Nasarudin Hoja-Nasarudin Hoja baru atau komedian muslim, lahir segera di Indonesia.
Dengan meneladani Azhar Usman dan kawan-kawan, akan mampu membuka perspektif dan wajah segar baru tentang Islam. Apalagi akhir-akhir ini sebagian umat Islam seperti justru senang bersikap reaktif, daripada proaktif, dengan tampil menjadi polisi moral dalam menyikapi sebagian karya-karya kreatif anak bangsa.”
Setelah tiga tahun berlalu, impian saya itu kiranya masih tetap sebagai impian. Kiranya tetap belum muncul komedian muslim andal di negeri demokrasi yang memiliki umat Islam terbesar di dunia ini. Juga belum muncul komedian muslim dengan perspektif muslim a la Indonesia yang berani berperang melawan stereotip dan kebencian ras di Amerika Serikat sana.
Bahkan bila diperlebar keluar dari panggung komedi, sepertinya bangsa ini, khususnya umat Islam, masih memiliki kiat yang terbatas dalam menghadapi “benturan kebudayaan” yang terjadi. Ketika heboh kartun yang menghina Nabi Muhammad SAW muncul di koran Denmark, reaksi tipikal kita adalah marah-marah. Sampai muncul seruan untuk memboikot produk dari Denmark.
Sebagian besar dari kita tidak tahu atau tidak hirau bahwa isu kartun tersebut ketika muncul untuk kedua kalinya telah membelah rakyat Denmark dalam dua kubu. Yaitu kubu yang membela umat Islam dan mengecam mereka yang memiliki sikap yang tidak toleran, sementara kubu lain berpihak kepada keyakinan yang menjunjung kebebasan berekspresi.
Kemudian ketika baru-baru ini muncul heboh film pendek Fitna yang buatan politisi sayap kanan Belanda, Geert Wilders, reaksi kita hampir tak berubah. Hanya bisa kembali marah-marah. Muncul lagi seruan untuk memboikot produk Belanda. Yang agak baru adalah sikap denial, penyangkalan diri, seperti tercermin dari upaya Menkominfo kita yang mengultimatum Google sebagai pemilik layanan video sharing YouTube untuk memblok permintaan akses film Fitna dari Indonesia.
Presiden SBY juga mengancam akan menghukum mereka yang mengedarkan Fitna di Indonesia. Ketika Google menyetujui pemblokiran akses itu, kita sepertinya sudah merasa bahwa misi kita telah berhasil dengan gilang-gemilang. Padahal Internet tak bisa ditaklukkan seratus persen, apalagi hanya dengan surat keputusan !
Kegetolan kita untuk melakukan penyangkalan itu menjadi ulasan menarik Herman Elia dalam artikel “Pemimpin Menjawab Cemooh” (Kompas, 5/4/2008). Artikel ini mengomentari pendapat Presiden SBY sebelumnya bahwa para pemimpin bangsa ini harus tabah menghadapi cemoohan dan kritik dari rakyat yang tidak sabar melihat datangnya perubahan.
Dalam pendapat Herman Elia, protes, cerca dan cemoohan itu memang dibutuhkan. Karena memperlihatkan substansi yang lebih gamblang dibanding hanya sajian fakta dan data. Apalagi, menurutnya, fenomena penyangkalan diri para pemimpin kita sudah demikian meruyak, bahkan hingga sampai pada tahap menyalahkan korban.
Ketika seorang ibu dan anak balitanya meninggal karena kelaparan di Sulawesi Selatan, yang ditonjolkan adalah karena sang suami yang seorang tukang becak suka minum-minuman keras dan tidak memperhatikan keluarganya. Ketika sebuah perguruan tinggi mengumumkan penelitian adanya kandungan enterobacter sakazakii dalam susu formula, disangkal fihak pemerintah dengan mempertanyakan validitas penelitian mereka. Akar dari tindak penyangkalan itu, menurutnya, karena para pemimpin kita memandang diri positif secara berlebihan.
Indonesia yang tidak bergerak. Ilustrasi menarik mengenai pemimpin kita yang memandang diri positif secara berlebihan dapat kita simak dari peristiwa di Lemhanas, yang juga disentil oleh karikatur Om Pasikom di Kompas (12/4/2008) yang lalu. Peristiwa yang terjadi adalah kemarahan Presiden SBY ketika menemui audiens yang tertidur di tengah pidatonya. Bahkan sosok yang tertidur itu sempat ia sebut sebagai “berdosa kepada rakyat.”
Tetapi dalam perspektif fihak yang mengantuk sebagai cerminan rasa bosan mengikuti pidato itu, barangkali pendapat ekonom sohor John Kenneth Galbraith jadi relevan baginya. Sebagaimana pidatonya di American University, Washington DC dan dikutip majalah Time (18/6/1984), Galbraith berujar : “Speeches in our culture are the vacuum that fills a vacuum.” Pidato dalam kultur Amerika adalah kekosongan untuk mengisi kekosongan.
Pidato Presiden SBY tentu saja bukan berisi kekosongan belaka. Walau kemudian ternyata pidatonya menyebabkan audiens mengantuk barangkali karena cara penyampaiannya. Anda pasti punya pendapat sendiri tentang gaya berpidato presiden kita itu. Hal lainnya, tentu saja mengenai naskah pidatonya, di mana saya punya sedikit cerita tentang hal satu ini.
Semua itu diawali ketika saya diiming-imingi sebagai calon “bintang tamu” dalam tayangan parodi politik di televisi. Tawaran ini saya anggap sebagai lelucon, tidak tulus dan tidak serius, tetapi sempat juga mendorong saya melakukan selancar di Internet guna mengunjungi situs yang tidak lajim saya tengok selama ini : situs web Presiden SBY.
Di situs yang dieksekusi dengan pendekatan kuno sehingga ibarat papan pengumuman yang dipasang di tempat sepi itu, saya bisa menemukan pidato Presiden SBY ketika meluncurkan buku kumpulan pidato yang berjudul Indonesia On The Move (Indonesia Bergerak) sekaligus meresmikan perluasan Toko Buku Gramedia di Matraman Raya, Jakarta, 28 Desember 2007.
Bagi saya, baik judul atau pun isi pidatonya itu merupakan bahan mentah yang menarik untuk ditekuk sana-sini sebagai bahan humor. Sebagai contoh, dalam pidatonya tersebut SBY sempat bertanya : “Mengapa saya sampai sekarang terus membeli buku ?”
Dalam humor crafting, pertanyaan itu bisa disebut sebagai set-up, umpan atau jebakan. Ini bagian dari konstruksi lawakan yang pasti tidak lucu, tetapi sangat penting perannya. Bagian inilah yang harus dikreasi sangat cermat guna mampu merenggut perhatian pemirsa. Kemudian disusul ledakan, tonjokan lucunya, punchline, misalnya dapat kita berikan : “Hukum ekuilibrium, Bapak Presiden. Karena Anda kini telah jualan buku pula !”
Judul buku SBY itu sendiri, Indonesia On The Move (Indonesia Bergerak), yang disusun juru bicaranya yang Staf Khusus Hubungan Luar Negeri, Dino Patti Djalal, dapat dikontraskan secara sarkastis dengan judul buku Dari 0,0 Kilometer yang ditulis juru bicara presiden yang lain, Andi A. Mallarangeng.
Misalnya : Mustahil Indonesia mampu bergerak maju. Bukankah kedua orang dekat presiden justru saling bertentangan ? Yang satu ingin bergerak sementara yang lainnya ingin terpatok di titik 0,0 kilometer saja ?
Bocoran info : transkrip pidato Presiden SBY itu berisi sekitar 3300 kata. Terdiri delapan halaman kuarto dengan ketikan berspasi tunggal. Pidato yang menurut saya teramat panjang. Mudah memicu pendengarnya untuk menjadi bosan. Lalu mengantuk dan menjadi tertidur. Sehingga bila Presiden SBY mewacanakan agar pemimpin Indonesia tabah menghadapi cemoohan dan kritik dari rakyat, sepertinya secara pribadi, seperti kasus kemarahannya di Lembahas itu, menunjukkan ia belum siap menghadapinya.
Minimal bila dikontraskan dengan pendapat William Phillips dalam bukunya A Sense of the Present (Chilmark, 1967), yang berujar : boredom, after all is a form of criticism. Kebosanan sesungguhnya merupakan bentuk sebuah kritik. Dalam hal ini tentu saja kritik terhadap gaya pidato, panjang naskah dan isi naskah pidato presiden kita.
Usul-usil saya : kiranya peranserta penulis lelucon atau gag writer sudah menjadi kebutuhan mendesak untuk menjadi bagian dari tim penulis naskah pidato presiden kita di masa-masa mendatang.
Lawakan sebagai kata hati. “Kritik ibarat sikat untuk membersihkan jas para bangsawan,” demikian tutur penyair dan diplomat Inggris, Henry Wotton (1568–1639). Nasehat hebat. Walau pun demikian kritik itu sendiri menjadi hal yang tidak selalu ditanggapi secara elegan oleh mereka yang menjadi sasaran. Kaum agamawan mudah tergoda untuk menampik kritik karena merasa membawakan kebenaran, yaitu wahyu-wahyu dari Tuhan. Para pemimpin bisa juga anti kritik karena merasa paling tahu dan karena memiliki kekuasaan.
Bagaimana dengan komedian ?
Seorang Jon Stewart, penulis dan komedian terkenal yang mengasuh acara The Daily Show with Jon Stewart, pernah dicemooh dalam acara akbar penganugerahan Grammy Award 2001. Ia yang acara televisinya melaporkan kekurangan dan kemunafikan dunia politik Amerika Serikat dengan pisau satir yang tajam dan pernah berujar sebagai komedian ia selalu melucukan segala hal yang absurd dari pemerintah AS, menanggapi cemoohan itu dengan rendah hati : “Saya merasakan cemoohan Anda dan saya ikhlas menerimanya.”
Keikhlasan itu boleh jadi menunjukkan betapa jalan hidup komedian sejati nampaknya memang berbeda dibanding jalan hidup agamawan atau pun tokoh pemerintahan. Komedian dianugerahi keluwesan sikap yang tidak boleh fanatik, sok berkuasa atau pun sok absolut dalam memegang sesuatu kebenaran. Walau pahit, kritik harus menjadi bagian dari eksistensinya.
“Hargai semua kritik. Jangan remehkan kritik. Walau kritik itu salah sekali pun, selalu ada hal-hal positif darinya. Anda harus mencermati bagaimana persepsi orang terhadap diri Anda,” demikian kata John Cantu, mentor humor yang terkenal. Sementara itu Don Stevens memberi masukan kepada komedian tunggal untuk selalu berkeyakinan bahwa sajian komedinya itu akan lebih banyak salah daripada benarnya. Komedian, selalulah berendah hati.
Nasehat-nasehat berharga itu memang tertuju kepada komedian tunggal, stand-up comedian, yang oleh Azhar Usman disebutnya sebagai binatang yang berbeda. "It's a very sophisticated art. Stand-up is different than formula jokes. I was very intimidated at first; you have to do a lot of talking about yourself, " tuturnya.
Komedi tunggal adalah seni yang sangat canggih. Berbeda dari lawakan ketengan. Komedian tunggal memang dituntut selalu untuk melakukan penjelajahan ke dalam diri mereka sendiri sehingga lawakan yang muncul tidak lain merupakan isi kata hati.
Kaleng-kaleng yang berjaket. Bagaimana kritik dalam konstelasi dunia komedi kita ? Kiranya tak ada atau belum ada sosok semacam Simon Cowel, si mulut pedas tetapi jujur dan cerdas dalam American Idol. Media massa kita telah terlalu lama kehilangan sosok wartawan sekualitas Efix Mulyadi atau H. Sujiwo Tejo di Kompas yang berpena tajam dan setia dalam mengorek kekurangan dunia komedi kita. Bagaimana suara para akademisi kita ? Sepi.
Apa pula peran PASKI di sini ? Lupakanlah, karena begitu berdiri PASKI sudah langsung mati suri dengan alasan yang logis : karena dunia komedi kita adalah dunia Hobbesian. Juga terlalu banyak warga komunitas komedi kita yang berkerak dalam mengukuhi sikap mental kelangkaan, scarcity mentality dan belum mengenal paradigma baru, fenomena buntut panjang yang berpendekatan abundance mentality, sikap mental berkelimpahan. Atmosfir iri hati dan menilai komedian lain sebagai saingan masih kental menyelimuti kosmis dunia komedi kita..
Tanpa kritik dan tanpa kerjasama, membuat komedian-komedian kita tidak mampu seperti layang-layang di mana tiupan angin yang keras justru mampu membuatnya terbang dan membubung tinggi. Berlian-berlian calon komedian yang bertebaran di tanah air tidak pula mendapatkan gosokan yang keras dan berkelanjutan sehingga bisa terkelupas bagian luarnya, lalu mampu menunjukkan intinya yang berkilauan.
Yang menonjol dalam dunia komedi kita dewasa ini adalah complacency, rasa puas diri, walau tawa audiens yang mereka peroleh hanyalah tawa kepalsuan atau tawa kalengan belaka. Para kreator acara komedi di televisi-televisi kita nampaknya cukup berbangga dengan hadirnya barisan kaleng-kaleng berisik yang selalu menyemarakkan acaranya itu.
Mungkin karena kaleng-kaleng itu datang secara sukarela dengan rasa bangga. Dengan masing-masing membalut diri secara warna-warni. Dengan jaket-jaket almamater mereka.
Wonogiri, 12-16 April 2008
ke