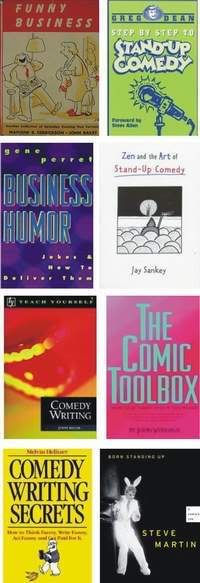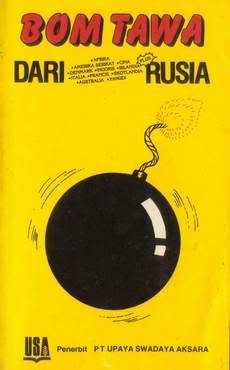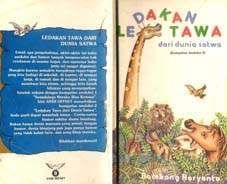Wonogiri, 29 Mei 2005
Yth. Mas Indro Warkop DKI,
MAS DONO ALMARHUM ADALAH FENOMENA LANGKA dalam dunia komedi Indonesia. Anda, Mas Indro, pasti menjadi saksi untuk semua keistimewaan Mas Dono itu. Selain sebagai intelektual, termasuk ketika menjadi dosen di FISIP UI, Mas Dono juga penulis. Jarang sekali ada komedian kita yang juga penulis. Mas Dono tidak hanya menulis novel, tetapi juga buku-buku kumpulan humor, serta artikel-artikel di koran Kompas yang bergengsi.
Salah satu isi tulisan Mas Dono di Harian Kompas, telah saya kutip dalam artikel terlampir. Yaitu ketika Mas Dono mengeluh, “Membuat lucuan yang benar-benar lucu saja setengah mati. Kondisi lawak di Indonesia saat ini : ia adalah pemikir, penulis, penampil, sekaligus pengurus keuangan...Bagaimana bisa selalu prima ?” (Kompas, 22/3/1996).
MERUJUK HAL DI ATAS, dan terutama ketika saat ini Mas Indro menjabat sebagai Ketua Umum PASKI, mudah-mudahan keluhan Mas Dono itu mampu menjadi salah satu ilham bagi Anda dalam mengisi makna kepemimpinan Anda sebagai Ketua Umum PASKI. Hemat saya, seperti juga pernah diusulkan oleh pekerja seni/intelektual dan mantan wartawan Kompas, Sudjiwo Tedjo, bahwa komunitas komedi kita memerlukan suntikan dari para intelektual. Ia usulkan sejak para ahli psikologi sampai ahli bahasa.
Saya sendiri, dalam upaya ikut urun rembug bagi kemajuan komunitas dunia komedi Indonesia, adalah dengan memajang aneka tulisan saya di situs Komedikus Erektus ! (http://komedian.blogspot.com). Salah satu tulisan yang terbaru isinya mendiskusikan disonansi kognitif sebagai formula menciptakan lawakan.
DISKUSI SEPUTAR DISONANSI KOGNITIF itu dimunculkan oleh Prof. Sarlito Wirawan Sarwono, Guru Besar Fakultas. Psikologi UI, dalam email yang beliau kirimkan kepada saya. Kami tak jarang berbagi SMS atau email sejak beliau menjadi salah satu juri Mandom Resolution Award (MRA) 2004 di Jakarta (Nopember 2004), di mana saya ikut dan menjadi salah satu pemenangnya. MRA 2004 ini bukan lomba lawakan, tetapi lomba mencanangkan resolusi dan pencapaiannya.
Begitulah, sementara ini sekian dulu obrolan saya. Terlampir saya kirimkan fotokopi artikel saya (“Dicari, Penulis Naskah Komedi”, yang dimuat di harian Solopos, 29 Mei 2005). Semoga ada manfaatnya bagi Anda dan juga bagi PASKI yang Anda pimpin.
Sukses untuk komunitas komedi Indonesia !
Hormat saya,
Bambang Haryanto
Jl. Kajen Timur 72 Wonogiri 57612
Situs KE : http://komedian.blogspot.com
Situs EI : http://episto.blogspot.com
Email : humorliner@yahoo.com
HP : +6281 329306300
Sunday, May 29, 2005
Dicari, Penulis Naskah Komedi !
Oleh : Bambang Haryanto
Email : humorliner@yahoo.com
Dimuat di Harian Solopos (Solo), 29 Mei 2005.
MAJALAH US News & World Report (12/91988) pernah mewartakan kecemasan berat yang diidap komedian Richard Lewis. Saat itu ia ditanya oleh temannya : apa yang ia kerjakan bila harta karun yang ia miliki, yaitu naskah-naskah komedi yang ia tulis selama 16 tahun terakhir, terbakar bersama rumahnya. Dengan ketakutan. Lewis segera bergegas menuju kantor bank terdekat di Beverly Hills, lalu menyewa safe deposit, untuk mengamankan lebih dari 250.000 judul lelucon karyanya.
Tidak setiap komedian seperti Richard Lewis yang begitu cermat dan memiliki perhatian yang tinggi terhadap karya-karya tertulis komedinya. Di Indonesia pernah terbetik kabar bahwa naskah pemanggungan lawakan Srimulat yang ditulis almarhum Teguh Srimulat, telah hilang.
Bahkan kabar angin yang berhembus kemudian mewartakan bahwa ada kelompok lawak tertentu yang (saat itu lagi ngetop di televisi) diduga menjiplak naskah milik kelompok lawak Srimulat yang hilang tersebut. Kontroversi ini sepertinya belum tuntas sampai saat ini, tetapi fakta tersebut menandakan bahwa naskah komedi merupakan komoditas yang tetap saja langka dan sangat dicari di negeri ini.
Sayang, pemahaman mengenai pentingnya naskah komedi tersebut terlalu lama tidak terangkat ke permukaan. Bahkan, sekadar contoh, di balik hiruk pikuk acara reality show di stasiun televisi swasta TPI yang mengadakan seleksi kelompok lawak bertajuk Audisi Pelawak TPI (API), isu penting itu tidak gencar mengemuka.
Disebutkan, Audisi Pelawak TPI merupakan ajang unjuk prestasi bagi grup pelawak muda berpotensi yang belum mendapat kesempatan unjuk kemampuan berkompetisi menjadi grup lawak terbaik. Di sisi lain, kehadiran pelawak-pelawak baru di layar kaca dirasakan menjadi salah satu kebutuhan saat ini, karena kondisi obyektif saat ini menunjukkan kehadiran pelawak yang sama dalam satu malam pada berbagai stasiun televisi yang berbeda.
Dengan demikian API diharapkan mampu menghadirkan pelawak-pelawak baru berkualitas, sehingga menambah panjang daftar pelawak-pelawak di tanah air.
DEMIKIANLAH, KITA CATAT betapa kebutuhan adanya naskah-naskah komedi dan penulis-penulisnya sekaligus, seolah dianggap bukan hal yang mendesak. Hal itu bisa dimaklumi karena acara seperti API tak lain merupakan program me too, program berbau ikut-ikutan dari reality show yang lebih dulu terkenal seperti AFI (Akademi Fantasi Indosiar) atau pun Indonesia Idol.
Kedua program kontes untuk menemukan bintang-bintang baru dalam kegiatan tarik suara tersebut telah dicontek mentah-mentah oleh para konseptor acara TPI, yaitu hanya mengganti subjek atau pelakunya, yang semula calon penyanyi digantikan para calon pelawak. Mereka melupakan bahwa sebenarnya antara nyanyian atau lagu dengan lawakan terdapat perbedaan yang mencolok, walau pun keduanya dapat sama–sama dipanggungkan di layar televisi.
SENYATANYA DUNIA KOMEDI tidak sama dengan dunia tarik suara. Dunia komedi memiliki tuntutan yang jauh lebih keras. Sebab dalam dunia tarik suara sebuah lagu dapat dan halal secara mudah diulang-ulang, untuk dinyanyikan oleh beragam penyanyi, dalam pelbagai kesempatan. Tetapi lawakan tidak. Kalau Anda melucukan sesuatu, mungkin di antara kawan-kawan ada yang menyeletuk bahwa ia sudah pernah mendengarnya. Dalam dunia menyanyi, bakal tak ada penonton yang berteriak melarang seseorang menyanyikan sesuatu lagu karena lagu tersebut pernah didengarnya.
Realitas ini menandakan bahwa tuntutan orisinalitas yang tinggi terhadap materi lawakan, membuatnya terasa semakin langka dalam peredaran. Apalagi materi lawakan baru ketika begitu tampil di media akan langsung menjadi usang. Faktanya, tidak hanya materi lawakan spesifik tersebut, juga premisnya, bahkan semua lawakan yang mirip juga ikut menjadi usang karenanya.
Tuntutan orisinalitas yang tinggi terhadap materi lawakan tersebut membuat banyak kelompok lawak kita tidak punya nafas panjang. “Membuat lucuan yang benar-benar lucu saja setengah mati. Kondisi lawak di Indonesia saat ini : ia adalah pemikir, penulis, penampil, sekaligus pengurus keuangan....Bagaimana mau selalu prima ?”, cetus almarhum Dono Warkop (1996) ketika mengeluhkan tiadanya penulis –penulis naskah komedi yang dapat meringankan bebannya.
KELUHAN KRONIS DONO tersebut bisa dimaklumi, apalagi karena komedi memang seni yang rumit. Edmund Gwenn, aktor komedi Hollywood era 1940-an saat menjelang ajalnya berbisik kepada aktor Hollywood terkenal lainnya, Jack Lemmon, bahwa menuju kematian itu menyakitkan, tetapi tidak sebegitu menyakitkan dibandingkan berpentas sebagai komedian.
Sementara itu Gene Perret, pemenang tiga Emmy Award dalam penulisan naskah komedi yang sekaligus penulis lawakan komedian Bob Hope yang terkenal, menyatakan bahawa penulisan naskah komedi ibarat jazz dalam musik Selain harus inovatif, sarat pemberontakan, ketimbang berlaku normal. Bahkan cenderung menghancurkan tradisi yang ada ketimbang membebeknya.
Walau pun demikian, imbuh Perret, penulisan naskah komedi dapat dipelajari. Menjadi komedian juga dapat dipelajari. Kalau kita sudi melebarkan wawasan terhadap dunia komedi di negara-negara maju, seperti di Amerika Serikat, tidak sedikit ditemui pelbagai workshop untuk calon komedian dan workshop pelatihan bagi penulis naskah-naskah komedi.
UNTUK PERKEMBANGAN MASA DEPAN DUNIA KOMEDI KITA, apalagi setelah hadirnya organisasi PASKI (Persatuan Artis Seni Komedi Indionesia), diharapkan kontes semacam API di TPI haruslah dibarengi dengan kegiatan yang bermenukan intelektualitas. Misalnya dengan menyelenggarakan workshop penulisan naskah komedi sampai kiat-kiat menjadi komedian.
Karena kita telah lama kehilangan intelektual humor sekaliber almarhum Arwah Setiawan, sementara tokoh lainnya seperti Arswendo Atmowiloto atau pun Jaya Suprana ketika menjadi pencela (kritikus) di ajang API justru nampak terbawa arus, maka untuk membuka wawasan yang lebih luas sudah saatnya bila didatangkan pembicara dari luar negeri.
Upaya pembelajaran yang lebih serius dan komprehensif dalam komunitas dunia komedi kita yang selama ini sangat terbengkalai, bahkan selama puluhan tahun ini, menunggu segera untuk direalisasikan !
*Bambang Haryanto, penulis komedi dan dua buku kumpulan humor. Alumnus UI.
Email : humorliner@yahoo.com
Dimuat di Harian Solopos (Solo), 29 Mei 2005.
MAJALAH US News & World Report (12/91988) pernah mewartakan kecemasan berat yang diidap komedian Richard Lewis. Saat itu ia ditanya oleh temannya : apa yang ia kerjakan bila harta karun yang ia miliki, yaitu naskah-naskah komedi yang ia tulis selama 16 tahun terakhir, terbakar bersama rumahnya. Dengan ketakutan. Lewis segera bergegas menuju kantor bank terdekat di Beverly Hills, lalu menyewa safe deposit, untuk mengamankan lebih dari 250.000 judul lelucon karyanya.
Tidak setiap komedian seperti Richard Lewis yang begitu cermat dan memiliki perhatian yang tinggi terhadap karya-karya tertulis komedinya. Di Indonesia pernah terbetik kabar bahwa naskah pemanggungan lawakan Srimulat yang ditulis almarhum Teguh Srimulat, telah hilang.
Bahkan kabar angin yang berhembus kemudian mewartakan bahwa ada kelompok lawak tertentu yang (saat itu lagi ngetop di televisi) diduga menjiplak naskah milik kelompok lawak Srimulat yang hilang tersebut. Kontroversi ini sepertinya belum tuntas sampai saat ini, tetapi fakta tersebut menandakan bahwa naskah komedi merupakan komoditas yang tetap saja langka dan sangat dicari di negeri ini.
Sayang, pemahaman mengenai pentingnya naskah komedi tersebut terlalu lama tidak terangkat ke permukaan. Bahkan, sekadar contoh, di balik hiruk pikuk acara reality show di stasiun televisi swasta TPI yang mengadakan seleksi kelompok lawak bertajuk Audisi Pelawak TPI (API), isu penting itu tidak gencar mengemuka.
Disebutkan, Audisi Pelawak TPI merupakan ajang unjuk prestasi bagi grup pelawak muda berpotensi yang belum mendapat kesempatan unjuk kemampuan berkompetisi menjadi grup lawak terbaik. Di sisi lain, kehadiran pelawak-pelawak baru di layar kaca dirasakan menjadi salah satu kebutuhan saat ini, karena kondisi obyektif saat ini menunjukkan kehadiran pelawak yang sama dalam satu malam pada berbagai stasiun televisi yang berbeda.
Dengan demikian API diharapkan mampu menghadirkan pelawak-pelawak baru berkualitas, sehingga menambah panjang daftar pelawak-pelawak di tanah air.
DEMIKIANLAH, KITA CATAT betapa kebutuhan adanya naskah-naskah komedi dan penulis-penulisnya sekaligus, seolah dianggap bukan hal yang mendesak. Hal itu bisa dimaklumi karena acara seperti API tak lain merupakan program me too, program berbau ikut-ikutan dari reality show yang lebih dulu terkenal seperti AFI (Akademi Fantasi Indosiar) atau pun Indonesia Idol.
Kedua program kontes untuk menemukan bintang-bintang baru dalam kegiatan tarik suara tersebut telah dicontek mentah-mentah oleh para konseptor acara TPI, yaitu hanya mengganti subjek atau pelakunya, yang semula calon penyanyi digantikan para calon pelawak. Mereka melupakan bahwa sebenarnya antara nyanyian atau lagu dengan lawakan terdapat perbedaan yang mencolok, walau pun keduanya dapat sama–sama dipanggungkan di layar televisi.
SENYATANYA DUNIA KOMEDI tidak sama dengan dunia tarik suara. Dunia komedi memiliki tuntutan yang jauh lebih keras. Sebab dalam dunia tarik suara sebuah lagu dapat dan halal secara mudah diulang-ulang, untuk dinyanyikan oleh beragam penyanyi, dalam pelbagai kesempatan. Tetapi lawakan tidak. Kalau Anda melucukan sesuatu, mungkin di antara kawan-kawan ada yang menyeletuk bahwa ia sudah pernah mendengarnya. Dalam dunia menyanyi, bakal tak ada penonton yang berteriak melarang seseorang menyanyikan sesuatu lagu karena lagu tersebut pernah didengarnya.
Realitas ini menandakan bahwa tuntutan orisinalitas yang tinggi terhadap materi lawakan, membuatnya terasa semakin langka dalam peredaran. Apalagi materi lawakan baru ketika begitu tampil di media akan langsung menjadi usang. Faktanya, tidak hanya materi lawakan spesifik tersebut, juga premisnya, bahkan semua lawakan yang mirip juga ikut menjadi usang karenanya.
Tuntutan orisinalitas yang tinggi terhadap materi lawakan tersebut membuat banyak kelompok lawak kita tidak punya nafas panjang. “Membuat lucuan yang benar-benar lucu saja setengah mati. Kondisi lawak di Indonesia saat ini : ia adalah pemikir, penulis, penampil, sekaligus pengurus keuangan....Bagaimana mau selalu prima ?”, cetus almarhum Dono Warkop (1996) ketika mengeluhkan tiadanya penulis –penulis naskah komedi yang dapat meringankan bebannya.
KELUHAN KRONIS DONO tersebut bisa dimaklumi, apalagi karena komedi memang seni yang rumit. Edmund Gwenn, aktor komedi Hollywood era 1940-an saat menjelang ajalnya berbisik kepada aktor Hollywood terkenal lainnya, Jack Lemmon, bahwa menuju kematian itu menyakitkan, tetapi tidak sebegitu menyakitkan dibandingkan berpentas sebagai komedian.
Sementara itu Gene Perret, pemenang tiga Emmy Award dalam penulisan naskah komedi yang sekaligus penulis lawakan komedian Bob Hope yang terkenal, menyatakan bahawa penulisan naskah komedi ibarat jazz dalam musik Selain harus inovatif, sarat pemberontakan, ketimbang berlaku normal. Bahkan cenderung menghancurkan tradisi yang ada ketimbang membebeknya.
Walau pun demikian, imbuh Perret, penulisan naskah komedi dapat dipelajari. Menjadi komedian juga dapat dipelajari. Kalau kita sudi melebarkan wawasan terhadap dunia komedi di negara-negara maju, seperti di Amerika Serikat, tidak sedikit ditemui pelbagai workshop untuk calon komedian dan workshop pelatihan bagi penulis naskah-naskah komedi.
UNTUK PERKEMBANGAN MASA DEPAN DUNIA KOMEDI KITA, apalagi setelah hadirnya organisasi PASKI (Persatuan Artis Seni Komedi Indionesia), diharapkan kontes semacam API di TPI haruslah dibarengi dengan kegiatan yang bermenukan intelektualitas. Misalnya dengan menyelenggarakan workshop penulisan naskah komedi sampai kiat-kiat menjadi komedian.
Karena kita telah lama kehilangan intelektual humor sekaliber almarhum Arwah Setiawan, sementara tokoh lainnya seperti Arswendo Atmowiloto atau pun Jaya Suprana ketika menjadi pencela (kritikus) di ajang API justru nampak terbawa arus, maka untuk membuka wawasan yang lebih luas sudah saatnya bila didatangkan pembicara dari luar negeri.
Upaya pembelajaran yang lebih serius dan komprehensif dalam komunitas dunia komedi kita yang selama ini sangat terbengkalai, bahkan selama puluhan tahun ini, menunggu segera untuk direalisasikan !
*Bambang Haryanto, penulis komedi dan dua buku kumpulan humor. Alumnus UI.
Thursday, May 26, 2005
Menikmati Humor Prof. Sarlito W. Sarwono (2)
(Menelisik disonansi kognitif dalam sitkom Friends)
Oleh : Bambang Haryanto
Email : humorliner@yahoo.com
TAWA MENYENTUH KALBU. Pasangan kumpul kebo Ross (David Schwimmer) dan Rachel (Jennifer Aniston) dalam sitkom Friends yang terkenal sedang dikisahkan mencari pembantu rumah tangga. Tentu saja untuk mengasuh putrinya, Emma, yang masih berusia balita.
Ada seorang kandidat kuat, seorang wanita yang nampak sabar, keibuan dan berlatar belakang keturunan Hispanik. Dalam wawancara nampak ada kimia kecocokan antara ketiganya.
Tetapi ketika wawancara usai dan si wanita itu hendak pulang, terjadilah adegan tanya jawab di depan pintu. Wanita itu bertanya dalam nada cemas, apakah di keluarga ini sering ada tes penggunaan narkoba secara mendadak. Kalau ada, ia mengharap, dirinya memperoleh pemberitahuan tersebut tiga hari sebelumnya. Tentu saja, kandidat nanny yang satu ini segera mereka coret dari daftar nominasi.
Sejurus kemudian bel pintu apartemen Ross dan Rachel berbunyi. Kata Ross, calon pembantu satu ini yang ia sebut dengan “she” bernama Sandy. Berpengalaman tiga tahun dan memiliki latar belakang early childhood education, pendidikan usia dini yang cocok untuk mengasuh Emma. Ketika pintu dibuka, yang segera terlihat di hadapan mata Ross dan Rachel adalah sosok yang tak terduga-duga sebelumnya.
“Hi, nama saya Sandy”.
Ia seorang pria muda dan tampan.
Dalam menit-menit pertama, sitkom Friends telah menghasilkan kejutan demi kejutan. Tentu saja pula ledakan tawa. Bahkan berlanjut ketika ditunjukkan bahwa Sandy (Freddie Prinze Jr.) yang pengasuh bayi pria itu memang andal dan penuh kasih sayang yang tak kalah dari nature seorang wanita. Rachel yang sering digambarkan sebagai wanita yang mudah terharu, terenyuh dengan kebaikan, serta merta menyukai Emma diasuh olehnya.
Sementara Ross yang nampak luarnya berlagak macho, merasa aneh. Ia merasa tidak sreg di rumahnya ada pengasuh bayi pria yang sensitif, mudah menangis dalam haru, terampil merajut, pandai mengasuh Emma, baik mendongeng dengan boneka atau menina bobo Emma dengan tiupan recorder lagu “Greenfield” yang menawan. Juga pintar memasak kue. Terlebih lagi Sandy juga disukai pula oleh teman-teman mereka. Bahkan mengajak Joey Tribiani (Matt Le Blanc) dan Rachel untuk memainkan recorder melantunkan lagu anak-anak “Three Blind Mice” yang menampilkan suasana ceria.
DISONANSI KOGNITIF. Hal-hal kurang lajim dari nanny pria ini dalam sepanjang cerita memang menghasilkan tawa demi tawa. Tawa yang muncul adalah tawa yang menyentuh kalbu-kalbu kita. Karena kita bisa berempati dengan sosok Sandy, betapa pria pun dapat menampilkan sisi-sisi feminin yang ia miliki secara tulus dan apa adanya.
Jelasnya, tawa yang kita hadirkan bukan tawa yang murahan. Misalnya karena karena ulah badut-badutan. Tidak ada itu. Jauh pula dari stereotip bahwa dalam lawakan sisi feminitas seseorang pria selalu identik dengan penampilan sissy atau kebanci-bancian yang memang masih suka dieksploitasi dalam pemanggungan lawak di televisi-televisi kita.
Kejadian-kejadian tidak normal tersebut dalam bahasa Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Prof. Sarlito W. Sarwono, dapat digolongkan dalam apa yang beliau sebut sebagai Disonansi Kognitif. Dalam email (8/5/2005) yang dikirimkan kepada saya, antara lain beliau telah menulis :
Mas Bambang,
Tulisan anda tentang Komedi Indonesia sangat betul. Jadi pelawak memang harus cerdas, karena kunci lucu cuma satu, yaitu penonton tiba-tiba dihadapkan kepada sesuatu hal yang bertentangan dengan apa yang mereka ketahui selama ini.
Dalam Psikologi, itu namanya Disonansi Kognitif. Contoh, penyanyi sepuh ber-blangkon dan lurik, tiba-tiba menyanyi "Love Me Tender" dengan suara dan gaya Elvis Presley (selalu ada di Srimulat jaman dulu dan selalu memancing tawa).
SEMBUNYIKAN KEJUTAN. Disonansi kognitif memang berpotensi menimbulkan kejutan, dan itulah nyawa dari pementasan lawakan. Sebab pementasan komedi senyatanya merupakan mata rantai kejutan demi kejutan. Tanpa unsur dadakan, kejutan atau surprise, gelak tawa yang memuncak tak bakal meledak dari sana. Untuk meraih momen puncak tawa tersebut, Gene Perret, penulis kepala untuk komedian sohor Bob Hope, telah menulis formulanya :
Hide the joke whenever possible. Get some surprise into the punchline. Don’t let the audience see it coming. Sembunyikan lelucon Anda semampu mungkin. Hadirkan dadakan saat kata pukulan itu diledakkan. Jangan sampai penonton tahu kedatangannya.
Dalam bahasa sehari-hari, disonansi kognitif itu mungkin dapat pula diartikan sebagai reversal, kebalikan. Ronald Wolfe dalam bukunya Writing Comedy : A Guide to Scriptwriting for TV, Radio, Film and Stage (1992), menulis bahwa : kebalikan dari hal-hal yang normal terjadi, yang muncul secara tak terduga, akan menghasilkan ledakan tawa.
Wolfe pun bermurah hati memberikan contoh :
“Istriku dan diriku telah bersepakat untuk bercerai, tetapi anak-anaklah yang membuat kita masih bersama. Aku tidak menginginkan anak-anak tersebut dan istriku juga tidak menginginkannya pula !”
Saya yakin, Prof. Sarlito akan terbahak dengan lelucon disonansi kognitif yang cerdas ini. Bagaimana dengan Anda ?
Wonogiri, 26 Mei 2005
Oleh : Bambang Haryanto
Email : humorliner@yahoo.com
TAWA MENYENTUH KALBU. Pasangan kumpul kebo Ross (David Schwimmer) dan Rachel (Jennifer Aniston) dalam sitkom Friends yang terkenal sedang dikisahkan mencari pembantu rumah tangga. Tentu saja untuk mengasuh putrinya, Emma, yang masih berusia balita.
Ada seorang kandidat kuat, seorang wanita yang nampak sabar, keibuan dan berlatar belakang keturunan Hispanik. Dalam wawancara nampak ada kimia kecocokan antara ketiganya.
Tetapi ketika wawancara usai dan si wanita itu hendak pulang, terjadilah adegan tanya jawab di depan pintu. Wanita itu bertanya dalam nada cemas, apakah di keluarga ini sering ada tes penggunaan narkoba secara mendadak. Kalau ada, ia mengharap, dirinya memperoleh pemberitahuan tersebut tiga hari sebelumnya. Tentu saja, kandidat nanny yang satu ini segera mereka coret dari daftar nominasi.
Sejurus kemudian bel pintu apartemen Ross dan Rachel berbunyi. Kata Ross, calon pembantu satu ini yang ia sebut dengan “she” bernama Sandy. Berpengalaman tiga tahun dan memiliki latar belakang early childhood education, pendidikan usia dini yang cocok untuk mengasuh Emma. Ketika pintu dibuka, yang segera terlihat di hadapan mata Ross dan Rachel adalah sosok yang tak terduga-duga sebelumnya.
“Hi, nama saya Sandy”.
Ia seorang pria muda dan tampan.
Dalam menit-menit pertama, sitkom Friends telah menghasilkan kejutan demi kejutan. Tentu saja pula ledakan tawa. Bahkan berlanjut ketika ditunjukkan bahwa Sandy (Freddie Prinze Jr.) yang pengasuh bayi pria itu memang andal dan penuh kasih sayang yang tak kalah dari nature seorang wanita. Rachel yang sering digambarkan sebagai wanita yang mudah terharu, terenyuh dengan kebaikan, serta merta menyukai Emma diasuh olehnya.
Sementara Ross yang nampak luarnya berlagak macho, merasa aneh. Ia merasa tidak sreg di rumahnya ada pengasuh bayi pria yang sensitif, mudah menangis dalam haru, terampil merajut, pandai mengasuh Emma, baik mendongeng dengan boneka atau menina bobo Emma dengan tiupan recorder lagu “Greenfield” yang menawan. Juga pintar memasak kue. Terlebih lagi Sandy juga disukai pula oleh teman-teman mereka. Bahkan mengajak Joey Tribiani (Matt Le Blanc) dan Rachel untuk memainkan recorder melantunkan lagu anak-anak “Three Blind Mice” yang menampilkan suasana ceria.
DISONANSI KOGNITIF. Hal-hal kurang lajim dari nanny pria ini dalam sepanjang cerita memang menghasilkan tawa demi tawa. Tawa yang muncul adalah tawa yang menyentuh kalbu-kalbu kita. Karena kita bisa berempati dengan sosok Sandy, betapa pria pun dapat menampilkan sisi-sisi feminin yang ia miliki secara tulus dan apa adanya.
Jelasnya, tawa yang kita hadirkan bukan tawa yang murahan. Misalnya karena karena ulah badut-badutan. Tidak ada itu. Jauh pula dari stereotip bahwa dalam lawakan sisi feminitas seseorang pria selalu identik dengan penampilan sissy atau kebanci-bancian yang memang masih suka dieksploitasi dalam pemanggungan lawak di televisi-televisi kita.
Kejadian-kejadian tidak normal tersebut dalam bahasa Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Prof. Sarlito W. Sarwono, dapat digolongkan dalam apa yang beliau sebut sebagai Disonansi Kognitif. Dalam email (8/5/2005) yang dikirimkan kepada saya, antara lain beliau telah menulis :
Mas Bambang,
Tulisan anda tentang Komedi Indonesia sangat betul. Jadi pelawak memang harus cerdas, karena kunci lucu cuma satu, yaitu penonton tiba-tiba dihadapkan kepada sesuatu hal yang bertentangan dengan apa yang mereka ketahui selama ini.
Dalam Psikologi, itu namanya Disonansi Kognitif. Contoh, penyanyi sepuh ber-blangkon dan lurik, tiba-tiba menyanyi "Love Me Tender" dengan suara dan gaya Elvis Presley (selalu ada di Srimulat jaman dulu dan selalu memancing tawa).
SEMBUNYIKAN KEJUTAN. Disonansi kognitif memang berpotensi menimbulkan kejutan, dan itulah nyawa dari pementasan lawakan. Sebab pementasan komedi senyatanya merupakan mata rantai kejutan demi kejutan. Tanpa unsur dadakan, kejutan atau surprise, gelak tawa yang memuncak tak bakal meledak dari sana. Untuk meraih momen puncak tawa tersebut, Gene Perret, penulis kepala untuk komedian sohor Bob Hope, telah menulis formulanya :
Hide the joke whenever possible. Get some surprise into the punchline. Don’t let the audience see it coming. Sembunyikan lelucon Anda semampu mungkin. Hadirkan dadakan saat kata pukulan itu diledakkan. Jangan sampai penonton tahu kedatangannya.
Dalam bahasa sehari-hari, disonansi kognitif itu mungkin dapat pula diartikan sebagai reversal, kebalikan. Ronald Wolfe dalam bukunya Writing Comedy : A Guide to Scriptwriting for TV, Radio, Film and Stage (1992), menulis bahwa : kebalikan dari hal-hal yang normal terjadi, yang muncul secara tak terduga, akan menghasilkan ledakan tawa.
Wolfe pun bermurah hati memberikan contoh :
“Istriku dan diriku telah bersepakat untuk bercerai, tetapi anak-anaklah yang membuat kita masih bersama. Aku tidak menginginkan anak-anak tersebut dan istriku juga tidak menginginkannya pula !”
Saya yakin, Prof. Sarlito akan terbahak dengan lelucon disonansi kognitif yang cerdas ini. Bagaimana dengan Anda ?
Wonogiri, 26 Mei 2005
Monday, May 23, 2005
Ngelantur Gosong, Limau Teracun Jim Carrey Palsu, SOS Kacau dan Bajaj Terpeleset
Resensi Pentas Kembang Api, TPI, 22 Mei 2005
Oleh : Bambang Haryanto
Email : humorliner@yahoo.com
DRAKULA MENGEJAR BASUKI. Kemana pun Basuki lari ke pojok-pojok panggung, Drakula itu selalu mengejarnya. Kadang muncul suatu adegan saat Basuki justru meledek Drakula bersangkutan, yang dinilai terlalu lamban bergerak. Malam itu saya jadi saksi betapa panggung Anekaria Srimulat di Taman Ria Senayan, Jakarta, tahun 1980-an, riuh dengan gelak tawa.
Sebagai puncak uber-uberan Drakula vs Basuki berakhir ketika Basuki tak bisa menghindar. Ia terjatuh dengan gaya split, lalu menekuk kaki depannya, meniru adegan dalam pentas wayang orang untuk menyatakan takluk kepada fihak yang mengalahkannya. Gaya wayang orang dari Basuki ini meledakkan tawa. Khasanah gerak dari wayang orang yang secara tiba-tiba masuk dalam adegan pentas Srimulat, dan penonton pun memahaminya, itulah rumus mengapa ledakan tawa penonton segera riuh terjadi.
Tahu sama tahu. Pelawak tahu. Penonton pun tahu. Itulah rumus mati dari lawakan yang mengundang tawa. Sekali lagi saya tak bosan mengutip ucapan dari Gene Perret, kepala penulis lawakannya Bob Hope, yang menulis bahwa sense of humor menyangkut tiga keterampilan : (1) to see things as they are, melihat sesuatu apa adanya, (2) to recognize things as they are, memahami/mengerti sesuatu apa adanya, dan (3) to accept things as they are, menerima sesuatu apa adanya.
Sekadar contoh : awal Maret 2005, Erika Michiko, reporter yang cantik dari rumah produksi Shandika Widya Cinema bersama Sabar (kamerawan) dan Yanto (pengemudi) menyambangi rumah saya di Wonogiri. Mereka hendak mendokumentasikan kiprah saya sebagai seorang epistoholik, penulis surat-surat pembaca sejak tahun 1973, untuk tayangan Bussseeet di stasiun televisi swasta TV7. Hasil reportase itu telah ditayangkan 20/3/2005 dan 18/5/2005 yang lalu.
Setelah melewati tahap wawancara, lalu ditetapkan tema tayangan, syuting pun segera dimulai. Saat itu saya nyeletuk, “kini saatnya saya belajar bahasa visual”. Sabar dan Erika terdengar tertawa. Apa ada yang lucu, atau sengaja dibuat lucu, dari kalimat saya tadi ? Tidak ada, bukan ?
Urgensi dari kalimat “belajar bahasa visual” saya munculkan, karena saya faham bahwa memang terdapat perbedaan antara bahasa tulis dengan bahasa visual. Orang-orang media televisi pasti tahu. Erika dan Sabar juga tahu. Saya hanya melakukan callback sesuatu yang ia tahu. Tawa muncul dari formula tahu sama tahu itu.
Karena memang pemahaman tentang bahasa visual tersebut telah saya geluti dan saya ajarkan di tahun 1984. Saat itu saya menjadi asisten dosen untuk mata kuliah Teknologi Media di Jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Sastra (kini Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya) Universitas Indonesia, Jakarta.
Dengan melontarkan sesuatu konsep yang saya yakin juga juga difahami oleh audiens “lawakan” saya saat itu, dalam hal ini Erika dan Sabar, maka dengan murah hati mereka pun menyambutnya dengan tawa. Tahu sama tahu, sekali lagi, itu kuncinya.
Contoh lain : pengamat politik Eep Saefuloh yang baru saja menikahi presenter televisi Sandrina Malakiano, dalam suatu seminar, telah mengaitkan dirinya dengan peristiwa pembongkaran tindak korupsi di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Eep cerita, mungkin karena dirinya dikira sebagai orang KPU atau ada orang KPU yang mirip dirinya, ketika mengisi bensin ada seseorang yang nyeletuk : “Pak Eep, mobil Anda ini hasil dari dana taktis KPU, ya ? Dan kemarin bisa umroh, juga berkat dana dari sumber yang sama ya?”. Tentu saja, semua peserta seminar itu terbahak. Tahu sama tahu.
TETAPI NGELANTUR TIDAK TAHU. Kelompok lawak Ngelantur asal Waru Sidoarjo ini, hemat saya, dalam penampilannya di Kembang Api, 22 Mei 2005, tidak memerhatikan rumus tahu sama tahu tersebut. Trio Heri Suryanto, Totok Pranadi dan M. Isa tersebut akhirnya gosong malam itu. Padahal adegan awalnya, dialog dua orang, berpakaian biasa, yang melucukan kelompok-kelompok lawak pesaingnya, cukup menggelitik.
Tetapi begitu muncul tokoh ketiga, memakai pakaian, gerak-gerik dan mengenakan mahkota raja, penonton dibuat terkacau. Tidak ada lagi kesatuan konteks dalam adegan yang terjadi. Tidak mudah bagi penonton untuk memahami bagaimana sosok dua orang yang berpakaian masa kini tiba-tiba harus berinteraksi dengan seorang “raja”. Raja dari mana ? Memang sang “raja” itu terlihat bloon, berkali-kali menanyakan siapa jati dirinya, tetapi konteks dan dialog yang terjadi antara ketiganya sudah tidak mempunyai fondasi kuat lagi untuk memancing penonton untuk tertawa.
Kecelakaan yang nyaris serupa dialami oleh kelompok SOS dari Bandung. Dengan mengambil seting Romeo dan Juliet, bahkan sampai Sule (Sutisna) mau-maunya berpakaian model putri raja, memancing kontroversi. Pencela Basuki bilang, sebaiknya memakai seting cerita dalam negeri saja. Kalau demi alasan tahu sama tahu, saran Basuki ini layak diperhatikan.
Sementara itu pencela lainnya, Mang Ibing yang sarjana muda Sastra Rusia, menganggap kisah Romeo dan Juliet karya pujangga Inggris William Shakespeare sebagai humanisme universal. Cerita itu, katanya, adalah sastra dunia dan sudah menjadi milik semua bangsa. Keduanya, boleh jadi benar.
Tetapi dalam pentas lawakan, rumus tahu sama tahu, malam itu telah diteledorkan oleh trio Suwarman (Oni), Obin Wahyudin (Ogi) dan Sutisna (Sule) ini. Bahkan ketika Sule di awal adegan menyanyikan lagu Yen Ing Tawang, berbahasa Jawa, kekacauan konteks makin terasa menjadi-jadi.
JIM CARREY DARI TANGERANG. Di MSFN Forum pernah diluncurkan diskusi mengenai siapa stand-up comedian atau pelawak solo, yang terbaik. Nama-nama yang muncul banyak sekali dan beragam. Ada nama George Carlin, yang oleh salah satu pengusulnya diimbuhi pendapat, “bila Anda tahu politik, George Carlin adalah yang terbaik”.
Bila Anda pernah baca teks monolognya, “You Are All Diseased” (tayang di HBO), dan dipentaskan di sini, ia pasti akan diuber-uber laskar tertentu karena lelucon Carlin itu menanyakan secara kritis apa peranan agama dan bahkan peran Tuhan.
Nama lain yang muncul adalah Robin “Nano-Nano” Williams. Ada Chris Rock yang baru saja memandu acara Oscar 2005. Juga muncul nama Jim Carrey, yang membintangi film-film Ace Ventura. Pendapat untuk Jim Carry yang mukanya fleksibel mirip plastik itu : Jim Carrey wasn't very good in standup. The guy is funny to watch but his act doesn't hold up well without the visuals.. Jim Carrey tidak terlalu bagus bila tampil sebagai komedian solo. Ia lucu untuk dilihat tetapi aksinya tidak prima bila tanpa dibantu (efek) visual. Jim Carrey lucu bila di film, karena ada fasilitas close-up yang mampu mengarahkan penonton kepada ulah atau mimiknya yang luar biasa plastis itu.
Keinginan untuk lucu model Jim Carrey rupanya bikin mabuk kelompok Limau untuk main api malam itu. Ali Zainal Abidin, Sumono dan M.Furqon yang hendak memparodikan film/sinetron “Ada Apa dengan Cinta ?”, adalah pilihan beresiko. Karena karakter dalam tokoh-tokoh film/sinetron tersebut, walau populer, belumlah begitu berurat berakar dalam benak penonton. Apalagi memasukkan atau memaksakan karakter Jim Carrey dalam diri Mamet-nya “Ada Apa dengan Cinta ?”, siapa yang bisa ngeh dengan transformasi aneh semacam ini ?
Tetapi kelompok ini sudah memiliki kata sakti, “Kata Ustad Sanusi”, yang mampu memancing tawa. Tetapi kalau terlalu sering diulang-ulang dalam set-up yang kurang terjaga, maka punchline seperti ini akan mudah kehilangan magisnya.
CERDASNYA KANG IBING. Dari angka-angka polling, kelompoknya R. Asep Saefuloh, Meilia Balipa Emil dan Isa Wahyu Prastantyo yang alumni Komunikasi Universitas Indonusa Esa Unggul tahun2004 ini, nampak unggul. Pembuka adegannya Bajaj, yaitu monolog dengan alat bantu asesori telepon seluler, menarik walau bukan hal baru.
Komedian Shelley Berman yang masuk kelompok legendary comedian seangkatan Rodney Dangerfield sampai George Burns (biografi komedian gaek satu ini, George Burns and The Hundred Year Dash, 1996, pantas dibaca oleh para komedian) pernah pula melakukannya.
Saya tak habis heran, mereka pun yang anak Jakarta kini tertular penyakit asal Yogyakarta. Main plesetan. Maka ketika melawakkan judul-judul film, dan mereka bilang banyak film Indonesia menggunakan judul “buah-buhanan”, muncul kemudian : Malam Tomat Kliwon.
Kang Ibing, menyebut lawakan kelompok Bajaj yang suka bermain-main kata atau (pun) itu sebagai lawakan intelektual. Bahkan pemunculan secara mak benduduk kata tomat dari judul film tadi ia sebut sebagai lawakan cerdas.
Bolehlah. Siapa saja memang berhak berkomentar seputar bermain-main kata, pun, dalam lawakan. Termasuk pula pencipta lagu Amerika, Ira Gershwin (1896–1983), yang berkata bahwa permainan kata-kata merupakan bentuk terendah dari humor, the lowest form of wit.
Saya sih setuju sama pendapat Eyang Ira ini.
Bagaimana dengan Anda ?
Wonogiri, 24 Mei 2005
Oleh : Bambang Haryanto
Email : humorliner@yahoo.com
DRAKULA MENGEJAR BASUKI. Kemana pun Basuki lari ke pojok-pojok panggung, Drakula itu selalu mengejarnya. Kadang muncul suatu adegan saat Basuki justru meledek Drakula bersangkutan, yang dinilai terlalu lamban bergerak. Malam itu saya jadi saksi betapa panggung Anekaria Srimulat di Taman Ria Senayan, Jakarta, tahun 1980-an, riuh dengan gelak tawa.
Sebagai puncak uber-uberan Drakula vs Basuki berakhir ketika Basuki tak bisa menghindar. Ia terjatuh dengan gaya split, lalu menekuk kaki depannya, meniru adegan dalam pentas wayang orang untuk menyatakan takluk kepada fihak yang mengalahkannya. Gaya wayang orang dari Basuki ini meledakkan tawa. Khasanah gerak dari wayang orang yang secara tiba-tiba masuk dalam adegan pentas Srimulat, dan penonton pun memahaminya, itulah rumus mengapa ledakan tawa penonton segera riuh terjadi.
Tahu sama tahu. Pelawak tahu. Penonton pun tahu. Itulah rumus mati dari lawakan yang mengundang tawa. Sekali lagi saya tak bosan mengutip ucapan dari Gene Perret, kepala penulis lawakannya Bob Hope, yang menulis bahwa sense of humor menyangkut tiga keterampilan : (1) to see things as they are, melihat sesuatu apa adanya, (2) to recognize things as they are, memahami/mengerti sesuatu apa adanya, dan (3) to accept things as they are, menerima sesuatu apa adanya.
Sekadar contoh : awal Maret 2005, Erika Michiko, reporter yang cantik dari rumah produksi Shandika Widya Cinema bersama Sabar (kamerawan) dan Yanto (pengemudi) menyambangi rumah saya di Wonogiri. Mereka hendak mendokumentasikan kiprah saya sebagai seorang epistoholik, penulis surat-surat pembaca sejak tahun 1973, untuk tayangan Bussseeet di stasiun televisi swasta TV7. Hasil reportase itu telah ditayangkan 20/3/2005 dan 18/5/2005 yang lalu.
Setelah melewati tahap wawancara, lalu ditetapkan tema tayangan, syuting pun segera dimulai. Saat itu saya nyeletuk, “kini saatnya saya belajar bahasa visual”. Sabar dan Erika terdengar tertawa. Apa ada yang lucu, atau sengaja dibuat lucu, dari kalimat saya tadi ? Tidak ada, bukan ?
Urgensi dari kalimat “belajar bahasa visual” saya munculkan, karena saya faham bahwa memang terdapat perbedaan antara bahasa tulis dengan bahasa visual. Orang-orang media televisi pasti tahu. Erika dan Sabar juga tahu. Saya hanya melakukan callback sesuatu yang ia tahu. Tawa muncul dari formula tahu sama tahu itu.
Karena memang pemahaman tentang bahasa visual tersebut telah saya geluti dan saya ajarkan di tahun 1984. Saat itu saya menjadi asisten dosen untuk mata kuliah Teknologi Media di Jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Sastra (kini Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya) Universitas Indonesia, Jakarta.
Dengan melontarkan sesuatu konsep yang saya yakin juga juga difahami oleh audiens “lawakan” saya saat itu, dalam hal ini Erika dan Sabar, maka dengan murah hati mereka pun menyambutnya dengan tawa. Tahu sama tahu, sekali lagi, itu kuncinya.
Contoh lain : pengamat politik Eep Saefuloh yang baru saja menikahi presenter televisi Sandrina Malakiano, dalam suatu seminar, telah mengaitkan dirinya dengan peristiwa pembongkaran tindak korupsi di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Eep cerita, mungkin karena dirinya dikira sebagai orang KPU atau ada orang KPU yang mirip dirinya, ketika mengisi bensin ada seseorang yang nyeletuk : “Pak Eep, mobil Anda ini hasil dari dana taktis KPU, ya ? Dan kemarin bisa umroh, juga berkat dana dari sumber yang sama ya?”. Tentu saja, semua peserta seminar itu terbahak. Tahu sama tahu.
TETAPI NGELANTUR TIDAK TAHU. Kelompok lawak Ngelantur asal Waru Sidoarjo ini, hemat saya, dalam penampilannya di Kembang Api, 22 Mei 2005, tidak memerhatikan rumus tahu sama tahu tersebut. Trio Heri Suryanto, Totok Pranadi dan M. Isa tersebut akhirnya gosong malam itu. Padahal adegan awalnya, dialog dua orang, berpakaian biasa, yang melucukan kelompok-kelompok lawak pesaingnya, cukup menggelitik.
Tetapi begitu muncul tokoh ketiga, memakai pakaian, gerak-gerik dan mengenakan mahkota raja, penonton dibuat terkacau. Tidak ada lagi kesatuan konteks dalam adegan yang terjadi. Tidak mudah bagi penonton untuk memahami bagaimana sosok dua orang yang berpakaian masa kini tiba-tiba harus berinteraksi dengan seorang “raja”. Raja dari mana ? Memang sang “raja” itu terlihat bloon, berkali-kali menanyakan siapa jati dirinya, tetapi konteks dan dialog yang terjadi antara ketiganya sudah tidak mempunyai fondasi kuat lagi untuk memancing penonton untuk tertawa.
Kecelakaan yang nyaris serupa dialami oleh kelompok SOS dari Bandung. Dengan mengambil seting Romeo dan Juliet, bahkan sampai Sule (Sutisna) mau-maunya berpakaian model putri raja, memancing kontroversi. Pencela Basuki bilang, sebaiknya memakai seting cerita dalam negeri saja. Kalau demi alasan tahu sama tahu, saran Basuki ini layak diperhatikan.
Sementara itu pencela lainnya, Mang Ibing yang sarjana muda Sastra Rusia, menganggap kisah Romeo dan Juliet karya pujangga Inggris William Shakespeare sebagai humanisme universal. Cerita itu, katanya, adalah sastra dunia dan sudah menjadi milik semua bangsa. Keduanya, boleh jadi benar.
Tetapi dalam pentas lawakan, rumus tahu sama tahu, malam itu telah diteledorkan oleh trio Suwarman (Oni), Obin Wahyudin (Ogi) dan Sutisna (Sule) ini. Bahkan ketika Sule di awal adegan menyanyikan lagu Yen Ing Tawang, berbahasa Jawa, kekacauan konteks makin terasa menjadi-jadi.
JIM CARREY DARI TANGERANG. Di MSFN Forum pernah diluncurkan diskusi mengenai siapa stand-up comedian atau pelawak solo, yang terbaik. Nama-nama yang muncul banyak sekali dan beragam. Ada nama George Carlin, yang oleh salah satu pengusulnya diimbuhi pendapat, “bila Anda tahu politik, George Carlin adalah yang terbaik”.
Bila Anda pernah baca teks monolognya, “You Are All Diseased” (tayang di HBO), dan dipentaskan di sini, ia pasti akan diuber-uber laskar tertentu karena lelucon Carlin itu menanyakan secara kritis apa peranan agama dan bahkan peran Tuhan.
Nama lain yang muncul adalah Robin “Nano-Nano” Williams. Ada Chris Rock yang baru saja memandu acara Oscar 2005. Juga muncul nama Jim Carrey, yang membintangi film-film Ace Ventura. Pendapat untuk Jim Carry yang mukanya fleksibel mirip plastik itu : Jim Carrey wasn't very good in standup. The guy is funny to watch but his act doesn't hold up well without the visuals.. Jim Carrey tidak terlalu bagus bila tampil sebagai komedian solo. Ia lucu untuk dilihat tetapi aksinya tidak prima bila tanpa dibantu (efek) visual. Jim Carrey lucu bila di film, karena ada fasilitas close-up yang mampu mengarahkan penonton kepada ulah atau mimiknya yang luar biasa plastis itu.
Keinginan untuk lucu model Jim Carrey rupanya bikin mabuk kelompok Limau untuk main api malam itu. Ali Zainal Abidin, Sumono dan M.Furqon yang hendak memparodikan film/sinetron “Ada Apa dengan Cinta ?”, adalah pilihan beresiko. Karena karakter dalam tokoh-tokoh film/sinetron tersebut, walau populer, belumlah begitu berurat berakar dalam benak penonton. Apalagi memasukkan atau memaksakan karakter Jim Carrey dalam diri Mamet-nya “Ada Apa dengan Cinta ?”, siapa yang bisa ngeh dengan transformasi aneh semacam ini ?
Tetapi kelompok ini sudah memiliki kata sakti, “Kata Ustad Sanusi”, yang mampu memancing tawa. Tetapi kalau terlalu sering diulang-ulang dalam set-up yang kurang terjaga, maka punchline seperti ini akan mudah kehilangan magisnya.
CERDASNYA KANG IBING. Dari angka-angka polling, kelompoknya R. Asep Saefuloh, Meilia Balipa Emil dan Isa Wahyu Prastantyo yang alumni Komunikasi Universitas Indonusa Esa Unggul tahun2004 ini, nampak unggul. Pembuka adegannya Bajaj, yaitu monolog dengan alat bantu asesori telepon seluler, menarik walau bukan hal baru.
Komedian Shelley Berman yang masuk kelompok legendary comedian seangkatan Rodney Dangerfield sampai George Burns (biografi komedian gaek satu ini, George Burns and The Hundred Year Dash, 1996, pantas dibaca oleh para komedian) pernah pula melakukannya.
Saya tak habis heran, mereka pun yang anak Jakarta kini tertular penyakit asal Yogyakarta. Main plesetan. Maka ketika melawakkan judul-judul film, dan mereka bilang banyak film Indonesia menggunakan judul “buah-buhanan”, muncul kemudian : Malam Tomat Kliwon.
Kang Ibing, menyebut lawakan kelompok Bajaj yang suka bermain-main kata atau (pun) itu sebagai lawakan intelektual. Bahkan pemunculan secara mak benduduk kata tomat dari judul film tadi ia sebut sebagai lawakan cerdas.
Bolehlah. Siapa saja memang berhak berkomentar seputar bermain-main kata, pun, dalam lawakan. Termasuk pula pencipta lagu Amerika, Ira Gershwin (1896–1983), yang berkata bahwa permainan kata-kata merupakan bentuk terendah dari humor, the lowest form of wit.
Saya sih setuju sama pendapat Eyang Ira ini.
Bagaimana dengan Anda ?
Wonogiri, 24 Mei 2005
Wednesday, May 18, 2005
Humor Amerika, Rusia, Cina, Indonesia
Oleh : Harry Tekssi*
PKJT Sasonomulyo Solo
I
MENDIANG PRESIDEN KENNEDY yang konon pernah digunjing akibat kisah-kisah asmaranya, baik ketika hidup mau pun sesudah mengalami hari naas di Dallas, kisahnya tak luput dijadikan bahan humor. Ketika masih hidup, antara lain pada suatu jumpa pers 15 Februari 1962, beliau mengkhawatirkan akan timbulnya suatu gegeran sosial di negerinya akibat otomatisasi.
“Tantangan di dalam negeri yang besar pada tahun enampuluhan ini”, begitu kata dia, “adalah usaha mempertahankankan secara penuh lapangan kerja apabila otomatisasi telah menggantikan kerja-kerja manusia”
Di sini sang dedengkot The New York Times, James Reston, nyeletuklah : “Mesin-mesin nampaknya akan menggantikan segalanya di negeri ini kecuali mungkin hanya cewek-cewek cakep body asoy dan Presiden Kennedy sangat mengkhawatirkan hal ini”
Cerita lain diambil dari satu adegan film Nashville karya sutradara Robert Altman : ketika tiba-tiba seorang penyanyi di panggung ditembak mati oleh seorang gila. Sang korban itu, anehnya, beberapa saat kemudian terbangun lagi, hidup kembali. Malah teriak keras-keras, “Saudara-saudara, ini bukanlah Dallas. Ini Nashville”
HUMOR-HUMOR DARI NEGERI SAYAP KIRI juga ada. Banyak. Dan terutama yang berasal dari balik Tirai Besi pada hemat saya adalah lebih kaya dan lebih menggelitik. Lebih manjur, cespleng begitulah, yang mungkin karena mereka mempunyai basis penguat ! Humor-humor mereka adalah justru berangkat dari kesedihan, barangkali hidup yang pahit. “Rusia sebegitu jauh telah menghapus Tuhan, tetapi Tuhan sebegitu jauh masih lebih toleran”
Yah, memang. Seperti halnya Mark Twain yang dikutip Alfons Taryadi dalam Kompas, “sumber tersembunyi humor bukanlah keriangan melainkan kesedihan. Di Sorga tak ada humor” – (maka) di negeri “agama adalah candu” rasanya kita bisa menerima bahwa humor relevan subur bermunculan. Terlebih lagi, mungkin (!), ini akibat Rusia sendiri telah menghapus Tuhan, sementara yang namanya Sorga bukankah cuman hak patent milik Tuhan ? Di Sorga toh tak ada humor.
“Kalau bangsa Amerika memiliki Mafia, kami bangsa Rusia juga mempunyainya. Namanya : Pemerintah”
Atau yang jenis ini, satu lagi pil pahit. Bungkusnya tentu saja humor. Suatu malam pintu rumah seorang petani Rusia terdengar diketuk orang. “Siapa di luar ?”, sapa Pak Tani dengan cemas. Was-was. “Saya Malaikat Pencabut Nyawa !” Dada Pak Tani terasa longgar kemudian melepaskan nafas panjang, nafas lega. “Sokurlah, sokurlah, mari silakan masuk. Saya kira Anda polisi rahasia”
HUMOR MENGENAI FILSAFAT DASAR NEGERI RUSIA ? Mari, dan dimulai dengan mengutip apa yang dicatat oleh The Listener dari Inggris, saya baca kemudian dari majalah Readers Digest :
Apa itu filsafat ? Ialah kucing hitam di dalam kamar gelap. Lalu, apa itu filsafat Marxist ? Ialah kamar yang gelap di mana Anda mencari kucing hitam, sedang kucing tersebut sebenarnya tidak ada. Kalau filsafat Marxist-Leninist bagaimana pula ? Jawabnya : adalah kamar yang gelap di mana Anda mencari kucing hitam di dalamnya sedang kucing itu sebenarnya tidak ada – tetapi Anda tetap berteriak keras-keras : ‘Ini kucingnya, aku mendapatkannya !’ “
RUSIA DAN PULA ISRAEL, ras bangsa Skot atau pun negeri Cina merupakan bangsa-bangsa yang sering kita dengar punya humor-humor khas yang sanggup membuat perut kita keras. Ini lagi satu kisah dari negeri ketua Mao ketika mendapat kunjungan Presiden Amerika. Kalu tak khilap, Presiden Eisenhower.
Beliau asal negeri Sayap Kanan ini memang disambut hangat ketika mendarat di ibukota negeri Sayap Kiri ala Mao itu, Peking. Tetapi di antara sambutan hangat itu ada sesuatu yang aneh : penduduk Peking menyambut tanpa disertai secercah pun sungging senyum. “Mengapa begitu, Komrade ?” tanya pak Eisenhower.
A-ha, Ketua Mao rupanya sudah siaga kung-fu untuk melakukan loncatan jauh ke depan, memberi tendang balas yang jitu. “Waktu jaman Long March dahulu demi untuk menghilangkan rasa kelaparan, rakyat kami selalu saja berusaha tertawa. Dan sekarang ? Anda kini jadi saksi, mereka tidak tertawa lagi”
II
BAGAIMANA TENTANG BANGSA KITA ? Adalah pak Mochtar Lubis yang baru-baru saja meletuskan humor tentang Indonesia. Bahwa nabi Adam dan Ibu Hawa itu orang asli Indonesia. Punya ciri kuat sebagai jembel, hanya punya tiga hal –buah khuldi, ular dan telanjang—tetapi mengira bahwa hidupnya sudah kayak di Firdaus saja.
Atau lagi, bahwa orang Indonesia masa kini, kata orang, punya tiga kecenderungan serentak : memakai pakaian model masa lampau, memakai mobil model masa kini, menghabiskan biaya masa depan.
Pengin dengar humor tentang Indonesia yang rodo-rodo memakai unsur internasional ? Ini dia. Adalah kata sahibul hikayat berbincanglah tiga orang : Amerika, Jepang dan Indonesia. Bertiga saling pamer kelebihan negeri masing-masing.
“Neil Armstrong yang mendarat di bulan adalah lambang supremasi kesuperioran negeri kami”, si Amerika memulai. “Ia bisa mendarat dengan tepat di permukaan bulan pada satu tempat yang sudah lama direncanakan”
“Apa memang tepat benar ?”, sanggah si Jepang dan Indonesia getas.
“Yeaah. Ya tidak tepat benar”, kilah Paman Sam. “Selisih jarak lokasi yang didarati dan yang direncanakan ada sekitar seratus meter”
Gantian si Jepang. “Negeri Anda berdua punya bullet train ? “. Si Indonesia gemas. Si Amerika gemas. “Kereta kami itu sanggup berangkat dari satu stasiun dan secara otomatis nanti kembali tepat pada lokasi ketika berangkatnya !”
“Apa memang tepat benar ?”, kini Amerika menyerbu. Indonesia diam.
“Ah, ya memang tidak tepat benar”, elak si Jepang. “Selisihnya ada sekitar barang dua-tiga meter”.
Kini, ini dia, Indonesia ganti berdiri. “Anda berdua pernanh dengar bahwa di Indonesia ada orang sanggup melahirkan anak lewat dubur ?”. Paman Sam kaget. Si Jepang kaget. Sama-sama setengah mati. Was-was. Kalau-kalau teknologi medis mereka telah tersaingi.
“Apa memang tepat benar itu ?” Paman Sam menyerbu dengan tinju, Jepang dengan mawashi-geri model karate. Si Indonesia sih kalem-kalem saja : “Ya, tidaklah tepat benar. Ada selisih kurang dari sepersepuluh meter”.
III
SEBEGITU JAUH JENIS HUMOR YANG LAIN, misal tentang pemerintah atau kebijaksanaan politiknya, adalah masih tabu. Atau terbatas, terisolir di antara gedung-gedung parlemen. Atau mungkin karena terlalu riskan.
Contoh kita selama ini yang berani ambil resiko adalah dramawan Rendra. Ia “maestro”, walau ia diperbolehkan berbagi humor dengan publik cuman di kawasan “bagian Republik Indonesia yang paling merdeka” : TIM, Jakarta. Bahkan sebelum masa akhir-akhir ini, ia dilarang meledek di kota asalnya : Yogya. Malah di kota tempat lahirnya, Solo, poster wajahnya kena coret. Di-la-rang !
Sokur saja humor itu sendiri tetap ada. Kita tahu sendiri, kita mengalami sendiri. Baik karton crude Johnny Hidayat di (majalah) STOP mau pun jenis model reog BKAK di televisi. Atau, kita kenal akan tokoh Pak Basiyo dari Yogya yang hemat saya benar-benar “maestro” plus piawai berhumor sealur logika bisosiasi yang ditawarkan oleh seorang Arthur Koestler. Silakan dengar seri kasetnya, sayang hanya dalam bahasa Jawa, untuk berhura-hura.
KITA KINI MEMANG JADI SAKSI, kita tahu sendiri : yang sangat laris adalah humor dalam peran sebagai alat penghibur. Sebagai jongos, kata pak Arwah Setiawan. Alias penekunan humor sebagai salah satu di antara tiga kawasan kreativitas, di samping kesenian dan ilmu pengetahuan, masih ngenas. Sisi peran humor yang antara lain sebagai alat koreksi, kritik, rupanya memang masih dililit masalah di sana-sini.
Kenapa ?
Atau memang, kita-kita ini tidak percaya dan tidak peka terhadap humor dalam peran sebagai kritik ? Siapa bisa menjawab. Tetapi semoga saya diijinkan untuk condong meng-ya-kan, bahwa kita toh masih punya humor, humor soliloquy, humor percakapan sendiri. Dengan arti, betahlah untuk sementara (atau selamanya ?) kita-kita ini untuk sabar terpusar dalam situasi “katastrophe” yang tersurat dari puisi Taufik Ismail :
PENDERITAAN
Berakit-rakit ke hulu
berenang-renang ke tepian,
Bersakit-sakit dahulu,
bersakit-sakit berkepanjangan
Hingga dalam melulu “bersakit-sakit berkepanjangan” itu toh otomatis kita masih terus bisa berhumor bukan ? Sebab, di sorga tak ada humor. Di sorga tak perlu ada kritik. Dengan humorlah kita bisa menyalurkan rasa bersakit-sakit seirama buku biru Arthur Koestler, The Act of Creation, yang pernyataannya senada Freud : humor justru merupakan pengganti kekerasan, penyalur nafsu-nafsu agresif dalam jiwa manusia.
MARI BERHIMPUN. HIDUP LHI. MARI TERTAWA, tertawa itu pengobat paling mujarab, kata Readers Digest. Dan lagi, menertawai diri sendiri kata petuah, merupakan satu kebajikan.
Ini dia, lagi puisi Taufik Ismail yang lain, kiranya bisa berjasa mengendorkan saraf-saraf kita, jidat kerut merut kita dewasa ini :
BAGAIMANA KALAU
Bagaimana kalau dulu bukan khuldi yang dimakan Adam, tapi buah alpukat.
Bagaimana kalau bumi bukan bulat, tetapi segi empat.
Bagiamana kalau lagu Indonesia Raya kita rubah, dan kepada Koes Plus kita beri mandat.
Bagaimana kalau ibukota Amerika Hanoi, dan ibukota Indonesia Monaco.
Bagaimana kalau malam nanti jam sebelas, salju turun di Gunung Sahari.
Bagiamna kalau bisa dibuktikan bahwa Ali Murtopo, Ali Sadikin dan Ali Wardhana ternyata pengarang-pengarang lagu pop.
Bagaimana kalau hutang-hutang Indonesia dibayar dengan pementasan Rendra.
Bagaimana kalau segala yang kita angankan terjadi, dan segala yang terjadi pernah kita rancangkan.
Bagaimana kalau akustik dunia jadi sedemikian sempurnanya sehingga di kamar tidur kau sampai deru bom Vietnam, gemersik sejuta kaki pengungsi, gemuruh banjir dan gempa bumi serta suara-suara percintaan anak muda, juga bunyi industri persisi dan margasatwa Afrika.
Bagaimana kalau pemerintah diizinkan protes dan rakyat kecil mempertimbangkan protes itu.
Bagaimana kalau kesenian dihentikan saja sampai di sini dan kita pelihara ternak sebagai pengganti.
Bagaimana kalau sampai waktunya kita tidak perlu bertanya bagaimana lagi.
(1971)
BAGAIMANA KALAU sampai waktunya kita tidak perlu bertanya bagaimana lagi ? Tertawa saja hingga dunia ikut tertawa, sebab menangislah maka kamu akan menangis sendirian saja.
Bagaimana kalau sampai waktunya kita tidak perlu bertanya bagaimana kok tidak tertawa lagi ? Mari menangis, dalam tertawa. Atau : kita pilih serempak diam bagai mulut botol kena sumbat ? Tetapi ingat, diam jenis ini adalah “sunyi bagai dunia bisik”.
Atau mungkin kita lebih memilih : kritik yang tanpa kata. Atau, situasi sebar luasnya virus apatis yang nurut kata sementara Bapak ia berbahaya bagi kesinambungan dan kelanggengan hidup bernegara. Atau, pilih saja pola kebudayaan sas-sus hingga kita biar mudah terseret dalam situasi absurd ?
Memang. Apabila dalam situasi serba rancau bahasa, absurd, jelasnya bila menurut dramawan Eugene Ionesco adalah situasi tragedi bahasa, kritik atau pun kritik humor rasanya orang sangat ciut nyali untuk mendendangkannya. Maka adalah seorang Martin Esslin ketika memperbincangkan ihwal Teater Absurd ia mengutip apa arti “absurd” sebagaimana yang dikatakan oleh Ionesco, sebagai berikut :
What is sometimes labeled the absurd, is only denunciation or the ridiculous nature of language which is empty substance, made up cliches and slogans.
Ya. Betapa mengerikan bila bahasa telah hanya merupakan bangunan klise-klise dan slogan-slogan belaka.
Adalah Goenawan Mohamad mengatakan di antara bagian kredonya yang terkenal, Potret Seorang Penyair Muda Sebagai Si Malin Kundang, berkenaan situasi tragedi bahasa atau “...suatu bahasa otomatik yang dimaksudkan Ionesco (adalah sbb : - HT) dengan apa pembicaraan dari hati ke hati menjadi sulit, dengan apa diskusi menjadi kandas, dengan apa telaah perundang-undangan hampir mustahil...Tapi apa lagikah yang tinggal apabila kata kontra revolusioner (bisa diganti : subversif, mengganggu kestabilan nasional, etc – HT) yang tak jelas pengertiannya itu sudah cukup untuk membunuh orang ?”
ITULAH MAKANYA, dalam situasi tersebut –sesudah semacam keterusterangan dan semacam humor alegori—satu kritik, kritik humor besar kemungkinan mudah ditarik ke dalam pengertian “lebih condong kepada baik buruknya konotasi daripada kepersisan definisi” : mengganggu kestabilan nasional.
Seseorang di Surabaya, Aceh, Sangir talaud, Bandung, Yogya atau Jakarta sesudah sama-sama membaca kisah Nasarudin Hoja pada majalah anak-anak Kawanku, lalu sama-sama berbincang kejenakaannya, sama serentak terbahak, dalam kemelut tragedi bahasa mungkin sekali semua himpunan pencandu Hoja bisa kena vonis yang mengecutkan hati itu.
Semoga saja tidak. Atau, belum tidak ? Kalau pun ya, ya memang sudah suratan nasib : kita semua akan menikmati seperti apa yang dimaui oleh seorang jenderal Amerika, Phillip H. Sheridan (1855) mengenai negeri Texas. “Bila saja aku memiliki Texas dan sekaligus Neraka, maka Texas akan aku sewakan saja dan aku lebih baik tinggal berdiam di Neraka”
IV
INDONESIA 1978 TENTU SAJA BUKAN TEXAS 1855. Bukan pula neraka. Melainkan, Come ! Beautiful Islands. And the welcome await you when you make trip to Indonesia, begitu iklan GIA di Time. Dan sementara iklan di AI (Amnesty International) dan IPI (International Press Institute), pfuah, itu urusan orang lain yang usil.
Bagi kita, yang sudah terbiasa “penderitaan dan kemiskinan adalah pengalaman sehari-hari. Asketisme (yang bukan a la biara) ini sudah mendarah daging” (T.H. Sumartana, “Cara Kita Menahan Derita”, TEMPO, 15 Oktober 1977), negeri kita (sekali lagi) bukan Texas-nya Sheridan di atas. Kita semua nampak masih sabar menunggu, masih nampak sabar selalu, merasa betah dengan hidup ini. Dan kata orang, itulah optimisme !
Jadi umpama pun kena serbu senewen-senewen dikit, tak apalah, pusing-pusing sedikit, bukankah “Keluarga Sejahtera Indonesia 1978” menawarkan Inza ? Mules-mules dikit akibat HO atau KM ? Kencangin ikat pinggang ! Dan bila pun tuli-tuli sedikit, apa “Keluarga Sejahtera Indonesia 1978” tidak kenal King Aid ?
Ya. Sebab kita semua maklum bahwa para guru pengambil kebijaksanaan, yang di atas-atas sana itu atau paduka-paduka semacamnya itu, sudah sangat pasti bahwa beliau-beliau perlu diberi kasihan. Karena lebih dulu dan lebih banyak kena serbu macam-macam rasa tak enak ketimbang kita yang biasa-biasa saja ini.
Adalah cerita Marie Fraser di Indiana Teacher, saya temui di Readers Digest (1966). Ini dia :
Di luar bangunan Istana Christianborg, yaitu Gedung Parlemen Denmark di Kopenhagen, terdapat tiga patung yang mengawal pintu gerbangnya. Patung tersebut melambangkan tokoh : orang yang lagi pusing-pusing kepalanya, orang yang mulas-mulas perutnya, dan orang yang tuli (!) pendengarannya.
“Ketiga patung tersebut menyarankan pada Anda”, tutur orang Denmark sambil senyum sayur asam, “Bahwa bila Anda memasuki kancah politik maka Anda pasti akan mengidap penyakit itu ketiga-tiganya”.
* Harry Tekssi adalah nama aktivis kesenian dari Bambang Haryanto pada tahun 1970-an, di lingkungan PKJT (Pusat Kebudayaan Jawa Tengah), Sasonomulyo, Solo. Artikel ini telah dimuat di majalah Semangat (Yogyakarta), No. 10, Juni 1978 : 18-20.
Wonogiri, 18-19 Mei 2005
PKJT Sasonomulyo Solo
I
MENDIANG PRESIDEN KENNEDY yang konon pernah digunjing akibat kisah-kisah asmaranya, baik ketika hidup mau pun sesudah mengalami hari naas di Dallas, kisahnya tak luput dijadikan bahan humor. Ketika masih hidup, antara lain pada suatu jumpa pers 15 Februari 1962, beliau mengkhawatirkan akan timbulnya suatu gegeran sosial di negerinya akibat otomatisasi.
“Tantangan di dalam negeri yang besar pada tahun enampuluhan ini”, begitu kata dia, “adalah usaha mempertahankankan secara penuh lapangan kerja apabila otomatisasi telah menggantikan kerja-kerja manusia”
Di sini sang dedengkot The New York Times, James Reston, nyeletuklah : “Mesin-mesin nampaknya akan menggantikan segalanya di negeri ini kecuali mungkin hanya cewek-cewek cakep body asoy dan Presiden Kennedy sangat mengkhawatirkan hal ini”
Cerita lain diambil dari satu adegan film Nashville karya sutradara Robert Altman : ketika tiba-tiba seorang penyanyi di panggung ditembak mati oleh seorang gila. Sang korban itu, anehnya, beberapa saat kemudian terbangun lagi, hidup kembali. Malah teriak keras-keras, “Saudara-saudara, ini bukanlah Dallas. Ini Nashville”
HUMOR-HUMOR DARI NEGERI SAYAP KIRI juga ada. Banyak. Dan terutama yang berasal dari balik Tirai Besi pada hemat saya adalah lebih kaya dan lebih menggelitik. Lebih manjur, cespleng begitulah, yang mungkin karena mereka mempunyai basis penguat ! Humor-humor mereka adalah justru berangkat dari kesedihan, barangkali hidup yang pahit. “Rusia sebegitu jauh telah menghapus Tuhan, tetapi Tuhan sebegitu jauh masih lebih toleran”
Yah, memang. Seperti halnya Mark Twain yang dikutip Alfons Taryadi dalam Kompas, “sumber tersembunyi humor bukanlah keriangan melainkan kesedihan. Di Sorga tak ada humor” – (maka) di negeri “agama adalah candu” rasanya kita bisa menerima bahwa humor relevan subur bermunculan. Terlebih lagi, mungkin (!), ini akibat Rusia sendiri telah menghapus Tuhan, sementara yang namanya Sorga bukankah cuman hak patent milik Tuhan ? Di Sorga toh tak ada humor.
“Kalau bangsa Amerika memiliki Mafia, kami bangsa Rusia juga mempunyainya. Namanya : Pemerintah”
Atau yang jenis ini, satu lagi pil pahit. Bungkusnya tentu saja humor. Suatu malam pintu rumah seorang petani Rusia terdengar diketuk orang. “Siapa di luar ?”, sapa Pak Tani dengan cemas. Was-was. “Saya Malaikat Pencabut Nyawa !” Dada Pak Tani terasa longgar kemudian melepaskan nafas panjang, nafas lega. “Sokurlah, sokurlah, mari silakan masuk. Saya kira Anda polisi rahasia”
HUMOR MENGENAI FILSAFAT DASAR NEGERI RUSIA ? Mari, dan dimulai dengan mengutip apa yang dicatat oleh The Listener dari Inggris, saya baca kemudian dari majalah Readers Digest :
Apa itu filsafat ? Ialah kucing hitam di dalam kamar gelap. Lalu, apa itu filsafat Marxist ? Ialah kamar yang gelap di mana Anda mencari kucing hitam, sedang kucing tersebut sebenarnya tidak ada. Kalau filsafat Marxist-Leninist bagaimana pula ? Jawabnya : adalah kamar yang gelap di mana Anda mencari kucing hitam di dalamnya sedang kucing itu sebenarnya tidak ada – tetapi Anda tetap berteriak keras-keras : ‘Ini kucingnya, aku mendapatkannya !’ “
RUSIA DAN PULA ISRAEL, ras bangsa Skot atau pun negeri Cina merupakan bangsa-bangsa yang sering kita dengar punya humor-humor khas yang sanggup membuat perut kita keras. Ini lagi satu kisah dari negeri ketua Mao ketika mendapat kunjungan Presiden Amerika. Kalu tak khilap, Presiden Eisenhower.
Beliau asal negeri Sayap Kanan ini memang disambut hangat ketika mendarat di ibukota negeri Sayap Kiri ala Mao itu, Peking. Tetapi di antara sambutan hangat itu ada sesuatu yang aneh : penduduk Peking menyambut tanpa disertai secercah pun sungging senyum. “Mengapa begitu, Komrade ?” tanya pak Eisenhower.
A-ha, Ketua Mao rupanya sudah siaga kung-fu untuk melakukan loncatan jauh ke depan, memberi tendang balas yang jitu. “Waktu jaman Long March dahulu demi untuk menghilangkan rasa kelaparan, rakyat kami selalu saja berusaha tertawa. Dan sekarang ? Anda kini jadi saksi, mereka tidak tertawa lagi”
II
BAGAIMANA TENTANG BANGSA KITA ? Adalah pak Mochtar Lubis yang baru-baru saja meletuskan humor tentang Indonesia. Bahwa nabi Adam dan Ibu Hawa itu orang asli Indonesia. Punya ciri kuat sebagai jembel, hanya punya tiga hal –buah khuldi, ular dan telanjang—tetapi mengira bahwa hidupnya sudah kayak di Firdaus saja.
Atau lagi, bahwa orang Indonesia masa kini, kata orang, punya tiga kecenderungan serentak : memakai pakaian model masa lampau, memakai mobil model masa kini, menghabiskan biaya masa depan.
Pengin dengar humor tentang Indonesia yang rodo-rodo memakai unsur internasional ? Ini dia. Adalah kata sahibul hikayat berbincanglah tiga orang : Amerika, Jepang dan Indonesia. Bertiga saling pamer kelebihan negeri masing-masing.
“Neil Armstrong yang mendarat di bulan adalah lambang supremasi kesuperioran negeri kami”, si Amerika memulai. “Ia bisa mendarat dengan tepat di permukaan bulan pada satu tempat yang sudah lama direncanakan”
“Apa memang tepat benar ?”, sanggah si Jepang dan Indonesia getas.
“Yeaah. Ya tidak tepat benar”, kilah Paman Sam. “Selisih jarak lokasi yang didarati dan yang direncanakan ada sekitar seratus meter”
Gantian si Jepang. “Negeri Anda berdua punya bullet train ? “. Si Indonesia gemas. Si Amerika gemas. “Kereta kami itu sanggup berangkat dari satu stasiun dan secara otomatis nanti kembali tepat pada lokasi ketika berangkatnya !”
“Apa memang tepat benar ?”, kini Amerika menyerbu. Indonesia diam.
“Ah, ya memang tidak tepat benar”, elak si Jepang. “Selisihnya ada sekitar barang dua-tiga meter”.
Kini, ini dia, Indonesia ganti berdiri. “Anda berdua pernanh dengar bahwa di Indonesia ada orang sanggup melahirkan anak lewat dubur ?”. Paman Sam kaget. Si Jepang kaget. Sama-sama setengah mati. Was-was. Kalau-kalau teknologi medis mereka telah tersaingi.
“Apa memang tepat benar itu ?” Paman Sam menyerbu dengan tinju, Jepang dengan mawashi-geri model karate. Si Indonesia sih kalem-kalem saja : “Ya, tidaklah tepat benar. Ada selisih kurang dari sepersepuluh meter”.
III
SEBEGITU JAUH JENIS HUMOR YANG LAIN, misal tentang pemerintah atau kebijaksanaan politiknya, adalah masih tabu. Atau terbatas, terisolir di antara gedung-gedung parlemen. Atau mungkin karena terlalu riskan.
Contoh kita selama ini yang berani ambil resiko adalah dramawan Rendra. Ia “maestro”, walau ia diperbolehkan berbagi humor dengan publik cuman di kawasan “bagian Republik Indonesia yang paling merdeka” : TIM, Jakarta. Bahkan sebelum masa akhir-akhir ini, ia dilarang meledek di kota asalnya : Yogya. Malah di kota tempat lahirnya, Solo, poster wajahnya kena coret. Di-la-rang !
Sokur saja humor itu sendiri tetap ada. Kita tahu sendiri, kita mengalami sendiri. Baik karton crude Johnny Hidayat di (majalah) STOP mau pun jenis model reog BKAK di televisi. Atau, kita kenal akan tokoh Pak Basiyo dari Yogya yang hemat saya benar-benar “maestro” plus piawai berhumor sealur logika bisosiasi yang ditawarkan oleh seorang Arthur Koestler. Silakan dengar seri kasetnya, sayang hanya dalam bahasa Jawa, untuk berhura-hura.
KITA KINI MEMANG JADI SAKSI, kita tahu sendiri : yang sangat laris adalah humor dalam peran sebagai alat penghibur. Sebagai jongos, kata pak Arwah Setiawan. Alias penekunan humor sebagai salah satu di antara tiga kawasan kreativitas, di samping kesenian dan ilmu pengetahuan, masih ngenas. Sisi peran humor yang antara lain sebagai alat koreksi, kritik, rupanya memang masih dililit masalah di sana-sini.
Kenapa ?
Atau memang, kita-kita ini tidak percaya dan tidak peka terhadap humor dalam peran sebagai kritik ? Siapa bisa menjawab. Tetapi semoga saya diijinkan untuk condong meng-ya-kan, bahwa kita toh masih punya humor, humor soliloquy, humor percakapan sendiri. Dengan arti, betahlah untuk sementara (atau selamanya ?) kita-kita ini untuk sabar terpusar dalam situasi “katastrophe” yang tersurat dari puisi Taufik Ismail :
PENDERITAAN
Berakit-rakit ke hulu
berenang-renang ke tepian,
Bersakit-sakit dahulu,
bersakit-sakit berkepanjangan
Hingga dalam melulu “bersakit-sakit berkepanjangan” itu toh otomatis kita masih terus bisa berhumor bukan ? Sebab, di sorga tak ada humor. Di sorga tak perlu ada kritik. Dengan humorlah kita bisa menyalurkan rasa bersakit-sakit seirama buku biru Arthur Koestler, The Act of Creation, yang pernyataannya senada Freud : humor justru merupakan pengganti kekerasan, penyalur nafsu-nafsu agresif dalam jiwa manusia.
MARI BERHIMPUN. HIDUP LHI. MARI TERTAWA, tertawa itu pengobat paling mujarab, kata Readers Digest. Dan lagi, menertawai diri sendiri kata petuah, merupakan satu kebajikan.
Ini dia, lagi puisi Taufik Ismail yang lain, kiranya bisa berjasa mengendorkan saraf-saraf kita, jidat kerut merut kita dewasa ini :
BAGAIMANA KALAU
Bagaimana kalau dulu bukan khuldi yang dimakan Adam, tapi buah alpukat.
Bagaimana kalau bumi bukan bulat, tetapi segi empat.
Bagiamana kalau lagu Indonesia Raya kita rubah, dan kepada Koes Plus kita beri mandat.
Bagaimana kalau ibukota Amerika Hanoi, dan ibukota Indonesia Monaco.
Bagaimana kalau malam nanti jam sebelas, salju turun di Gunung Sahari.
Bagiamna kalau bisa dibuktikan bahwa Ali Murtopo, Ali Sadikin dan Ali Wardhana ternyata pengarang-pengarang lagu pop.
Bagaimana kalau hutang-hutang Indonesia dibayar dengan pementasan Rendra.
Bagaimana kalau segala yang kita angankan terjadi, dan segala yang terjadi pernah kita rancangkan.
Bagaimana kalau akustik dunia jadi sedemikian sempurnanya sehingga di kamar tidur kau sampai deru bom Vietnam, gemersik sejuta kaki pengungsi, gemuruh banjir dan gempa bumi serta suara-suara percintaan anak muda, juga bunyi industri persisi dan margasatwa Afrika.
Bagaimana kalau pemerintah diizinkan protes dan rakyat kecil mempertimbangkan protes itu.
Bagaimana kalau kesenian dihentikan saja sampai di sini dan kita pelihara ternak sebagai pengganti.
Bagaimana kalau sampai waktunya kita tidak perlu bertanya bagaimana lagi.
(1971)
BAGAIMANA KALAU sampai waktunya kita tidak perlu bertanya bagaimana lagi ? Tertawa saja hingga dunia ikut tertawa, sebab menangislah maka kamu akan menangis sendirian saja.
Bagaimana kalau sampai waktunya kita tidak perlu bertanya bagaimana kok tidak tertawa lagi ? Mari menangis, dalam tertawa. Atau : kita pilih serempak diam bagai mulut botol kena sumbat ? Tetapi ingat, diam jenis ini adalah “sunyi bagai dunia bisik”.
Atau mungkin kita lebih memilih : kritik yang tanpa kata. Atau, situasi sebar luasnya virus apatis yang nurut kata sementara Bapak ia berbahaya bagi kesinambungan dan kelanggengan hidup bernegara. Atau, pilih saja pola kebudayaan sas-sus hingga kita biar mudah terseret dalam situasi absurd ?
Memang. Apabila dalam situasi serba rancau bahasa, absurd, jelasnya bila menurut dramawan Eugene Ionesco adalah situasi tragedi bahasa, kritik atau pun kritik humor rasanya orang sangat ciut nyali untuk mendendangkannya. Maka adalah seorang Martin Esslin ketika memperbincangkan ihwal Teater Absurd ia mengutip apa arti “absurd” sebagaimana yang dikatakan oleh Ionesco, sebagai berikut :
What is sometimes labeled the absurd, is only denunciation or the ridiculous nature of language which is empty substance, made up cliches and slogans.
Ya. Betapa mengerikan bila bahasa telah hanya merupakan bangunan klise-klise dan slogan-slogan belaka.
Adalah Goenawan Mohamad mengatakan di antara bagian kredonya yang terkenal, Potret Seorang Penyair Muda Sebagai Si Malin Kundang, berkenaan situasi tragedi bahasa atau “...suatu bahasa otomatik yang dimaksudkan Ionesco (adalah sbb : - HT) dengan apa pembicaraan dari hati ke hati menjadi sulit, dengan apa diskusi menjadi kandas, dengan apa telaah perundang-undangan hampir mustahil...Tapi apa lagikah yang tinggal apabila kata kontra revolusioner (bisa diganti : subversif, mengganggu kestabilan nasional, etc – HT) yang tak jelas pengertiannya itu sudah cukup untuk membunuh orang ?”
ITULAH MAKANYA, dalam situasi tersebut –sesudah semacam keterusterangan dan semacam humor alegori—satu kritik, kritik humor besar kemungkinan mudah ditarik ke dalam pengertian “lebih condong kepada baik buruknya konotasi daripada kepersisan definisi” : mengganggu kestabilan nasional.
Seseorang di Surabaya, Aceh, Sangir talaud, Bandung, Yogya atau Jakarta sesudah sama-sama membaca kisah Nasarudin Hoja pada majalah anak-anak Kawanku, lalu sama-sama berbincang kejenakaannya, sama serentak terbahak, dalam kemelut tragedi bahasa mungkin sekali semua himpunan pencandu Hoja bisa kena vonis yang mengecutkan hati itu.
Semoga saja tidak. Atau, belum tidak ? Kalau pun ya, ya memang sudah suratan nasib : kita semua akan menikmati seperti apa yang dimaui oleh seorang jenderal Amerika, Phillip H. Sheridan (1855) mengenai negeri Texas. “Bila saja aku memiliki Texas dan sekaligus Neraka, maka Texas akan aku sewakan saja dan aku lebih baik tinggal berdiam di Neraka”
IV
INDONESIA 1978 TENTU SAJA BUKAN TEXAS 1855. Bukan pula neraka. Melainkan, Come ! Beautiful Islands. And the welcome await you when you make trip to Indonesia, begitu iklan GIA di Time. Dan sementara iklan di AI (Amnesty International) dan IPI (International Press Institute), pfuah, itu urusan orang lain yang usil.
Bagi kita, yang sudah terbiasa “penderitaan dan kemiskinan adalah pengalaman sehari-hari. Asketisme (yang bukan a la biara) ini sudah mendarah daging” (T.H. Sumartana, “Cara Kita Menahan Derita”, TEMPO, 15 Oktober 1977), negeri kita (sekali lagi) bukan Texas-nya Sheridan di atas. Kita semua nampak masih sabar menunggu, masih nampak sabar selalu, merasa betah dengan hidup ini. Dan kata orang, itulah optimisme !
Jadi umpama pun kena serbu senewen-senewen dikit, tak apalah, pusing-pusing sedikit, bukankah “Keluarga Sejahtera Indonesia 1978” menawarkan Inza ? Mules-mules dikit akibat HO atau KM ? Kencangin ikat pinggang ! Dan bila pun tuli-tuli sedikit, apa “Keluarga Sejahtera Indonesia 1978” tidak kenal King Aid ?
Ya. Sebab kita semua maklum bahwa para guru pengambil kebijaksanaan, yang di atas-atas sana itu atau paduka-paduka semacamnya itu, sudah sangat pasti bahwa beliau-beliau perlu diberi kasihan. Karena lebih dulu dan lebih banyak kena serbu macam-macam rasa tak enak ketimbang kita yang biasa-biasa saja ini.
Adalah cerita Marie Fraser di Indiana Teacher, saya temui di Readers Digest (1966). Ini dia :
Di luar bangunan Istana Christianborg, yaitu Gedung Parlemen Denmark di Kopenhagen, terdapat tiga patung yang mengawal pintu gerbangnya. Patung tersebut melambangkan tokoh : orang yang lagi pusing-pusing kepalanya, orang yang mulas-mulas perutnya, dan orang yang tuli (!) pendengarannya.
“Ketiga patung tersebut menyarankan pada Anda”, tutur orang Denmark sambil senyum sayur asam, “Bahwa bila Anda memasuki kancah politik maka Anda pasti akan mengidap penyakit itu ketiga-tiganya”.
* Harry Tekssi adalah nama aktivis kesenian dari Bambang Haryanto pada tahun 1970-an, di lingkungan PKJT (Pusat Kebudayaan Jawa Tengah), Sasonomulyo, Solo. Artikel ini telah dimuat di majalah Semangat (Yogyakarta), No. 10, Juni 1978 : 18-20.
Wonogiri, 18-19 Mei 2005
Monday, May 16, 2005
Taufik Savalas, Lelucon Porno dan Stand-Up Comedy
Oleh : Bambang Haryanto
Email : humorliner@yahoo.com
HUBUNGAN INTIM. “Malam ini saya seneng banget dan sudah nyiapin kurang lebih 300 cerita. Nah kebetulan ada cerita nih. Suami-istri lagi berhubungan. Tapi engga jorok, sih. Lagi berhubungan. Huh-hah, huh-hah, huh-hah. Lagi-lagi hot-hotnya nih. Engga apa-apa kok, laki-bini. Halal. Asal jangan yang bukan muhrimnya. Engga boleh. Tiba-tiba istrinya bilang, ‘Mas, yok, kita keluar bareng, mas’. Anaknya nyeletuk, ‘Mamaa, aku ikut ! ‘ “
Audiens terdengar tertawa dan disusul tepuk tangan.
Demikian sepenggal cerita dari Taufik Savalas ketika mengawali pentasnya sebagai stand-up comedian dalam acara Comedy Club. “Maklum anak-anak, engga ngerti apa-apa’, tambah Taufik lagi. “Nah, kebetulan, tadi saya baca komik yang cerita dua binatang. Binatang ayam dan sapi. Suatu hari....” Cerita lainnya yang dipanggungkannya malam itu tentang monyet sebagai pilot pesawat di sebalik peristiwa kejatuhan pesawat bersangkutan di hutan Amazone.
Apakah Anda sudah pernah menyaksikannya ? Program rekaan rumah produksi media alliance dengan tajuk Comedy Club itu telah ditayangkan 2 Juli sampai 24 September 2004 di TransTV. Sebagai orang yang ingin sekali menonton bagaimana program tersebut, saat itu terpaksa harus frustrasi. Saya merasa tidak beruntung, karena siaran TransTV tak bisa nembus ke kota kecil Wonogiri, tempat saya tinggal.
Tetapi terdorong niat kuat untuk ikut mendorong keberhasilan upaya media alliance tersebut, melalui situs webnya (www.media-alliance.tv), pada awal September 2004, saya menulis pesan pada situs bersangkutan :
“Semoga acara Anda di Trans TV yang menampilkan Taufik Savalas akan sukses. Agar ada yang mengikuti, sehingga semakin cerdas tontonan komedi di Indonesia. Sayang, info Anda di situs web ini terlalu minim, tidak memuat kontak atau pendapat penonton, melalui web ini. Sayang juga, karena keterbatasan teknologi, saya belum juga bisa nonton tayangan stand up comedian-nya Taufik itu. Pada hal saya pengin sekali, ingin menyumbang gagasan kreatif. Tak apa. Saya senang bisa bersilaturahmi dengan Anda. Sukses untuk media alliance ! BH”
Saat itu tidak ada respons dari media alliance. Saya lalu merasa beruntung ketika Comedy Club itu rerun, diputar ulang pada bulan April 2005 yang lalu. Tiap Rabu, jam 18.30, di TransTV. Tetapi situs web rumah produksi media alliance sudah lenyap dari dunia maya. Mungkin rumah produksi ini sudah pula tutup ? Setelah bisa menonton, saya malah merasa buntung. Karena menurut pemahaman saya bukan seperti Comedy Club itulah sebuah stand up comedy dipentaskan !
ROCK YANG PEMARAH. Jay Sankey, penulis buku Zen and The Art of Stand-Up Comedy (1998) pernah mengajukan pertanyaan : mengapa memanggungkan pentas komedi solo atau stand-up comedy ? Karena di mata sebagian besar komedian, pentas komedi solo itu bukan hanya sesuatu yang ia kerjakan. Melainkan sesuatu tentang diri mereka sendiri !
“Ketika pertama kali mengembangkan tokoh komedi solo saya, saya berpendapat bahwa saya sedang menulis mengenai seseorang yang bukan diri saya. Tetapi begitu tampil di panggung, tiba-tiba saya tertabrak kenyataan bahwa beragam fakta seputar lelucon yang saya lemparkan di panggung itu memang bukan nyata-nyata gambaran hidup diri saya, tetapi tema emosional dan keprihatinan di balik lelucon-lelucon saya tersebut sangat mencerminkan siapa diri saya, apa yang saya fikirkan dan bagaimana saya merasakannya”, tulis Sankey.
Setiap orang memang dapat menceritakan lelucon. Tetapi bagi komedian sejati lucu itu harus bermula dan bersumber dari dirinya sendiri. Karena memang lelucon-lelucon yang ia bawakan di panggung merupakan perpanjangan diri mereka sendiri. Perbedaan hakiki inilah kemudian yang membuat pentasnya menjadi hidup. Menjadi pentas sebuah kehidupan.
Perspektif tersebut akan melahirkan realitas bahwa tiap-tiap komedian adalah sosok unik. Hadir sebagai persona. Komedian muda kulit hitam yang baru saja memandu Oscar 2005, Chris Rock, adalah sosok yang pemarah. Adam Sandler naif dan bodoh. Woody Allen adalah sosok yang neurotik. Chris Farley almarhum, sangat eksesif. Sementara Dennis Miller terampil dengan humor-humor politik.
Tetapi upaya mengembangkan dan memahirkan, tidak hanya perspektif komedi yang unik, tetapi juga kemampuan untuk mengomunikasikan perspektif tersebut, memerlukan kerja keras yang bukan main-main. Mengasah diri menjadi komedian sejati adalah pekerjaan 24 jam sehari. Radarnya yang peka harus terus jalan, untuk menguping tiap pembicaraan, mengamati peristiwa yang terjadi di sekelilingnya, mencatat pula kesan dan pula pikirannya seputar semua yang ia amati.
Menurut Sankey, intensitas seperti inilah yang membuat hidup komedian begitu menarik, karena menggelegaknya kegairahan untuk sungguh-sungguh mengatakan semua hal yang ia pikirkan. Tak ayal, sodokan-sodokan komentar para komedian sering mengantarkannya untuk dijuluki sebagai filsuf yang blak-blakan, pemimpi anarkis, atau bahkan pahlawan sosial.
PELAWAK BERGELAR Ph.D. Lawakan Taufik Savalas di Comedy Club jelas masih jauh bila disebut sebagai manifestasi pandangan pribadinya terhadap dunia. Taufik Savalas hanya tampil sebagai medium, tukang, untuk menceritakan cerita-cerita yang dianggap oleh produser acara Comedy Club sebagai cerita lucu. Tak ada seiris atau sekerat dari pribadinya telah ikut mewarnai cerita-cerita yang ia bawakan.
Memang penonton bisa tertawa, tetapi itu hanya di permukaan. Penonton belum tersentuh untuk digetarkan dawai-dawai sukmanya. Tak ayal seorang Garin Nugroho pernah berkomentar, humor televisi di Indonesia belum banyak yang mampu mengangkat rangsang manusiawi dalam diri pemirsa, seperti keharuan, kegembiraan, cinta sampai rasa ikatan persaudaraan (Kompas, 27/3/1994).
Untuk memancing tawa penonton, seperti halnya yang dilakukan oleh Taufik Savalas di Comedy Club, juga Komeng dan Ulfa ketika memandu acara API di TPI, dan juga sederet pelawak lainnya, selalu tergoda untuk menghamburkan lelucon menyangkut wilayah-wilayah biru, atau porno. Teramat gatal mengolah hal-hal banal untuk melucukan objek-objek seputar anal. Bagi saya, mereka pantas disebut sebagai pelawak-pelawak yang bergelar Ph.D. Karena materi lawakannya melulu seputar :
Pretty hard Dick atau Pretty huge Dick !
Wonogiri, 15-16 Mei 2005
Email : humorliner@yahoo.com
HUBUNGAN INTIM. “Malam ini saya seneng banget dan sudah nyiapin kurang lebih 300 cerita. Nah kebetulan ada cerita nih. Suami-istri lagi berhubungan. Tapi engga jorok, sih. Lagi berhubungan. Huh-hah, huh-hah, huh-hah. Lagi-lagi hot-hotnya nih. Engga apa-apa kok, laki-bini. Halal. Asal jangan yang bukan muhrimnya. Engga boleh. Tiba-tiba istrinya bilang, ‘Mas, yok, kita keluar bareng, mas’. Anaknya nyeletuk, ‘Mamaa, aku ikut ! ‘ “
Audiens terdengar tertawa dan disusul tepuk tangan.
Demikian sepenggal cerita dari Taufik Savalas ketika mengawali pentasnya sebagai stand-up comedian dalam acara Comedy Club. “Maklum anak-anak, engga ngerti apa-apa’, tambah Taufik lagi. “Nah, kebetulan, tadi saya baca komik yang cerita dua binatang. Binatang ayam dan sapi. Suatu hari....” Cerita lainnya yang dipanggungkannya malam itu tentang monyet sebagai pilot pesawat di sebalik peristiwa kejatuhan pesawat bersangkutan di hutan Amazone.
Apakah Anda sudah pernah menyaksikannya ? Program rekaan rumah produksi media alliance dengan tajuk Comedy Club itu telah ditayangkan 2 Juli sampai 24 September 2004 di TransTV. Sebagai orang yang ingin sekali menonton bagaimana program tersebut, saat itu terpaksa harus frustrasi. Saya merasa tidak beruntung, karena siaran TransTV tak bisa nembus ke kota kecil Wonogiri, tempat saya tinggal.
Tetapi terdorong niat kuat untuk ikut mendorong keberhasilan upaya media alliance tersebut, melalui situs webnya (www.media-alliance.tv), pada awal September 2004, saya menulis pesan pada situs bersangkutan :
“Semoga acara Anda di Trans TV yang menampilkan Taufik Savalas akan sukses. Agar ada yang mengikuti, sehingga semakin cerdas tontonan komedi di Indonesia. Sayang, info Anda di situs web ini terlalu minim, tidak memuat kontak atau pendapat penonton, melalui web ini. Sayang juga, karena keterbatasan teknologi, saya belum juga bisa nonton tayangan stand up comedian-nya Taufik itu. Pada hal saya pengin sekali, ingin menyumbang gagasan kreatif. Tak apa. Saya senang bisa bersilaturahmi dengan Anda. Sukses untuk media alliance ! BH”
Saat itu tidak ada respons dari media alliance. Saya lalu merasa beruntung ketika Comedy Club itu rerun, diputar ulang pada bulan April 2005 yang lalu. Tiap Rabu, jam 18.30, di TransTV. Tetapi situs web rumah produksi media alliance sudah lenyap dari dunia maya. Mungkin rumah produksi ini sudah pula tutup ? Setelah bisa menonton, saya malah merasa buntung. Karena menurut pemahaman saya bukan seperti Comedy Club itulah sebuah stand up comedy dipentaskan !
ROCK YANG PEMARAH. Jay Sankey, penulis buku Zen and The Art of Stand-Up Comedy (1998) pernah mengajukan pertanyaan : mengapa memanggungkan pentas komedi solo atau stand-up comedy ? Karena di mata sebagian besar komedian, pentas komedi solo itu bukan hanya sesuatu yang ia kerjakan. Melainkan sesuatu tentang diri mereka sendiri !
“Ketika pertama kali mengembangkan tokoh komedi solo saya, saya berpendapat bahwa saya sedang menulis mengenai seseorang yang bukan diri saya. Tetapi begitu tampil di panggung, tiba-tiba saya tertabrak kenyataan bahwa beragam fakta seputar lelucon yang saya lemparkan di panggung itu memang bukan nyata-nyata gambaran hidup diri saya, tetapi tema emosional dan keprihatinan di balik lelucon-lelucon saya tersebut sangat mencerminkan siapa diri saya, apa yang saya fikirkan dan bagaimana saya merasakannya”, tulis Sankey.
Setiap orang memang dapat menceritakan lelucon. Tetapi bagi komedian sejati lucu itu harus bermula dan bersumber dari dirinya sendiri. Karena memang lelucon-lelucon yang ia bawakan di panggung merupakan perpanjangan diri mereka sendiri. Perbedaan hakiki inilah kemudian yang membuat pentasnya menjadi hidup. Menjadi pentas sebuah kehidupan.
Perspektif tersebut akan melahirkan realitas bahwa tiap-tiap komedian adalah sosok unik. Hadir sebagai persona. Komedian muda kulit hitam yang baru saja memandu Oscar 2005, Chris Rock, adalah sosok yang pemarah. Adam Sandler naif dan bodoh. Woody Allen adalah sosok yang neurotik. Chris Farley almarhum, sangat eksesif. Sementara Dennis Miller terampil dengan humor-humor politik.
Tetapi upaya mengembangkan dan memahirkan, tidak hanya perspektif komedi yang unik, tetapi juga kemampuan untuk mengomunikasikan perspektif tersebut, memerlukan kerja keras yang bukan main-main. Mengasah diri menjadi komedian sejati adalah pekerjaan 24 jam sehari. Radarnya yang peka harus terus jalan, untuk menguping tiap pembicaraan, mengamati peristiwa yang terjadi di sekelilingnya, mencatat pula kesan dan pula pikirannya seputar semua yang ia amati.
Menurut Sankey, intensitas seperti inilah yang membuat hidup komedian begitu menarik, karena menggelegaknya kegairahan untuk sungguh-sungguh mengatakan semua hal yang ia pikirkan. Tak ayal, sodokan-sodokan komentar para komedian sering mengantarkannya untuk dijuluki sebagai filsuf yang blak-blakan, pemimpi anarkis, atau bahkan pahlawan sosial.
PELAWAK BERGELAR Ph.D. Lawakan Taufik Savalas di Comedy Club jelas masih jauh bila disebut sebagai manifestasi pandangan pribadinya terhadap dunia. Taufik Savalas hanya tampil sebagai medium, tukang, untuk menceritakan cerita-cerita yang dianggap oleh produser acara Comedy Club sebagai cerita lucu. Tak ada seiris atau sekerat dari pribadinya telah ikut mewarnai cerita-cerita yang ia bawakan.
Memang penonton bisa tertawa, tetapi itu hanya di permukaan. Penonton belum tersentuh untuk digetarkan dawai-dawai sukmanya. Tak ayal seorang Garin Nugroho pernah berkomentar, humor televisi di Indonesia belum banyak yang mampu mengangkat rangsang manusiawi dalam diri pemirsa, seperti keharuan, kegembiraan, cinta sampai rasa ikatan persaudaraan (Kompas, 27/3/1994).
Untuk memancing tawa penonton, seperti halnya yang dilakukan oleh Taufik Savalas di Comedy Club, juga Komeng dan Ulfa ketika memandu acara API di TPI, dan juga sederet pelawak lainnya, selalu tergoda untuk menghamburkan lelucon menyangkut wilayah-wilayah biru, atau porno. Teramat gatal mengolah hal-hal banal untuk melucukan objek-objek seputar anal. Bagi saya, mereka pantas disebut sebagai pelawak-pelawak yang bergelar Ph.D. Karena materi lawakannya melulu seputar :
Pretty hard Dick atau Pretty huge Dick !
Wonogiri, 15-16 Mei 2005
Wednesday, May 11, 2005
Menikmati Humor Prof. Sarlito W. Sarwono (1)
Oleh : Bambang Haryanto
Email : humorliner@yahoo.com
AWAS : ANDA SAKIT PERUT !. “Mas Bambang, tulisan Anda tentang Komedi Indonesia sangat betul. Jadi pelawak memang harus cerdas, karena kunci lucu cuma satu, yaitu penonton tiba-tiba dihadapkan kepada sesuatu hal yang bertentangan dengan apa yang mereka ketahui selama ini. Dalam Psikologi itu, namanya Disonansi Kognitif. Contoh, penyanyi sepuh ber-blangkon dan lurik, tiba-tiba menyanyi "Love Me Tender" dengan suara dan gaya Elvis Presley (selalu ada di Srimulat jaman dulu dan selalu memancing tawa)”
Itulah pembuka email dari Prof. Sarlito, yang dalam bahasa gaul mahasiswa dan koleganya akrab dipanggil dengan Mas Ito. Email yang terkirim sejak dua hari sebelumnya itu saya terima tanggal 10/5/2005. Isinya menyenangkan. Juga mengejutkan.
Kejutan pertama, saya tidak menyangka bahwa ketika (8/5/2005) memberitahukan kepada alumni kontes Mandom Resolution Award (MRA) 2004 (termasuk jurinya) bahwa saya telah membangun situs blog baru, Komedikus Erektus ! ini, begitu cepat mendapatkan tanggapan dari guru besar Fakultas Psikologi UI yang saya kenal ketika kami bertemu dalam ajang MRA 2004.
Kejutan kedua, saya tidak ikut bertanggung jawab bila Anda nanti kena sakit perut ketika menikmati lanjutan isi email yang berisi lawakan beliau seperti berikut ini :
“Atau kalau Petruk meledek Bagong : "Lambene Bagong melambe-lambe".
Lambe (Jawa) dipautkan dengan Lambai (Indonesia), jadi pas dan lucu.
Atau plesetan-plesetan yang suka saya pakai di ceramah-ceramah dan tidak pernah basi:
Puskesmas = Pusing Keseleo dan Masuk Angin
MBA = Memble Aje. Mengingat banyaknya sarjana/S2 yang nganggur
PS (Play Station) = Permainan Sex. Remaja pamit mau main PS, tapi nggak taunya main PS yang lain”
PLESETAN DESCARTES. Sama-sama alumni Universitas Indonesia, tetapi saya mengenal secara pribadi Mas Ito baru pada ajang MRA 2004, di Hotel Borobudur, Jakarta, November 2004. Beliau menjadi ketua dewan juri, sementara juri yang lain adalah Tika Bisono dan Maria Hartiningsih. Saya adalah salah satu dari 20 finalis dan kemudian beruntung menjadi salah satu dari 10 pemenang MRA 2004 tersebut.
FLASHBACK : Ketika di depan ketiga juri MRA 2004 tersebut saya sempat meledek sendiri slogan Epistoholik Indonesia (EI), yaitu komunitas jaringan kaum pencandu menulis surat-surat pembaca ke media massa yang saya dirikan dan resolusinya saya ikutkan dalam MRA 2004 ini. Slogan EI itu diilhami ucapan filsuf dan matematikawan Perancis terkenal, Rene Descartes (1596–1650), yaitu Cogito ergo sum. Saya berpikir maka saya ada. Sementara slogan EI berbunyi, Episto ergo sum. Saya menulis surat pembaca maka saya ada.
Saya pun nyeletuk : “Kalau slogan Cogito ergo sum diciptakan orang dari Perancis, maka slogan Episto ergo sum diciptakan orang dari Praci” Saya menikmati saat melihat Mas Ito tergelak. Malah ia menimpali : “Pracimantoro ?” Ah, itu hanya guyon rekayasa. Daerah ini memang termasuk Kabupaten Wonogiri. Tetapi saya tidak tinggal di Praci, melainkan utaranya Praci, di Wonogiri. Berstatus sebagai penduduk WNA, Wonogiri Asli !
Seusai perhelatan MRA 2004, saya pun menulis pengalaman suka-duka mengikuti kontes tersebut dalam situs blog Esai Epistoholica (No.14 dan 15). Mas Ito rupanya berkenan membaca-baca dan memberi komentar :
“Mas Bambang, waah...asyik juga baca blog-nya. Rupanya banyak sekali anekdote yang bisa Anda rekam, yang kalau dibiarkan akan hilang ditelan bayu, dan tidak akan menambah khasanah KM (Knowledge Management) kita.”.
KASET SEKS. Tetapi anekdot saya itu jelas belum sekaliber leluconnya Mas Ito. Lelucon itu pernah saya dengar dari sebuah kaset di tahun 1984, saat saya menjadi asisten di Jurusan Ilmu Perpustakaan, Fakultas Sastra (kini Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya) Universitas Indonesia. Saya menjadi asisten untuk mata kuliah Teknologi Media.
Kampus saya dan kampusnya Mas Ito yang masih di Rawamangun itu hanya sepelemparan batu jauhnya. Tetapi saya hanya mengenal Mas Ito dari pelbagai media massa. Ia seorang akademisi yang terkenal. Hanya lewat sebuah kaset itulah saat itu telah terbukakan diri saya untuk mengenal pikiran-pikiran beliau, dan yang paling penting, lawakan-lawakan beliau.
Tentu, lawakan akademisi tidak sama dengan lawakan di panggung API. Kaset itu berisi ceramah Mas Ito untuk mahasiswa Sastra UI, yang saya kopi dari Lab Bahasa FSUI. Bukan pula kaset lawakan. Topiknya adalah pendidikan seks. Topik serius, apalagi beliau adalah anggota Asosiasi Seksologi Indonesia. Tetapi ternyata tawa audiens jelas terekam saling susul-menyusul. “Kalau organ seks laki-laki, penampilannya lebih sederhana”, begitu salah satu paparan Mas Ito. Ledakan tawa audiens terdengar sangat bergemuruh !
Apa rahasia di balik ledakan tawa itu ? Gene Perret, kepala penulis lawakannya Bob Hope, menulis bahwa sense of humor itu menyangkut tiga keterampilan : (1) to see things as they are, melihat sesuatu apa adanya, (2) to recognize things as they are, memahami/mengerti sesuatu apa adanya, dan (3) to accept things as they are, menerima sesuatu apa adanya.
Ujaran Mas Ito tentang konfigurasi organ seks pria di depan mahasiswa- mahasiswi FSUI tadi, mencocoki dengan ketiga rumusan Perret tentang sense of humor tersebut Harap Anda catat bahwa saat itu Mas Ito sedang tidak melucu. Beliau yang pernah berkuliah di Universitas Edinburgh, Skotlandia, hingga saya curiga kegemaran Mas Ito “melawak” itu gara-gara ketularan virus pelawak-pelawak dalam acara tahunan Festival Lawak Antarbangsa di Edinburgh yang terkenal itu, semata-mata mengemukakan suatu realitas. Tetapi karena realitas tersebut dilihat, difahami dan diterima oleh banyak orang, mereka pun serempak meledak dalam tawa.
MENJAUHI PREMIS KEBENARAN. Formula fondamen lawakan tersebut sayangnya belum difahami oleh banyak pelawak-pelawak kita. Juga para pembuat sitkom-sitkom kita. Contoh : seorang pelawak pernah berkata : “Politik”, katanya, “adalah gabungan antara kata poli yang berarti banyak, dan tik yang berarti itik. Jadi politik definisinya adalah hal-hal yang banyak dan riuh bersuara seperti itik”.
Definisi tersebut, walau ditujukan untuk melawak, berakar dari premis yang cacat, hasil rekayasa dan tidak berlandaskan kebenaran. Audiens sulit merunut logikanya, sulit mengaitkan dengan pengalaman mereka sendiri, sehingga semakin sulit terpancing untuk tergelak.
Tetapi premis-premis cacat itu lebih mewabah dalam produk komedi situasi kita. Mungkin karena terimbas tempaan kultur gerakan berbohong secara nasional, lihatlah pelbagai komedi situasi yang muncul berparade di televisi kita. Isinya tuyul-tuyulan, jin-jinan, siluman-silumanan, ajaib-ajaiban, konyol-konyolan yang cenderung merendahkan kecerdasan. Terutama sekali makin menjauh dari premis-premis kebenaran. Menjauh dari melihat sesuatu apa adanya, memahami/mengerti sesuatu apa adanya dan menerima sesuatu secara apa adanya pula.
BUTUH SARAN AHLI. Insan-insan komedi Indonesia sudah saatnya diajak kembali ke khittah, bahwa nilai melawak yang luhur muncul bila kita berani menertawai diri sendiri. Dengan sikap rendah hati, mungkin akan mudah tergerak untuk menyetrum diri dengan energi-energi kreatif baru. Penghibur dan mantan wartawan Kompas, Sujiwo Tejo, pernah mengusulkan agar insan-insan komedi kita sudi minta penataran dari pelbagai ahli. Baik ahli psikologi sampai ahli bahasa, demi meningkatkan kualitas personel dan sajian komedi mereka di televisi. Mungkin Prof. Sarlito memiliki saran dan kritik bagi komunitas komedi Indonesia ?
Oh ya, seputar formula Disonansi Kognitif yang diajukan Mas Ito, saya punya cerita kecil. Sebagai epistoholik, saya pernah menulis surat pembaca di harian Kompas edisi Jawa Tengah (20/8/2004) tentang kasus pembelian tiket pertandingan olahraga di mana setiap pengunjung memperoleh bonus satu bungkus rokok. Itulah kelucuan konyol khas bangsa ini : kegiatan untuk mempromosikan pentingnya kesehatan tetapi disponsori oleh produk yang berbahaya bagi kesehatan.
Potret Disonansi Kognitif yang lebih parah saya tulis di koran yang sama (18/9/2004) : Tanggal 19/8/2004, Presiden kita (Megawati) mengunjungi pasukan TNI-Polri yang bertugas di Aceh, di lembah Aloe Gintong, Kecamatan Jantho, Kabupaten Aceh Besar.
Kepada para prajurit, seperti dilaporkan Kompas (20/8/04 :1), Presiden berpesan : Jaga kesehatanmu (!) dan berhati-hatilah dalam bertempur. Berita yang sama dimuat di Solopos (20/8/04 :2) bertajuk : Di Aceh, Presiden bagikan rokok kepada prajurit.
Sambil menunggu saran atau kritik dari Mas Ito, kini saya sajikan bagian akhir dari email beliau.
Kuis analogi : Apa hubungannya Taman Mini, Metro Mini dan Rok Mini? Dalam Taman Mini ada Metro Mini, dalam Metro Mini ada Rok Mini, dalam Rok Mini ada Taman Mini .
Bila kelak menjadi stand-up comedian, merangkap sebagai bujangan yang taat aturan A (abstinence) atau berpantang seks dari formula ABC-nya pencegahan HIV/AIDS, terus terang saya belum berani memanggungkan kuis lawakan Mas Ito yang di atas tadi.
Saya takut tak kuat terhadap godaan panorama “taman mini yang memang melambai-lambai lambe itu”.
Wonogiri, 11 Mei 2005
Catatan : Email dari Prof. Sarlito yang karena saking menariknya telah begitu saja saya jadikan artikel di atas. Beberapa hari kemudian, saya baru sadar, bahwa mungkin saya telah melakukan tindakan tak etis. Yaitu memuat tulisan seseorang tanpa meminta ijin yang bersangkutan terlebih dahulu.
Merasa cemas-cemas harap, Senin sore (23/5/2005) saya mengirimkan SMS kepada Mas Ito :
Yth Mas Ito, humor “Taman Mini” Anda saking melambai-lambai lambe, langsung saya sosor jadi artikel di blog saya, tanpa minta ijin Mas Ito. Moga Mas Ito tidak keberatan. Thx. BH.
Sekejap muncul balasan beliau : ...Hahaha...Ok.
Kalau Anda rela tertawa, itulah berkah kesaktian dari teknik melawak yang disebut sebagai callback. Dalam teks artikel saya di atas ada kalimat yang berpotensi memancing tawa (saya harap), lalu dalam catatan ini hal tersebut saya munculkan kembali.
Dalam sitkom “Friends” yang dibintangi Jennifer Aniston sampai Lisa Kudrow (favorit saya yang memainkan Phoebe Buffay) garapan Marta Kauffman dan David Crane, teknik callback selalu saja muncul dan muncul kembali.
Wonogiri, 24 Mei 2005
Email : humorliner@yahoo.com
AWAS : ANDA SAKIT PERUT !. “Mas Bambang, tulisan Anda tentang Komedi Indonesia sangat betul. Jadi pelawak memang harus cerdas, karena kunci lucu cuma satu, yaitu penonton tiba-tiba dihadapkan kepada sesuatu hal yang bertentangan dengan apa yang mereka ketahui selama ini. Dalam Psikologi itu, namanya Disonansi Kognitif. Contoh, penyanyi sepuh ber-blangkon dan lurik, tiba-tiba menyanyi "Love Me Tender" dengan suara dan gaya Elvis Presley (selalu ada di Srimulat jaman dulu dan selalu memancing tawa)”
Itulah pembuka email dari Prof. Sarlito, yang dalam bahasa gaul mahasiswa dan koleganya akrab dipanggil dengan Mas Ito. Email yang terkirim sejak dua hari sebelumnya itu saya terima tanggal 10/5/2005. Isinya menyenangkan. Juga mengejutkan.
Kejutan pertama, saya tidak menyangka bahwa ketika (8/5/2005) memberitahukan kepada alumni kontes Mandom Resolution Award (MRA) 2004 (termasuk jurinya) bahwa saya telah membangun situs blog baru, Komedikus Erektus ! ini, begitu cepat mendapatkan tanggapan dari guru besar Fakultas Psikologi UI yang saya kenal ketika kami bertemu dalam ajang MRA 2004.
Kejutan kedua, saya tidak ikut bertanggung jawab bila Anda nanti kena sakit perut ketika menikmati lanjutan isi email yang berisi lawakan beliau seperti berikut ini :
“Atau kalau Petruk meledek Bagong : "Lambene Bagong melambe-lambe".
Lambe (Jawa) dipautkan dengan Lambai (Indonesia), jadi pas dan lucu.
Atau plesetan-plesetan yang suka saya pakai di ceramah-ceramah dan tidak pernah basi:
Puskesmas = Pusing Keseleo dan Masuk Angin
MBA = Memble Aje. Mengingat banyaknya sarjana/S2 yang nganggur
PS (Play Station) = Permainan Sex. Remaja pamit mau main PS, tapi nggak taunya main PS yang lain”
PLESETAN DESCARTES. Sama-sama alumni Universitas Indonesia, tetapi saya mengenal secara pribadi Mas Ito baru pada ajang MRA 2004, di Hotel Borobudur, Jakarta, November 2004. Beliau menjadi ketua dewan juri, sementara juri yang lain adalah Tika Bisono dan Maria Hartiningsih. Saya adalah salah satu dari 20 finalis dan kemudian beruntung menjadi salah satu dari 10 pemenang MRA 2004 tersebut.
FLASHBACK : Ketika di depan ketiga juri MRA 2004 tersebut saya sempat meledek sendiri slogan Epistoholik Indonesia (EI), yaitu komunitas jaringan kaum pencandu menulis surat-surat pembaca ke media massa yang saya dirikan dan resolusinya saya ikutkan dalam MRA 2004 ini. Slogan EI itu diilhami ucapan filsuf dan matematikawan Perancis terkenal, Rene Descartes (1596–1650), yaitu Cogito ergo sum. Saya berpikir maka saya ada. Sementara slogan EI berbunyi, Episto ergo sum. Saya menulis surat pembaca maka saya ada.
Saya pun nyeletuk : “Kalau slogan Cogito ergo sum diciptakan orang dari Perancis, maka slogan Episto ergo sum diciptakan orang dari Praci” Saya menikmati saat melihat Mas Ito tergelak. Malah ia menimpali : “Pracimantoro ?” Ah, itu hanya guyon rekayasa. Daerah ini memang termasuk Kabupaten Wonogiri. Tetapi saya tidak tinggal di Praci, melainkan utaranya Praci, di Wonogiri. Berstatus sebagai penduduk WNA, Wonogiri Asli !
Seusai perhelatan MRA 2004, saya pun menulis pengalaman suka-duka mengikuti kontes tersebut dalam situs blog Esai Epistoholica (No.14 dan 15). Mas Ito rupanya berkenan membaca-baca dan memberi komentar :
“Mas Bambang, waah...asyik juga baca blog-nya. Rupanya banyak sekali anekdote yang bisa Anda rekam, yang kalau dibiarkan akan hilang ditelan bayu, dan tidak akan menambah khasanah KM (Knowledge Management) kita.”.
KASET SEKS. Tetapi anekdot saya itu jelas belum sekaliber leluconnya Mas Ito. Lelucon itu pernah saya dengar dari sebuah kaset di tahun 1984, saat saya menjadi asisten di Jurusan Ilmu Perpustakaan, Fakultas Sastra (kini Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya) Universitas Indonesia. Saya menjadi asisten untuk mata kuliah Teknologi Media.
Kampus saya dan kampusnya Mas Ito yang masih di Rawamangun itu hanya sepelemparan batu jauhnya. Tetapi saya hanya mengenal Mas Ito dari pelbagai media massa. Ia seorang akademisi yang terkenal. Hanya lewat sebuah kaset itulah saat itu telah terbukakan diri saya untuk mengenal pikiran-pikiran beliau, dan yang paling penting, lawakan-lawakan beliau.
Tentu, lawakan akademisi tidak sama dengan lawakan di panggung API. Kaset itu berisi ceramah Mas Ito untuk mahasiswa Sastra UI, yang saya kopi dari Lab Bahasa FSUI. Bukan pula kaset lawakan. Topiknya adalah pendidikan seks. Topik serius, apalagi beliau adalah anggota Asosiasi Seksologi Indonesia. Tetapi ternyata tawa audiens jelas terekam saling susul-menyusul. “Kalau organ seks laki-laki, penampilannya lebih sederhana”, begitu salah satu paparan Mas Ito. Ledakan tawa audiens terdengar sangat bergemuruh !
Apa rahasia di balik ledakan tawa itu ? Gene Perret, kepala penulis lawakannya Bob Hope, menulis bahwa sense of humor itu menyangkut tiga keterampilan : (1) to see things as they are, melihat sesuatu apa adanya, (2) to recognize things as they are, memahami/mengerti sesuatu apa adanya, dan (3) to accept things as they are, menerima sesuatu apa adanya.
Ujaran Mas Ito tentang konfigurasi organ seks pria di depan mahasiswa- mahasiswi FSUI tadi, mencocoki dengan ketiga rumusan Perret tentang sense of humor tersebut Harap Anda catat bahwa saat itu Mas Ito sedang tidak melucu. Beliau yang pernah berkuliah di Universitas Edinburgh, Skotlandia, hingga saya curiga kegemaran Mas Ito “melawak” itu gara-gara ketularan virus pelawak-pelawak dalam acara tahunan Festival Lawak Antarbangsa di Edinburgh yang terkenal itu, semata-mata mengemukakan suatu realitas. Tetapi karena realitas tersebut dilihat, difahami dan diterima oleh banyak orang, mereka pun serempak meledak dalam tawa.
MENJAUHI PREMIS KEBENARAN. Formula fondamen lawakan tersebut sayangnya belum difahami oleh banyak pelawak-pelawak kita. Juga para pembuat sitkom-sitkom kita. Contoh : seorang pelawak pernah berkata : “Politik”, katanya, “adalah gabungan antara kata poli yang berarti banyak, dan tik yang berarti itik. Jadi politik definisinya adalah hal-hal yang banyak dan riuh bersuara seperti itik”.
Definisi tersebut, walau ditujukan untuk melawak, berakar dari premis yang cacat, hasil rekayasa dan tidak berlandaskan kebenaran. Audiens sulit merunut logikanya, sulit mengaitkan dengan pengalaman mereka sendiri, sehingga semakin sulit terpancing untuk tergelak.
Tetapi premis-premis cacat itu lebih mewabah dalam produk komedi situasi kita. Mungkin karena terimbas tempaan kultur gerakan berbohong secara nasional, lihatlah pelbagai komedi situasi yang muncul berparade di televisi kita. Isinya tuyul-tuyulan, jin-jinan, siluman-silumanan, ajaib-ajaiban, konyol-konyolan yang cenderung merendahkan kecerdasan. Terutama sekali makin menjauh dari premis-premis kebenaran. Menjauh dari melihat sesuatu apa adanya, memahami/mengerti sesuatu apa adanya dan menerima sesuatu secara apa adanya pula.
BUTUH SARAN AHLI. Insan-insan komedi Indonesia sudah saatnya diajak kembali ke khittah, bahwa nilai melawak yang luhur muncul bila kita berani menertawai diri sendiri. Dengan sikap rendah hati, mungkin akan mudah tergerak untuk menyetrum diri dengan energi-energi kreatif baru. Penghibur dan mantan wartawan Kompas, Sujiwo Tejo, pernah mengusulkan agar insan-insan komedi kita sudi minta penataran dari pelbagai ahli. Baik ahli psikologi sampai ahli bahasa, demi meningkatkan kualitas personel dan sajian komedi mereka di televisi. Mungkin Prof. Sarlito memiliki saran dan kritik bagi komunitas komedi Indonesia ?
Oh ya, seputar formula Disonansi Kognitif yang diajukan Mas Ito, saya punya cerita kecil. Sebagai epistoholik, saya pernah menulis surat pembaca di harian Kompas edisi Jawa Tengah (20/8/2004) tentang kasus pembelian tiket pertandingan olahraga di mana setiap pengunjung memperoleh bonus satu bungkus rokok. Itulah kelucuan konyol khas bangsa ini : kegiatan untuk mempromosikan pentingnya kesehatan tetapi disponsori oleh produk yang berbahaya bagi kesehatan.
Potret Disonansi Kognitif yang lebih parah saya tulis di koran yang sama (18/9/2004) : Tanggal 19/8/2004, Presiden kita (Megawati) mengunjungi pasukan TNI-Polri yang bertugas di Aceh, di lembah Aloe Gintong, Kecamatan Jantho, Kabupaten Aceh Besar.
Kepada para prajurit, seperti dilaporkan Kompas (20/8/04 :1), Presiden berpesan : Jaga kesehatanmu (!) dan berhati-hatilah dalam bertempur. Berita yang sama dimuat di Solopos (20/8/04 :2) bertajuk : Di Aceh, Presiden bagikan rokok kepada prajurit.
Sambil menunggu saran atau kritik dari Mas Ito, kini saya sajikan bagian akhir dari email beliau.
Kuis analogi : Apa hubungannya Taman Mini, Metro Mini dan Rok Mini? Dalam Taman Mini ada Metro Mini, dalam Metro Mini ada Rok Mini, dalam Rok Mini ada Taman Mini .
Bila kelak menjadi stand-up comedian, merangkap sebagai bujangan yang taat aturan A (abstinence) atau berpantang seks dari formula ABC-nya pencegahan HIV/AIDS, terus terang saya belum berani memanggungkan kuis lawakan Mas Ito yang di atas tadi.
Saya takut tak kuat terhadap godaan panorama “taman mini yang memang melambai-lambai lambe itu”.
Wonogiri, 11 Mei 2005
Catatan : Email dari Prof. Sarlito yang karena saking menariknya telah begitu saja saya jadikan artikel di atas. Beberapa hari kemudian, saya baru sadar, bahwa mungkin saya telah melakukan tindakan tak etis. Yaitu memuat tulisan seseorang tanpa meminta ijin yang bersangkutan terlebih dahulu.
Merasa cemas-cemas harap, Senin sore (23/5/2005) saya mengirimkan SMS kepada Mas Ito :
Yth Mas Ito, humor “Taman Mini” Anda saking melambai-lambai lambe, langsung saya sosor jadi artikel di blog saya, tanpa minta ijin Mas Ito. Moga Mas Ito tidak keberatan. Thx. BH.
Sekejap muncul balasan beliau : ...Hahaha...Ok.
Kalau Anda rela tertawa, itulah berkah kesaktian dari teknik melawak yang disebut sebagai callback. Dalam teks artikel saya di atas ada kalimat yang berpotensi memancing tawa (saya harap), lalu dalam catatan ini hal tersebut saya munculkan kembali.
Dalam sitkom “Friends” yang dibintangi Jennifer Aniston sampai Lisa Kudrow (favorit saya yang memainkan Phoebe Buffay) garapan Marta Kauffman dan David Crane, teknik callback selalu saja muncul dan muncul kembali.
Wonogiri, 24 Mei 2005
Monday, May 09, 2005
Gebraklah Lawakan Anda Pada Kata Pertama !
(Surat Untuk Kontestan Audisi Pelawak TPI/API)
Oleh : Bambang Haryanto
Email : humorliner@yahoo.com
TERPELESET LELUCON POLITIK. Yth. Kontestan Audisi Pelawak TPI (API) di TPI. Salam sejahtera. Selamat untuk BAJAJ (R. Asep Saefuloh, Meilia Balipa Emil, Isa Wahyu Prastantyo), LIMAU (Ali Zainal Abidin, Sumono dan M.Furqon), NGELANTUR (Suro (Heri Suryanto), Totok Pranadi, M. Isa. S), dan SOS (Suwarman, Obin Wahyudin dan Sutisna), yang terhindar dari kegosongan di Hari Minggu (8/5/2005) yang lalu.
Untuk HOKI (Teguh, Aona Suka dan Jamal Boy), semoga tidak putus asa. Sebenarnya saya bisa nyambung dengan upaya HOKI ketika menampilkan lawakan-lawakan berbau politik, yang sebenarnya relevan dengan saat ini. Misalnya tentang terjadinya korupsi, bagi-bagi komisi, di Komisi Pemilihan Umum.
Tetapi menurut saya, malam itu HOKI melupakan bahwa audiens televisi itu beragam. Umpama saja lawakan bab komisi itu dilontarkan di kampus, mungkin akan disambut ledakan tawa. Tetapi di televisi, ternyata lelucon politiknya HOKI mandul-mandul saja. Mengapa lawakan aktual HOKI itu kurang mendapatkan sambutan ?
Kita dapat belajar dari pendapat Gene Perret, penulis lawaknya komedian Bob Hope yang terkenal, yang mengatakan :
Not all audiences have a sense of humor about all topics. You must know what they see, recognize, and accept before kidding them. Tidak semua penonton memiliki selera humor mengenai pelbagai macam hal. Anda harus tahu apa yang mereka lihat, mereka fahami dan apa yang mereka terima sebelum melucukan hal-hal tersebut.
Di Malam Anugerah Oscar/Academy Award 2001, komedian Steve Martin (seorang doktor dan komedian favorit saya) yang jadi host acara itu, ketika tampil ia langsung menunjuk ke beberapa patung Oscar yang besar-besar di seputar panggung megah itu. Lalu Steve Martin bilang, “Kalau di Afghanistan, semua ini akan dihancurkan !”
Penonton meledak dalam bahak.
Sebab sebagian besar mereka itu “to see, to recognize and to acccept”, melihat, memahami dan menerima apa yang diungkap oleh Steve Martin tersebut. Karena memang saat itu televisi dan surat kabar dunia lagi heboh seputar berita penghancuran patung-patung Budha oleh kaum Taliban di Afghanistan.
KURANG MENGGEBRAK. Untuk semua kelompok yang tampil malam itu (8/5/2005), seperti diindikasikan oleh Basuki Srimulat, bagi saya memang seperti kurang peka dan kurang menyadari maha pentingnya gebrakan pertama begitu muncul di panggung.
Untuk perbaikan, berikut saya kutipkan petunjuk komedian wanita terkenal, Phyllis Diller : “The first word, that first sentence is one of the most important things you’re gonna do. I found that I must joke about something that they can look at and relate to”. Kata pertama, kalimat pertama merupakan hal paling penting dalam pemanggungan. Saya sadari bahwa saya harus melucukan sesuatu yang dapat mereka lihat atau yang terkait dengan penonton.
Begitulah asal-usul-usil saya untuk Anda semua.
Info lebih lanjut seputar sumbang gagasan saya terhadap dunia lawak Indonesia, silakan kunjungi situs saya, Komedikus Erektus !
Selamat berjuang. Sukses untuk TPI. Sukses untuk generasi baru pelawak Indonesia.
*Bambang Haryanto, penulis komedi dan dua buku kumpulan humor. Alumnus UI.
Oleh : Bambang Haryanto
Email : humorliner@yahoo.com
TERPELESET LELUCON POLITIK. Yth. Kontestan Audisi Pelawak TPI (API) di TPI. Salam sejahtera. Selamat untuk BAJAJ (R. Asep Saefuloh, Meilia Balipa Emil, Isa Wahyu Prastantyo), LIMAU (Ali Zainal Abidin, Sumono dan M.Furqon), NGELANTUR (Suro (Heri Suryanto), Totok Pranadi, M. Isa. S), dan SOS (Suwarman, Obin Wahyudin dan Sutisna), yang terhindar dari kegosongan di Hari Minggu (8/5/2005) yang lalu.
Untuk HOKI (Teguh, Aona Suka dan Jamal Boy), semoga tidak putus asa. Sebenarnya saya bisa nyambung dengan upaya HOKI ketika menampilkan lawakan-lawakan berbau politik, yang sebenarnya relevan dengan saat ini. Misalnya tentang terjadinya korupsi, bagi-bagi komisi, di Komisi Pemilihan Umum.
Tetapi menurut saya, malam itu HOKI melupakan bahwa audiens televisi itu beragam. Umpama saja lawakan bab komisi itu dilontarkan di kampus, mungkin akan disambut ledakan tawa. Tetapi di televisi, ternyata lelucon politiknya HOKI mandul-mandul saja. Mengapa lawakan aktual HOKI itu kurang mendapatkan sambutan ?
Kita dapat belajar dari pendapat Gene Perret, penulis lawaknya komedian Bob Hope yang terkenal, yang mengatakan :
Not all audiences have a sense of humor about all topics. You must know what they see, recognize, and accept before kidding them. Tidak semua penonton memiliki selera humor mengenai pelbagai macam hal. Anda harus tahu apa yang mereka lihat, mereka fahami dan apa yang mereka terima sebelum melucukan hal-hal tersebut.
Di Malam Anugerah Oscar/Academy Award 2001, komedian Steve Martin (seorang doktor dan komedian favorit saya) yang jadi host acara itu, ketika tampil ia langsung menunjuk ke beberapa patung Oscar yang besar-besar di seputar panggung megah itu. Lalu Steve Martin bilang, “Kalau di Afghanistan, semua ini akan dihancurkan !”
Penonton meledak dalam bahak.
Sebab sebagian besar mereka itu “to see, to recognize and to acccept”, melihat, memahami dan menerima apa yang diungkap oleh Steve Martin tersebut. Karena memang saat itu televisi dan surat kabar dunia lagi heboh seputar berita penghancuran patung-patung Budha oleh kaum Taliban di Afghanistan.
KURANG MENGGEBRAK. Untuk semua kelompok yang tampil malam itu (8/5/2005), seperti diindikasikan oleh Basuki Srimulat, bagi saya memang seperti kurang peka dan kurang menyadari maha pentingnya gebrakan pertama begitu muncul di panggung.
Untuk perbaikan, berikut saya kutipkan petunjuk komedian wanita terkenal, Phyllis Diller : “The first word, that first sentence is one of the most important things you’re gonna do. I found that I must joke about something that they can look at and relate to”. Kata pertama, kalimat pertama merupakan hal paling penting dalam pemanggungan. Saya sadari bahwa saya harus melucukan sesuatu yang dapat mereka lihat atau yang terkait dengan penonton.
Begitulah asal-usul-usil saya untuk Anda semua.
Info lebih lanjut seputar sumbang gagasan saya terhadap dunia lawak Indonesia, silakan kunjungi situs saya, Komedikus Erektus !
Selamat berjuang. Sukses untuk TPI. Sukses untuk generasi baru pelawak Indonesia.
*Bambang Haryanto, penulis komedi dan dua buku kumpulan humor. Alumnus UI.
Bagito 1999 Vs Bagito 2005
Oleh : Bambang Haryanto
Email : humorliner@yahoo.com
BAGITO 1999. “Makanya jangan kaget, kalau pelawak pun tak salah membaca Alvin Toffler, Machiavelli, atau malah John Naisbitt”, kata Tubagus Dedi Suwandi Gumelar yang bernama komersial Miing Bagito. Pernyataan dan omongan “kelas atas” ini termuat dalam wawancara yang dilakukan oleh wartawan Kompas Retno Bintarti, Agus Hermawan dan Rudy Badil, dan dimuat dalam Harian Kompas, 10 Oktober 1999.
Wawancara dilakukan menjelang tepat 21 tahun kelompok lawak Bagito pada tanggal 28 Oktober 1999. Wawancara itu juga merujuk penerbitan buku Bagito Trio Pengusaha Tawa (1995) yang ditulis oleh Herry Gendut Janarto.
Memang tidak salah bila pelawak, setiap kali, harus memperkaya dan meningkatkan diri dengan membaca-baca buku karya-karya penulis terkenal. Akademisi pemasaran dari Universitas Indonesia, Rhenald Khasali, malah pernah menyanjung Bagito terkait dengan upaya mereka meningkatkan diri tersebut.
HARTA TIDAK KELIHATAN. Dalam artikel berjudul “Bagito” di tabloid Kontan (No.8/13 November 2000), Rhenald Kasali membahas apa yang disebut sebagai invisible assets, harta yang tidak kelihatan yang dimiliki sesuatu perusahaan. Harta yang satu ini memang tidak kelihatan seperti mesin-mesin produksi, peralatan pabrik, mobil atau gedung yang nampak secara fisik.
Harta ini tak kasat mata karena ia melekat dalam diri seseorang dan tidak dapat diperoleh dalam sekejap. Tapi ia bisa berkembang dan menghasilkan hal-hal baru dalam kehidupan. Seberapa jauh ia berkembang akan sangat bergantung pada kemampuan manusia memupuknya dalam diri sendiri dan tim yang ada di sekitar dirinya.
“Belajarlah dari Bagito”, kata Rhenald Kasali yang merujuk isi buku Bagito Trio Pengusaha Tawa, yang mengulas bagaimana Bagito memobilisasi harta tak kelihatannya dengan metode tumbuh dari bawah. Bagito, menurutnya, menjadi besar karena mampu memobilisasi dengan baik harta tak kelihatan yang Tuhan berikan kepada mereka.
Sukses Bagito tentu saja tak dapat dikopi begitu saja oleh siapa pun, karena setiap manusia punya jalan dan karakternya masing-masing. Tapi, setiap manusia perlu menyadari bahwa sejak dilahirkan Tuhan telah membekali dirinya dengan harta tak kelihatan yang harus dimobilisasi secara bijak. Dedi Gumelar, katanya, memang cuma tamat STM, tapi ia pernah tampak kuliah kembali di sebuah lembaga pendidikan. Tetapi seingat saya, Bagito belum pernah melucukan pendidikannya yang STM (Sekolah Teknik Melawak ?) tersebut.
INVESTASI ISI OTAK. Di mana kini posisi Bagito di tahun 2005 ini ? Satu dari tiga anggota trio Bagito, Hadi “Unang” Prabowo Suwardi, telah keluar. Setelah sukses tampil di stasiun televisi RCTI membawakan “Basho”, rasanya pamor mereka makin meredup. Menurut pandangan saya, seperti halnya para pelawak Indonesia, mereka nampak kurang berinvestasi dalam pendidikan, yaitu untuk mendidik diri mereka sendiri.
Benyamin Franklin (1706–90), politisi, penemu dan ilmuwan Amerika, berkata : ”If a man empties his purse into his head no one can take it away from him. An investment in knowledge always pays the best interest”. Apabila seseorang mengosongkan isi dompetnya untuk mengisi kepalanya, maka tak seorang pun mampu mengambilnya dari dirinya. Berinvestasi dalam bentuk pengetahuan selalu memberikan bunga yang terbaik.
Ketika Bagito memperoleh kontrak bernilai milyaran rupiah dari “Basho”-nya RCTI, kira-kira berapa banyak buku-buku tentang lawak yang telah ia beli untuk mengisi “aki” otak dan wawasan mereka ? Pertanyaan yang sama juga tetap relevan untuk diajukan kepada para pelawak-pelawak kita yang masih berkibar saat ini. Saya ragu mereka terpikir untuk melakukan hal penting itu. Juga skeptis apakah buku-buku bacaan “tingkat atas” yang Miing sebutkan di awal tulisan ini, sedari Alvin Toffler hingga John Naisbitt, telah mampu memperkaya gizi bagi lawakan mereka.
Sekadar info : Alvin Toffler ngetop di tahun 1970-an dengan buku The Future Shock dan 1980-an dengan The Third Wave. Jadi Bagito nampak telmi karena ia baru menyebutkannya di tahun 1999. Alias “terlambat” sembilan belas tahun lebih kan..boo.
Baru-baru saja Miing Bagito terpilih sebagai Sekretaris Jenderal organisasi Persatuan Artis Seni Komedi Indonesia (PASKI).
Semoga posisinya yang baru ini akan mampu membuka pintu selebar-lebarnya bagi dirinya untuk mewariskan cerita-cerita keberhasilan, kegagalan, juga hikmah atas perjalanan hidupnya sebagai salah satu tonggak sejarah seni komedi di Indonesia. Siapa tahu, sesuai ajaran Robert T. Kiyosaki bahwa “mengajarlah dan Anda akan menerima”, akan menghadirkan mukjijat bagi Bagito 2005. Bangkit dari keterpurukan !
Wonogiri, 8 Mei 2005
Email : humorliner@yahoo.com
BAGITO 1999. “Makanya jangan kaget, kalau pelawak pun tak salah membaca Alvin Toffler, Machiavelli, atau malah John Naisbitt”, kata Tubagus Dedi Suwandi Gumelar yang bernama komersial Miing Bagito. Pernyataan dan omongan “kelas atas” ini termuat dalam wawancara yang dilakukan oleh wartawan Kompas Retno Bintarti, Agus Hermawan dan Rudy Badil, dan dimuat dalam Harian Kompas, 10 Oktober 1999.
Wawancara dilakukan menjelang tepat 21 tahun kelompok lawak Bagito pada tanggal 28 Oktober 1999. Wawancara itu juga merujuk penerbitan buku Bagito Trio Pengusaha Tawa (1995) yang ditulis oleh Herry Gendut Janarto.
Memang tidak salah bila pelawak, setiap kali, harus memperkaya dan meningkatkan diri dengan membaca-baca buku karya-karya penulis terkenal. Akademisi pemasaran dari Universitas Indonesia, Rhenald Khasali, malah pernah menyanjung Bagito terkait dengan upaya mereka meningkatkan diri tersebut.
HARTA TIDAK KELIHATAN. Dalam artikel berjudul “Bagito” di tabloid Kontan (No.8/13 November 2000), Rhenald Kasali membahas apa yang disebut sebagai invisible assets, harta yang tidak kelihatan yang dimiliki sesuatu perusahaan. Harta yang satu ini memang tidak kelihatan seperti mesin-mesin produksi, peralatan pabrik, mobil atau gedung yang nampak secara fisik.
Harta ini tak kasat mata karena ia melekat dalam diri seseorang dan tidak dapat diperoleh dalam sekejap. Tapi ia bisa berkembang dan menghasilkan hal-hal baru dalam kehidupan. Seberapa jauh ia berkembang akan sangat bergantung pada kemampuan manusia memupuknya dalam diri sendiri dan tim yang ada di sekitar dirinya.
“Belajarlah dari Bagito”, kata Rhenald Kasali yang merujuk isi buku Bagito Trio Pengusaha Tawa, yang mengulas bagaimana Bagito memobilisasi harta tak kelihatannya dengan metode tumbuh dari bawah. Bagito, menurutnya, menjadi besar karena mampu memobilisasi dengan baik harta tak kelihatan yang Tuhan berikan kepada mereka.
Sukses Bagito tentu saja tak dapat dikopi begitu saja oleh siapa pun, karena setiap manusia punya jalan dan karakternya masing-masing. Tapi, setiap manusia perlu menyadari bahwa sejak dilahirkan Tuhan telah membekali dirinya dengan harta tak kelihatan yang harus dimobilisasi secara bijak. Dedi Gumelar, katanya, memang cuma tamat STM, tapi ia pernah tampak kuliah kembali di sebuah lembaga pendidikan. Tetapi seingat saya, Bagito belum pernah melucukan pendidikannya yang STM (Sekolah Teknik Melawak ?) tersebut.
INVESTASI ISI OTAK. Di mana kini posisi Bagito di tahun 2005 ini ? Satu dari tiga anggota trio Bagito, Hadi “Unang” Prabowo Suwardi, telah keluar. Setelah sukses tampil di stasiun televisi RCTI membawakan “Basho”, rasanya pamor mereka makin meredup. Menurut pandangan saya, seperti halnya para pelawak Indonesia, mereka nampak kurang berinvestasi dalam pendidikan, yaitu untuk mendidik diri mereka sendiri.
Benyamin Franklin (1706–90), politisi, penemu dan ilmuwan Amerika, berkata : ”If a man empties his purse into his head no one can take it away from him. An investment in knowledge always pays the best interest”. Apabila seseorang mengosongkan isi dompetnya untuk mengisi kepalanya, maka tak seorang pun mampu mengambilnya dari dirinya. Berinvestasi dalam bentuk pengetahuan selalu memberikan bunga yang terbaik.
Ketika Bagito memperoleh kontrak bernilai milyaran rupiah dari “Basho”-nya RCTI, kira-kira berapa banyak buku-buku tentang lawak yang telah ia beli untuk mengisi “aki” otak dan wawasan mereka ? Pertanyaan yang sama juga tetap relevan untuk diajukan kepada para pelawak-pelawak kita yang masih berkibar saat ini. Saya ragu mereka terpikir untuk melakukan hal penting itu. Juga skeptis apakah buku-buku bacaan “tingkat atas” yang Miing sebutkan di awal tulisan ini, sedari Alvin Toffler hingga John Naisbitt, telah mampu memperkaya gizi bagi lawakan mereka.
Sekadar info : Alvin Toffler ngetop di tahun 1970-an dengan buku The Future Shock dan 1980-an dengan The Third Wave. Jadi Bagito nampak telmi karena ia baru menyebutkannya di tahun 1999. Alias “terlambat” sembilan belas tahun lebih kan..boo.
Baru-baru saja Miing Bagito terpilih sebagai Sekretaris Jenderal organisasi Persatuan Artis Seni Komedi Indonesia (PASKI).
Semoga posisinya yang baru ini akan mampu membuka pintu selebar-lebarnya bagi dirinya untuk mewariskan cerita-cerita keberhasilan, kegagalan, juga hikmah atas perjalanan hidupnya sebagai salah satu tonggak sejarah seni komedi di Indonesia. Siapa tahu, sesuai ajaran Robert T. Kiyosaki bahwa “mengajarlah dan Anda akan menerima”, akan menghadirkan mukjijat bagi Bagito 2005. Bangkit dari keterpurukan !
Wonogiri, 8 Mei 2005
Subscribe to:
Posts (Atom)