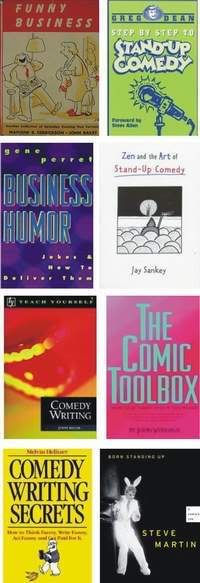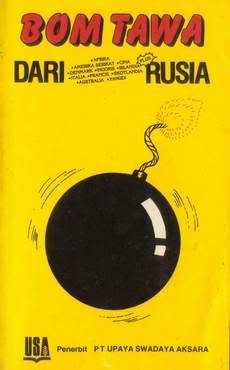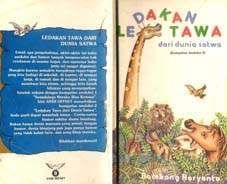Oleh : Bambang Haryanto
Email : humorliner@yahoo.com
September Tidak Ceria. Anda kenal Conan O’Brien ? Kalau Anda sempat menonton siaran tunda MetroTV (3/9/2006) yang menyiarkan Malam Penghargaan Emmy ke 58, Anda akan bertemu dengannya. Saya baru pertama kali melihat sosoknya yang punya tinggi badan 193 cm dan penampilannya dalam menembakkan lelucon-lelucon cerdas khas Amerika.
Pria berwajah agak sayu ini lulusan magna cum laude dari Jurusan Sejarah dan Sastra Universitas Harvard di tahun 1985. Pria cerdas, tentu saja. Boleh jadi Conan O’Brien merupakan tipikal komedian seperti yang pernah dideskripsikan oleh Jay Sankey dalam bukunya Zen and The Art of Stand-Up Comedy (1998). Bisakah judul itu mengingatkan Anda tentang Robert M. Pirsig ?
Jay Sankey bilang, “In my experience, most comics are extremely sensitive, relative unsecure, very insightful, highly intelligent people. Strong individuals rather than group members, with burning desire to share what they think and feel.”
Merujuk pengalaman saya, sebagian besar komedian adalah pribadi-pribadi yang peka, relatif gelisah, berwawasan dalam, orang-orang yang sangat cerdas. Lebih condong sebagai sosok berciri individualis dibanding sebagai anggota suatu kelompok, dirinya memiliki gairah berkobaran untuk berbagi segala hal yang ia pikirkan dan ia rasakan.
Catat penilaian Jay Sankey di atas terhadap apa yang dilakukan Conan O’Brien ketika gedung kembar World Trade Center di New York roboh oleh serangan teroris yang dahsyat, 11 September 2001. Baru seminggu kemudian acara Late Night with Conan O'Brien muncul kembali. Merujuk peristiwa tragis itu telah membuat pria yang lahir 18 April 1963 ini memberikan pengakuan :
“Saya akan berkata jujur kepada Anda : Saya tidak tahu bagaimana harus mengerjakan ini semua. Malam ini saya tidak memiliki gagasan untuk melakukannya. Untuk esok, juga tak ada gagasan. Dan bahkan untuk sepanjang sisa minggu ini saya juga memiliki gagasan bagaimana bisa kembali mengerjakan hal yang sama pula. Itulah semua hal yang kami rasakan.”
Bulan September 2001 di Amerika Serikat memang bukan bulan September ceria. Bahkan seorang Daniel Kurztman menyebutkan terjadinya “pergeseran seismik dalam lanskap budaya kita dan matinya humor.” Amerika memang menghentikan aliran budaya ciri khasnya dalam membuat satir. Amerika dipaksa berhenti untuk tertawa.
Bush Kini Cerdas! Momen duka itu memang tidak terus berlangsung selamanya. Ketika George W. Bush memicu perang untuk menggulingkan Taliban di Afghanistan, sesudah bangsa Amerika melampiaskan duka dan melakukan refleksi, humoris Amerika bangkit kembali. Peluru-peluru satir dan lelucon mereka berledakan kembali.
Humor ternyata sangat diperlukan dalam proses penyembuhan luka nurani bangsa. Bahkan Rudy Giuliani, Walikota New York, pada malam amal di bulan Oktober 2001 berseru : “Saya di sini mengijinkan Anda semua untuk bisa tertawa. Kalau tidak, Anda akan kami tangkap !”
Daniel Kutzman menyimpulkan : “Jauh dari termarginalisasi sebagai hal yang asal-asalan, sembrono dan tidak relevan, komedi terus membantu kita dalam menyembuhkan luka bangsa dan dalam pelbagai hal merupakan barometer bagaimana mood bangsa ini berubah.” Menurutnya, berdasar fakta warga Amerika kini dapat melucukan kebijakan seperti peringatan tentang ancaman serangan teroris, pengetatan keamanan dalam negeri yang berlebihan, tingkah beragam blunder Presiden Bush sampai kemunafikan politik luar negeri AS, semuanya merupakan garis bawah atas semua hal yang terjadi.
Memang belum ada sinyal kembalinya olok-olokan politik seperti yang biasa, tetapi pendekatan untuk selalu mengritisi diri sendiri dengan kacamata humor merupakan satu isyarat bahwa bangsa Amerika telah menjadi normal kembali. Komedian Jay Leno pun segera menimpali : “Kita tidak dapat menampilkan lelucon-lelucon tentang Presiden Bush lagi. Sebab ia cerdas kini !”
SBY : Bener, Pinter, Blunder. Berbeda dengan citra Presiden Bush yang telmi, bloon dan menjadi bulan-bulanan empuk para komedian, kita mungkin bisa disebut beruntung karena memiliki presiden SBY yang dicitrakan sebagai pribadi pinter, pandai dan bener, jujur. Orangnya pun santun. Sosoknya tinggi besar, gagah dan tampan.
Merujuk kualitas pribadinya seperti tersebut di atas, sebenarnya agak buntunglah komunitas komedi Indonesia. Karena dalam kacamata komedi, sosok SBY seperti itu justru merupakan sumber lawakan yang relatif miskin dan kering. Pribadinya yang kurang “bergerigi,” terutama karena karena tidak kontroversial, membuat dirinya relatif lebih sulit untuk dijadikan sebagai sasaran tembak lawakan yang biasa-biasa saja.
Menurut saya, itulah salah satu blunder besar yang terjadi dalam tayangan komedi Republik Mimpi di stasiun televisi swasta MetroTV. Karena tayangan komedi yang berniat melucukan SBY dan Jusuf Kalla, juga pemerintahannya, nampak hanya mengandalkan menu lawakan yang tidak, atau belum, mengolah esensi komedi atau parodi dengan sentuhan kecerdasan yang dibutuhkan.
Sungguh mengherankan, karena berdasarkan latar belakang penggagas dan tim kreatif Republik Mimpi, kita sebenarnya boleh berharap banyak. Karena rasanya baru kali ini orang-orang kampus terjun ikut membidani acara komedi di televisi.
Kita lihat, di sana ada seorang Effendi Gazali, Ph.D, pakar komunikasi yang seolah boleh menulis “apa saja” untuk harian Kompas. Dosen Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi UI ini pernah menjadi juara lawak yang paling “sesumbar,” se-Sumatera Barat. Dalam tayangan ia menjabat sebagai Penasehat Komunikasi Politik Republik Mimpi.
Kemudian, Suko Widodo, MA. Direktur Pusat Kajian Komunikasi Unair serta mantan Fellow VIP (Visitor International Program) dengan Fokus Demokratisasi Media di AS. Dalam acara ini Suko tampil sebagai Penasehat Spiritual Republik Mimpi dan menjadi salah satu think tank untuk tayangan ini.
Orang pintar lainnya yang berada di balik layar sebagai penanggung jawab adalah kolega Effendi Gazali yang sesama pengajar di UI, yaitu Dedy N. Hidayat, Ph.D. dan Pinckey Triputra, Ph.D. Ditambah eksekutif Media Group, Andi F. Noya.
Anggota tim kreatif dan sekaligus sebagai pelakon adalah Butet Kertaradjasa yang memerankan sebagai “SBY” (Si Butet Yogya), Presiden Republik Mimpi. Kemudian Kelik Pelipur Lara sebagai “Ucup Kelik,” Wakil Presiden Republik Mimpi dan kini ditambah pemanis, artis cantik Olga Lydia sebagai Sekretaris Kantor Wakil Presiden.
Apakah ada yang salah dalam tayangan Republik Mimpi ini ?
Character is 98% of Comedy ! Karakter adalah 98 persen komedi. Ini merupakan Hukum Komedi Evans Ketiga. Komedi bukan ibarat tusuk sate, atau untaian tasbih, yang berupa jajaran atau untaian lelucon demi lelucon. Bahkan dalam Hukum Komedi Evans Pertama justru mengatakan, buanglah lelucon-lelucon yang paling lucu sekali pun !
Nampak paradoks. Karena setiap orang tahu skrip komedi melibatkan lelucon, tetapi juga melibatkan karakter, pengembangan, dialog dan cerita. Lelucon yang sensasional tetapi dalam skrip yang salah, berpotensi menghancurkan segalanya, merusak irama dan aliran cerita. Menurutnya, yang dibutuhkan bukan ledakan bom demi bom lelucon, tetapi lelucon yang empan papan, lelucon yang tepat pada tempat yang tepat pula.
Lelucon yang hebat dan alamiah bila muncul dari karakter. Merujuk hal ini maka dalam tayangan komedi sering ditampilkan tokoh-tokoh berseragam kerja yang khas. Mungkin polisi, tentara, dokter, sampai hansip. Melihat seragam mereka, pada benak penonton sudah mengeram pemahaman atau referensi mengenai karakter tipikal tokoh-tokoh tersebut.
Begitu tokoh bersangkutan dihadapkan pada situasi atau setting tertentu, reaksi khas mereka masing-masing berpotensi diolah menjadi komedi yang alamiah. Dirinya tidak perlu melucu. Apalagi bila dirinya ditabrakkan dengan jalan pikiran tokoh lainnya mengenai topik yang sama, potensi kelucuan akan semakin mencuat.
Dalam tayangan Republik Mimpi, karakter masing-masing pelaku belum memperoleh garapan atau pendalaman secara maksimal. Kita para penonton belum memperoleh gambaran tipikal karakter masing-masing tokohnya.
Sekadar contoh, Butet dalam melakukan mimicking sosok Presiden SBY nampak masih terbatas pada ucapan atau pun gesture belaka. Pendekatannya masih secara wadag, fisik belaka. Sampai-sampai untuk mengejar efek tawa dirinya sampai pernah mengeluarkan lelucon berkonotasi seks, menyangkut “burung” dalam isu masalah flu burung. Tetapi karena penonton tidak mempunyai referensi kaitan antara burung dalam pidato SBY, lelucon itu tidak menghasilkan sensasi tawa yang diharapkan.
Butet dan tim kreatif Republik Mimpi nampak belum mampu mengeksplorasi karakter SBY yang, misalnya oleh Sukardi Rinakit (Kompas, 31/8/2006 :6) disebut sebagai pinter, bener (jujur), tetapi tidak banter, alias tidak cepat dan tidak berani menyerempet-nyerempet bahaya. Sementara Tamrin Amal Tomagola (Kompas, 4 September 2006 :7) menjuluki SBY sebagai “pribadi santun” yang “terpuruk dalam kebimbangan.”
Kalau saya menjadi tim kreatif Republik Mimpi saya akan “menembak” SBY sebagai berikut : “Sebagian orang berpendapat, Presiden SBY gantengnya mirip bintang film. Anda setuju ? Saya senang menyamakan dia dengan Lee Majors dalam film seri Six-Million-Dollar Man. Bedanya, di film itu Lee Majors digambarkan secara slow motion untuk larinya yang cepat, sementara SBY harus digambarkan beradegan slow motion untuk aksinya yang selalu saja slow motion !”
Humor memang agresif. Freud pernah menggariskan bahwa humor bersumber dari naluri manusia untuk melakukan agresi, tindak kekerasan. Merujuk hukum itulah, Butet lumayan tampil lucu ketika melakukan mimicking terhadap Soeharto. Kita tertawa karena kuatnya unsur vendetta, ingin melakukan membalas dendam lewat tertawa kepada penguasa Orde Baru yang represif itu. Tetapi ketika Butet melakukan mimicking yang sama terhadap SBY, hasilnya jelas hanya hambar-hambar adanya.
Tokoh Jusuf Kalla sebenarnya lebih menjanjikan untuk menjadi sasaran tembak lawakan. Pribadinya lebih warna-warni dan pendapatnya sering kontroversial. Ide Jusuf Kalla yang menyarankan terjadinya kawin kontrak antara pria Timur Tengah dengan perempuan daerah Puncak, hingga anak keturunannya kelak layak sebagai pemain sinetron, adalah harta karun bahan lelucon yang potensial untuk digali. Sayang, dalam Republik Mimpi, sosok Ucup Kelik lebih senang asyik bermain sebagai dirinya sendiri, dengan modal lelucon-lelucon akronim dan plesetannya belaka.
Freeport vs Freesex. Dalam artikelnya di Kompas (12/8/2006 : 6) Effendi Gazali menulis bahwa yang paling inti dari parodi politik adalah bagian updating . Tanpa itu kadarnya berkurang drastis, atau bukan lagi genre itu. Menurutnya, John Stewart (tepatnya Jon Stewart, pembawa acara The Daily Show with Jon Stewart) menggunakan data dan potongan berita asli untuk dianalisis. Tanpa konteks dengan peristiwa politik yang riil dalam berita, sebuah parodi bisa jatuh pada slapstick, seperti parodi politik pertama di Nippon TV.”
Mungkin saya keliru apabila menyamakan apa yang ia sebut sebagai updating itu dalam konstruksi lawakan adalah yang lajim disebut sebagai premis. Ini bagian lawakan yang tidak lucu, tetapi sangat penting. Karena ini merupakan bagian yang mampu membuat penonton terkait dengan materi lawakan.
Gus Dur ketika muncul di Republik Mimpi (28/8/2006) mengajukan premis, “Apa persamaan antara Ginandjar Kartasasmita dengan Sutrisno Bachir ?” Kita sebagai penonton merasa terkait, karena kedua orang itu sungguh terkenal. Kita pun terbahak ketika Gus Dur meluncurkan jawabannya sendiri, yang lucu, yang lajim disebut sebagai punchline :
“Ginandjar Kartasasmista sibuk dengan Freeport. Sutrisno Bachir sibuk dengan free sex.”
Dalam Republik Mimpi, Effendi Gazali sebagai Penasehat Komunikasi Politik, punya peran sebagai pengumpan. Tukang melontarkan premis demi premis. Sementara punchline diharapkan mampu diledakkan oleh Presiden atau Wakil Presiden.
Ketika ia melemparkan premis bahwa artis Bella Saphira ingin segera menikah, saya telah mengirimkan SMS kepadanya, : “Kehadiran GusDur di RM, bagus sekali. Ia melucukan figur2 dimana kita bs terkait (Perret’s Comedy Law No.2), smentara ‘Bella Saphira’ tak ada apa2nya.”
Buang saja isu-isu gincu semacam “Bella Saphira” itu. Tetapi pilihlah topik-topik updating yang terkait dengan hajat hidup orang banyak. Ketika dalam tayangan 4/9/2006 Effendi Gazali menampilkan kliping acara Global Inter-Media Dialogue di Bali, ini jelas sebuah bias. Juga blunder. Peristiwa semacam ini hanya dianggap besar kalangan esoterik, akademisi dan praktisi komunikasi, tetapi bukan isu yang menarik dan mampu menjangkau hajat hidup orang banyak.
Hemat saya, sebenarnya bencana lumpur panas di Sidoarjo, juga flu burung, masih merupakan isu panas yang tetap lezat untuk bahan lawakan politik. Dengan bercermin dan merujuk contoh kelambanan pemerintah AS dan FEMA ketika mengatasi bencana Badai Katrina, kedua bencana di negara kita itu merupakan topik hangat yang dapat diaduk-aduk sisi-sisi lelucon dan tragikanya.
Merujuk Lapindo Brantas adalah anak perusahaan kelompok Bakrie dan Freedom Institute merupakan organisasi himpunan kaum intelektual dimana keberadaannya juga didukung oleh kelompok bisnis Bakrie, kita dapat mengajukan pertanyaan kritis :
“Apa yang bisa diperbuat oleh Freedom Institute untuk mengatasi bencana lumpur panas di Porong, Sidoarjo ? Memasang iklan satu halaman penuh berisi kajian bahwa kenaikan lumpur panas itu baik bagi rakyat. “
Republik Mimpi Kuatkah Bertahan ? Conan O’Brien mengampu acara Late Night with Conan O'Brien sejak tahun 1993. O'Brien dijadwalkan akan menggantikan Jay Leno sebagai pembawa acara The Tonight Show pada tahun 2009. Dirinya berpredikat sebagai komedian, produser acara televisi dan penulis naskah televisi.
Apa predikat seorang Jon Stewart, yang acaranya The Daily Show With Jon Stewart berusaha dicontek idenya oleh Republik Mimpi ? Ia seorang penulis, produser dan sekaligus pembawa acara. Dalam penganugerahan Emmy 2006 untuk kategori Outstanding Variety, Music or Comedy Series, acaranya meraih penghargaan tersebut. Ia berhasil mengalahkan nominator lainnya seperti The Colbert Report, Late Night With Conan O’Brien, Late Show With David Letterman, dan Real Time With Bill Maher.
Terkait keteladanan sosok Conan O’Brien dan Jon Stewart di atas, maka tayangan komedi di televisi-televisi Indonesia seperti kritik pedas almarhum Prof. Dr. Sudjoko dari ITB (baca “Komedi Banal Indonesia” di bawah ini), haruslah mengandalkan para gag writer, penulis naskah lawakan. Bukan jamannya lagi hanya melulu menyerahkan kepada para pelawak atau artis-artis yang tidak memiliki tradisi dalam kiprah penulisan kreatif. Tanpa revolusi semacam, tayangan Republik Mimpi dijamin bakal tidak mampu lama bertahan.
Sebagai penutup kita mungkin kita dapat belajar bagaimana canggihnya seorang Conan O’Brien mengejek seorang presiden negara adidaya, yang juga pernah kuliah di Universitas Harvard, walau sering digambarkan karakternya sebagai pribadi yang dungu :
“Hari Selasa depan stasiun televisi NBC menjadwalkan edisi acara prime time Meet The Press dengan mengundang kandidat presiden Al Gore dan George W. Bush untuk acara debat pertama mereka. Acara Meet The Press yang normal biasanya diudarakan hari Minggu pagi, tetapi itu merupakan jadwal tetap bagi George W.Bush menonton film kartun.”
Wonogiri, 6-7 September 2006
ke
Tuesday, September 05, 2006
Komedi Banal Indonesia
Budayawan senior Prof. Dr. Sudjoko ditemukan meninggal dunia di rumahnya di Jl. Golf Barat XX No. 7 Arcamanik Kota Bandung, Jumat (25/8) pukul 17.30 WIB. Diperkirakan budayawan yang terkenal dengan wawasan dan minatnya yang luas ini, meninggal sejak tiga hari sebelumnya.
Sebagai pemerhati dunia komedi, saya teringat kritik beliau tentang karut-marut dunia komedi Indonesia yang menyedihkan. Pendapatnya ia tulis dalam mengantar buku karya Arwah Setiawan, Humor Jaman Edan (Jakarta : Grasindo, 1977).
Menurut beliau, dunia komedi Indonesia itu keblinger. Karena kita selalu mencari pelawak dulu, atau artis-artis dulu yang mengaku gampang melucu, sebab toh sama saja dengan celoteh sehari-hari. Modus acara reality show model API (TPI) dan dulu Meteor Kampus (AnTV) merujuk pada sikap keblinger tersebut. Toh dari ajang tersebut ternyata dewasa ini tidak mampu melahirkan bakat-bakat baru pelawak yang patut dibanggakan.
Menurut Prof. Sudjoko, yang paling utama untuk digenjot kreativitasnya adalah para penulis lakon. Sebuah tantangan berat. Karena selama ini penulis, seperti halnya sosok almarhum Arwah Setiawan, tidak pernah masuk pikiran dan bayangan bangsa kita tentang pembanyol.
Semua yang kita kenal sebagai pelawak, badut, bodor, klontangan, ludruk dan sebagainya adalah pelakon, orang panggung, orang tontonan. Mereka itu bukan penulis, bukan sastrawan. Dalang juga bukan penulis. Semua (mereka itu) tidak mampu menulis.
Merujuk tingginya ketidakmampuan menulis dan tingginya budaya mohbaca (istilah unik dari beliau yang juga seorang munsyi, ahli bahasa) sebagai akibatnya canda bangsa Indonesia sehari-hari cuman sentilan, olokan dan ejekan lepas-lepas. Dan supaya tawanya sering, banyak olokan cuma dibuat-buat saja, tanpa ditopang oleh akal pikir atau renungan.
Tayangan komedi model tayangan Extravaganza di TransTV, misalnya, jelas merupakan tayangan yang mencerminkan kebanalan atau kedangkalan bangsa ini seperti yang disinyalir oleh almarhum sejak lama itu. Sampai kapan ada perbaikan dan kemajuan ?
Selamat jalan, Pak Djoko. Semoga Anda kini damai dan sejahtera di sisiNya.
Bambang Haryanto
Jl. Kajen Timur 72 Wonogiri 57612
Warga Epistoholik Indonesia
Catatan : Tulisan ini dengan penyuntingan telah dimuat di kolom Surat Pembaca Harian Kompas Jawa Tengah, Selasa, 5 September 2006.
ke
Sebagai pemerhati dunia komedi, saya teringat kritik beliau tentang karut-marut dunia komedi Indonesia yang menyedihkan. Pendapatnya ia tulis dalam mengantar buku karya Arwah Setiawan, Humor Jaman Edan (Jakarta : Grasindo, 1977).
Menurut beliau, dunia komedi Indonesia itu keblinger. Karena kita selalu mencari pelawak dulu, atau artis-artis dulu yang mengaku gampang melucu, sebab toh sama saja dengan celoteh sehari-hari. Modus acara reality show model API (TPI) dan dulu Meteor Kampus (AnTV) merujuk pada sikap keblinger tersebut. Toh dari ajang tersebut ternyata dewasa ini tidak mampu melahirkan bakat-bakat baru pelawak yang patut dibanggakan.
Menurut Prof. Sudjoko, yang paling utama untuk digenjot kreativitasnya adalah para penulis lakon. Sebuah tantangan berat. Karena selama ini penulis, seperti halnya sosok almarhum Arwah Setiawan, tidak pernah masuk pikiran dan bayangan bangsa kita tentang pembanyol.
Semua yang kita kenal sebagai pelawak, badut, bodor, klontangan, ludruk dan sebagainya adalah pelakon, orang panggung, orang tontonan. Mereka itu bukan penulis, bukan sastrawan. Dalang juga bukan penulis. Semua (mereka itu) tidak mampu menulis.
Merujuk tingginya ketidakmampuan menulis dan tingginya budaya mohbaca (istilah unik dari beliau yang juga seorang munsyi, ahli bahasa) sebagai akibatnya canda bangsa Indonesia sehari-hari cuman sentilan, olokan dan ejekan lepas-lepas. Dan supaya tawanya sering, banyak olokan cuma dibuat-buat saja, tanpa ditopang oleh akal pikir atau renungan.
Tayangan komedi model tayangan Extravaganza di TransTV, misalnya, jelas merupakan tayangan yang mencerminkan kebanalan atau kedangkalan bangsa ini seperti yang disinyalir oleh almarhum sejak lama itu. Sampai kapan ada perbaikan dan kemajuan ?
Selamat jalan, Pak Djoko. Semoga Anda kini damai dan sejahtera di sisiNya.
Bambang Haryanto
Jl. Kajen Timur 72 Wonogiri 57612
Warga Epistoholik Indonesia
Catatan : Tulisan ini dengan penyuntingan telah dimuat di kolom Surat Pembaca Harian Kompas Jawa Tengah, Selasa, 5 September 2006.
ke
Subscribe to:
Posts (Atom)