Oleh : Bambang Haryanto
Email : humorliner@yahoo.com
Pelawak Itu Pribadi Gelisah. Steve Martin sedang duduk bersama tiga temannya di bawah keteduhan payung di pelataran restoran di California Selatan. Ia menyeruput kopi dan intuisinya berbisik, ada seorang fans mendekatinya. Segera ia menegakkan kerah jaket dan bergaya tak acuh di balik kacamata hitamnya.
Fans yang mendekat itu seorang wanita bertubuh subur. Dengan bergaya centil dan seolah mengajak bercanda, ia sodorkan kertas dan bolpen. Steve Martin tersenyum, lalu menuliskan tanda tangannya. Fans itu segera berlalu dengan riang hati, tetapi kepada suaminya ia mengeluh : “Steve Martin tidak mengatakan hal lucu sepatah kata pun !”
Tuntutan sulit bagi seorang Steve Martin. Dirinya memang tidak pernah menyediakan atau membawa-bawa stok lelucon seperti halnya Bob Hope atau George Burns. Ia juga tidak pula bisa langsung nyetel dalam berimprovisasi seperti halnya komedian Jonathan Winter atau Robin Williams.
Begitulah, gara-gara dirinya meroket sebagai komedian solo yang sukses secara fenomenal di era 70-an, ia selalu diharap mampu melucu setiap saat. Di mata para penggemarnya Steve Martin adalah sosok yang harus selalu siap melucu setiap saat seperti ketika naik panggung, gila dan liar, lincah bertingkah, berkuping kelinci atau tampil sebagai binatang berbentuk balon.
Tetapi berbeda dibanding penampilannya di panggung dan persona di layar putih, Steve Martin adalah pribadi yang serius, demikian tulis wartawan Cork Millner di majalah Saturday Evening Post (Nov-Des, 1989). “Ia cerdas dan canggih”, timpal Shelley Duvall, teman mainnya dalam film larisnya, Roxanne. Steve Martin berpendidikan doktor filsafat.
Kebanyakan pelawak memang pribadi yang sangat cerdas. Demikian kesimpulan Jay Sankey dalam bukunya Zen and The Art of Stand-Up Comedy (1998). Selain itu pelawak juga sangat sensitif, pribadi yang relatif gelisah, dan punya pisau pengamatan yang tajam. Sosoknya lebih condong sebagai individuil yang kuat ketimbang anggota sesuatu kelompok. Dirinya dikaruniai dorongan membara untuk berbagi segala apa yang ia fikirkan dan ia rasakan. Perspektif yang ia pilih adalah sebagai orang luar, outsider, pengamat.
Penonton Kita Belum Cerdas ? Aming Sugandhi, pemeran tokoh waria dalam acara komedi Extravaganza di TransTV, juga berpendapat senada. Ketika ditanyakan kepadanya oleh wartawan Kompas, Edna C. Patiasina, apakah dirinya aktor atau pelawak, Aming pun menjawab : “Aku belum siap memikul beban sebagai pelawak. Buat aku itu profesi yang sangat keren, tidak semua orang punya kapasitas seperti itu”
Menurut dia, menjadi sosok pelawak membutuhkan kecerdasan jauh di atas rata-rata. Pelawak harus mampu menangkap umpan lelucon untuk kemudian dikembangkan sendiri. Hal ini berbeda dengan apa yang dijalaninya selama ini. Dalam Extravaganza, misalnya, Aming berakting berdasarkan skenario yang telah disusun. “Kita masih berputar-putar di komedi slapstik, mungkin karena kultur kita belum siap menerima komedi cerdas”, ucap Aming (Kompas, 7/8/2005).
Pendapat Aming, yang mahasiswa jurusan Kriya Tekstil Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB itu, tentang “kultur kita belum siap menerima komedi cerdas”, boleh-boleh saja ia lontarkan. Sudah lajim dan layak bila dirinya membela format tayangan komedi di mana ia berkecimpung, mencari nafkah di dalamnya. Aming bahkan tidak sendirian. Pelawak Wahyu Sardono atau Dono Warkop almarhum juga pernah mengatakan hal yang sama, ketika bersama kelompoknya Warkop DKI sedang berkibar dengan film-film slapstiknya.
Seperti tertuang dalam artikel berjudul “Dono dan Tolak Politisi Busuk”, (Kompas, 30/12/2003), yang ditulis Effendi Gazali, dosen Pascasarjana Komunikasi UI dan Research Associate di Nijmegen University, Belanda, Dono memimpikan hadirnya lawakan cerdas tetapi saat itu belum mungkin. Hal ini, menurutnya, terjadi akibat tekanan kebijakan TVRI saat itu, juga tekanan politik dan ekonomi di era Orde Baru yang represif.
Effendi Gazali yang di tahun 1983, ketika duduk di SMA adalah juara melawak se-Propinsi Sumatera Barat, kemudian mengutip pertanyaan Dono : “Mungkinkah bikin lawakan a la Jay Leno atau David Letterman Show ?” Effendi pun membalas : “Kalau rakyat kita selalu dianggap tidak mampu mengerti lawakan cerdas, cita-cita itu pun akan menjadi in your dreams.”
Kini, ketika Orde Baru sudah tumbang, saat stasiun-stasiun televisi relatif bebas membuat acara yang tidak mendapat represi dari pemerintah, sialnya anggapan bahwa penonton kita dianggap tidak mampu mengerti lawakan cerdas, masih saja muncul.
Bangun, Aming, ayo bangun !
Ijinkanlah saya ikut berpendapat : sebenarnya penonton komedi kita senyatanya sudah semakin cerdas, tetapi hanya para komedian kita saja (juga para penulis naskah lawakan di televisi-televisi kita) yang tidak pernah menjadi semakin cerdas !
Lawak Gaya Keroyokan ! Suguhan komedi di televisi-televisi kita, bila menurut istilah komedian Sam Greenspan, barulah berkualitas tayangan yang menampilkan komedian pamer hidung dan komedian biang kerok. Dirinya telah membagi tiga jenis komedian.
Golongan pertama, ia istilahkan sebagai komedian pamer hidung. Ia adalah paman atau kakek Anda, atau siapa pun, yang melucukan seputar kejadian keluarga. Untuk memperoleh tawa ia melakukannya dengan menggelitik anak kecil dengan hidungnya. Leluconnya dangkal, rasis atau berbau SARA, berbau seksual, dan berselera rendah. Kelompok demografi penggemar terbaiknya : 0 – 6 tahun.
Golongan kedua adalah komedian biang kerok. Leluconnya tidak cerdas, juga tidak asli, ia melakukan aksinya semata ingin menjadi pusat perhatian. Di kelas, ia memasang pensil pada lubang hidungnya. Meninggikan nada sendirian ketika bernyanyi koor. Pelawak jenis ini kita temui ketika kita duduk sampai bangku SMA.
Golongan ketiga, adalah komedian solo, atau stand-up comedian, yang ia sebut sebagai seseorang yang memanggungkan komedi di muka audiens sebagai profesi dan untuk memperoleh nafkah. Sam Greenspan menyebut contoh : dirinya sendiri. Atau George Carlin.
Komedian golongan ketiga ini di Indonesia, menurut pengetahuan saya, masih ditunggu kehadirannya. Karena memang belum ada. Mungkin karena kentalnya semangat bergotong royong pada bangsa ini, bahkan juga dalam melakukan korupsi, maka pentas lawak kita yang lajim adalah pentas model gotong royong pula.
Mainnya model keroyokan. Anda dapat menunjuk pada sosok kelompok Srimulat, Ketoprak Humor, Bagito, Patrio, Cagur sampai pentas pelawak baru hasil karbitan Audisi Pelawak TPI (API). Dan, tentu saja, juga Extravaganza di mana Aming bermain di dalamnya. Dalam tayangan semacam ini yang dibutuhkan hanya aktor-aktor. Baik itu pelawak atau bukan pelawak. Baik memakai naskah yang harus ketat dipatuhi atau pun pelakunya dibebaskan untuk berimprovisasi.
Monyet Muntah-Muntah. Menurut muatan lawakannya, seorang Steve Silberberg, moderator newsgroup alt.comedy.standup, pernah membagi kategori pelawak. Yang pertama adalah pelawak yang lawakannya mengandung pesan-pesan untuk ia sampaikan. Golongan ini jarang-jarang eksis, tetapi dirinya mampu melawak sekaligus menebarkan pesan.
Golongan pelawak seperti inilah yang disinggung oleh Jay Sankey sebagai pribadi yang dikaruniai radar peka yang terus jalan, cermat menguping tiap pembicaraan, mengamati peristiwa yang terjadi di sekelilingnya, dan mencatat pula kesan dan pikirannya tentang semua hal yang ia observasi.
Semuanya itu ia olah dan menjadi siraman bensin guna mengobarkan bara semangatnya untuk selalu berbagi. Ia pun menuliskan lawakannya sendiri. Tidak ayal, karena sodokan komentar-komentar tajam dari para pelawak kategori intelektual dan cerdas ini, menurut Jay Sankey, sering mengantarkan diri mereka mampu meraih julukan sebagai filsuf yang blak-blakan, pemimpi anarkis, atau bahkan pahlawan sosial.
Sudah hadirkah pelawak atau komedian seperti ini di panggung-panggung komedi kita selama ini ? Saksikan dan silakan mencatat sendiri dari pentas lawakan di televisi kita selama ini.
Bagi saya, yang menonjol di televisi-televisi kita adalah suguhan acara humor yang hanya semakin riuh dengan para pelawak jenis yang kedua. Yaitu para pelawak yang misinya tampil di panggung semata-mata berambisi memperoleh tawa dari penontonnya. Tidak ayal, seorang Steve Silberberg kemudian mempunyai pendapat khas untuk para pelawak jenis kedua ini :
If they bought/stole/used someone else's material, they'd be no more than a talking monkey on stage regurgitating other people's thoughts.
Bila mereka membeli/mencuri/menggunakan materi lawakan karya orang lain, maka mereka itu tidak ubahnya sosok kera yang mampu bicara, yang tampil di panggung, untuk muntah-muntah mengeluarkan karya buah pikir orang lain.
Betul atau tidak : bila kita kini hampir tiap hari semakin sering melihat “kera-kera yang bisa ngomong dan muntah-muntah” itu di layar televisi kita ? Ucapan Aming yang dimuat di Kompas (7/8/2005) bahwa “komedi itu harus digarap dengan serius”, semoga dapat membangunkan kesadaran pada seluruh stakeholder dunia komedi kita.
Betul, Aming, dunia komedi kita memang menuntut perhatian yang lebih serius lagi. Semoga Anda bisa ikut serta memulainya !
Wonogiri, 7-8 Agustus 2005
Subscribe to:
Post Comments (Atom)






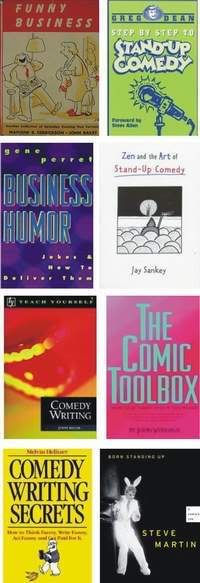
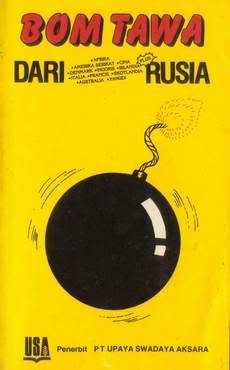
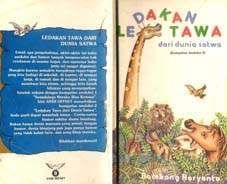



No comments:
Post a Comment