Email : humorliner@yahoo.com
 Badut-badut Kampus. Aksi pelawak ternyata bisa juga menjadi motivator tim bola basket. Itulah yang terjadi pada diri Devin O’Connor, mahasiswa senior dari Jurusan Teater Penn State University, AS. Seperti dikutip oleh Megan McKenna dalam situs universitas tersebut, The Collegian, si Devin O’Connor itu selalu hadir dalam pertandingan basket di kampusnya dengan memakai kostum yang aneh-aneh.
Badut-badut Kampus. Aksi pelawak ternyata bisa juga menjadi motivator tim bola basket. Itulah yang terjadi pada diri Devin O’Connor, mahasiswa senior dari Jurusan Teater Penn State University, AS. Seperti dikutip oleh Megan McKenna dalam situs universitas tersebut, The Collegian, si Devin O’Connor itu selalu hadir dalam pertandingan basket di kampusnya dengan memakai kostum yang aneh-aneh.“Awalnya hanya untuk lucu-lucuan, tetapi kemudian dirinya menjadi pemandu sorak tidak resmi dari tim universitas kami karena ia mampu menggairahkan suasana pertandingan,” tutur Kevin Scheler, teman Devin, yang mahasiswa Kinesiologi.
Mahasiswa lain, Jason Yanushonis, dari Jurusan Finance dan teman Devin di SMA menimpali bahwa O'Connor mampu membawakan selera humornya yang energetik kemana pun ia berada. “Anda tak dapat menduga apa yang akan meletup dari dirinya,” tegasnya. “Ia adalah sosok yang semua orang menginginkan dirinya hadir dalam pesta mereka, karena O’Connor mampu membuat suasana pesta menjadi berbeda.”
Badut sejak SMA itu kini memantapkan diri sebagai komedian mahasiswa yang berprospek cerah. Ia telah manggung di Universitas Yale dan Pittsburg, dan juga tampil sebagai pemenang dalam kontes Comic Strip Live Comic of the Month Contest di New York. “Saya suka kampus karena tipe komedi saya cocok dan terkait erat dengan situasi kampus,” jelas O’Connor.
Simak juga cerita Susan Johnston tentang Alison Block, cewek mahasiswa tingkat pascasarjana jurnalistik di Universitas Duke. Siangnya kuliah dan kalau malam manggung sebagai komedian. Digambarkan betapa Alison sehari-harinya senantiasa memasang antena otaknya, peka menguping ucapan atau pun situasi sekelilingnya yang mampu memicu imjinasi dan diolahnya menjadi lelucon. Selain menulis leluconnya sendiri, memanggungkannya, ia juga menyanyi, menulis fiksi, skenario dan juga menulis lagu. “Utamanya aktivitas yang tidak menghasilkan uang,” candanya. Tetapi jelas teramat vital bagi dirinya, karena akan mengasah tajam pisau intelektualitasnya.
Bagaimana potret aktual dunia komedi mahasiswa kita ?
Di negeri kita ini pasti akan mudah kita ketemukan badut-badut mahasiswa yang suka membuat ulah lucu atau sok lucu di pelbagai kampus. Mungkin mereka beraksi di dalam kelas saat kuliah atau berani naik panggung-panggung hiburan internal kampus mereka masing-masing. Tetapi di tingkat nasional, di mana kini hidung para pelawak mahasiswa semacam Devin O’Connor atau Alison Block di atas ? Bagimana kalau pertanyaan ini dilontarkan kepada Effendi Gazali ?
Kira-kira, mampukah ia menjawabnya ?
Jawaban telak dan tak terduga-duga, sekaligus mungkin benar, mungkin justru muncrat dari sinyalemen tajam dan sarkastis yang pernah dilontarkan oleh almarhum Sudjoko. Beliau adalah budayawan, ahli bahasa dan guru besar Seni Rupa dari ITB Bandung.
Kebetulan adik saya, Basnendar Heriprilosadoso, saat ini sedang menempuh pascasarjana di Seni Rupa ITB. Ia mengajar di ISI Surakarta, seorang kartunis dan desainer logo, di mana salah satu karya puncaknya adalah logo Galeri Nasional di bilangan Gambir Jakarta Pusat. Ketika merujuk sinyalemen Pak Djoko di atas ia telah saya titipi pesan yang mungkin rada aneh : untuk memotret coreng-moreng yang ada di tembok-tembok WC kampus ITB. Karena di lokasi inilah kejeniusan mahasiswa Indonesia, utamanya mahasiswa ITB, mampu terekspresikan dalam kualitas puncak, sehingga mampu mengundang bahak dan menarik perhatian Pak Djoko itu.
Bawa Pulang Alya Rohali. Di atas saya telah mencoba bertanya kepada Effendi Gazali (EG). Mengapa ? Karena ia seorang doktor dan pengajar di Universitas Indonesia. Seorang intelektual di bidang komunikasi dan menurut penuturan teman dunia maya saya, Ira Lathief, saat menulis buku Kumis Lele Rezeki Arwana dan meminta endorser untuk bukunya itu, tokoh “Dik Pendi” dari Republik Mimpi (RM) tersebut telah menuliskan di bawah namanya, sebuah gelar keren : stand-up comedian.
Di acara Republik Mimpi itu dirinya mendapatkan mitra Iwel Well, yang kebetulan sama-sama berasal dari Sumatra Barat. Tokoh dengan peran redundant di Republik Mimpi ini suka EG promosikan sebagai stand-up comedian pertama di Indonesia. Lucunya, di acara Republik Mimpi itu keduanya selalu nampak hanya berposisi sebagai sit-down (sekaligus sitting duck ?) comedian belaka. Masih muda sekaligus berjulukan the most eligible bachelor tetapi tak mampu “berdiri,” bukankah ini sebuah bencana ke-manusia-an ?
Lupakan lelucon low comedy itu. Saya ingin bertanya juga karena Effendi Gazali adalah kreator acara Republik Mimpi yang selalu menghadirkan para mahasiswa. Mereka hadir berombongan dengan selalu mengenakan jaket alma mater dan bahkan bersama dosen-dosen mereka, dalam siaran langsungnya. Selain acara Republik Mimpi, silakan Anda daftar sendiri acara-acara di televisi yang kurang lebih memiliki genre serupa yang menghadirkan para mahasiswa sebagai audiens dalam acara televisi mereka. Pertanyaan lanjut saya : apakah hanya pantas sebagai audiens acara komedi di televisi sajakah yang bisa diperankan oleh mahasiswa kita sekarang ini ?
Kalau jawabannya memang benar, maka saya mudah teringat pernyataan seorang Robin Day (1923 – ), broadcaster Inggris, yang berkata bahwa televisi itu subur berlandaskan ketidaknalaran dan ketidaknalaran juga subur di televisi. Televisi menyentuh emosi daripada intelek. Apakah acara komedi di televisi kita hanya menjadi etalase ketidaknalaran dan ketidakintelektualan insan-insan cendekia kita ? Pengalaman pribadi saya ketiksa bersentuhan dengan televisi kira-kira memang menegaskan hal-hal miring seperti itu.
“Bawa Pulang Alya Rohali !” adalah tagline yang saya buat ketika mengikuti acara kuis Siapa Berani ? di stasiun televisi Indosiar, 12 Maret 2002. Slogan itu tertulis di kaos dan juga mencuat sebagai lirik lagu yang kami bawakan, sebagai ekspresi kontingen Asosiasi Suporter Sepakbola Indonesia (ASSI), organisasi payung suporter sepakbola Indonesia yang turut saya bidani kelahirannya. Regu lainnya adalah kelompok suporter Aremania (Arema Malang), The Jakmania (Persija Jakarta), Pasoepati (Pelita Solo) dan Viking (Persib Bandung).
Helmy Yahya, kreator acara kuis keroyokan itu, di koran The Jakarta Post bilang bahwa acaranya yang ia pandu bersama Alya Rohali dan diikuti para penggila sepakbola ini merupakan salah satu yang terbaik. Tetapi sekaligus paling tercoreng, karena seusai kuis terjadi keributan parah, perkelahian antara dua kelompok suporter yang secara tradisional telah lama berseteru. Bahkan kemudian diikuti insiden penganiayaan berat saat itu.
Potret yang ingin saya garis bawahi ketika mengikuti kuis itu adalah suasana yang khas televisi : kentalnya rekayasa agar semua hal yang tersaji di layar nampak meriah, heboh, ceria, menggembirakan. Ketika Anda dan kawan-kawan nampak melempem, maka akan ada petugas televisi yang berusaha “membakar” Anda untuk kembali bergairah. Bagaimana kalau teknik rekayasa semacam ini juga dicangkokkan dalam acara komedi di televisi ?
Komedi-komedi kita yang sesat. Rekayasa yang sangat kental itulah yang sekarang tersaji dalam acara komedi di televisi kita. Saya mendapatkan pencerahan akan bahaya rekayasa tersebut dari teman diskusi saya di dunia maya, Isman H. Suryaman, pemilik blog The Fool dan penulis buku Bertanya atau Mati. Dalam emailnya (20/7/2007) Isman menulis :
“Pada dasarnya, kalau kita sekadar mengandalkan umpan balik penonton untuk menilai apakah komedi itu baik atau buruk, kita akan tersesat. Seperti menanyakan jalan keluar kota kepada orang yang tidak pernah keluar rumah. Extravaganza (acara komedi sketsa di TransTV-BH) masih terjebak pada hal itu. Karena ditayangkan di hadapan penonton asli, hal yang memancing gelak tawa penonton di panggung dianggap (sebagai) formula keberhasilan.
Padahal seperti diamati produser Chuck Barris (yang menciptakan Gong Show dan The Dating Game), perilaku penonton panggung dan penonton TV jauh berbeda. Saya menunggu sketsa komedi Indonesia yang dimainkan tanpa penonton. Seperti yang dirintis Monty Python. Atau jangan-jangan untuk itu harus seperti kru Monty Python sendiri, terdiri dari lulusan universitas dan magister dulu? “
Isman mungkin harus rela menunggu waktu yang teramat panjang agar harapannya yang positif dan ideal itu bisa direalisasikan. Karena para mahasiswa kita yang entah kena suntik borax, formalin atau dicekoki nitrous oxide atau laughing gas, nyatanya lontaran kalimat yang selalu berulang seperti “gitu saja kok repot” atau “piss, man” ternyata sudah mampu menggelegarkan tawa kompak mereka saat menjadi bagian siaran di televisi.
Begitulah kiranya, televisi itu memang subur berlandaskan ketidaknalaran dan ketidaknalaran juga subur di televisi. Begitulah, televisi menyentuh emosi daripada intelek. Termasuk intelektual para mahasiswa kita yang kemudian seperti tumpul karenanya. Kita tunggu saja Isman, siapa tahu sesudah mereka lulus dan juga menempuh magister, akan mampu mendongkrak selera humor mereka jadi lebih meningkat. Walau jangan terlalu optimistis.
Kembali ke Prof. Sudjoko almarhum.
Ketika mengikuti kontes Mandom Resolution Award 2004, saya berkenalan dengan peserta lain, seorang desainer produk, Bambang Kartono Kurniawan (BKK). Asal Jepara. Sambil ngobrol di kamarnya, di Hotel Borobudur, sebelum kami menghadapi dewan juri Sarlito Wirawan Sarwono, Tika Bisono dan Maria Hartiningsih, saya baru tahu dirinya masih memiliki hubungan keluarga dengan Dr. Sudjoko dari ITB itu. Ketika beliau meninggal dunia, saya mendapatkan tembusan isi milis dari BKK yang ditulis para mantan mahasiswanya. Salah satu milis itu ditulis Susiawan (Toronto, Canada), tertanggal 27 Agustus 2006. Isinya antara lain :
Pak Djoko memang suka tak suka harus mengarus dari tanah seberang, namun ketika beliau sudah kukuh sebagai pengajar senior di SR-ITB, saya pribadi sebagai mahasiswa 'bengal saat itu (terutama di periode 1978-1982an) merasakan bahwa beliaulah satu-satunya dosen yang selalu lantang mengkritisi kualitas pendidikan dan sikap mahasiswa-mahasiswanya. Tentu saja beliau disegani bahkan ditakuti banyak mahasiswanya, tapi tak termasuk saya. Setelah beliau, Alm. Prof.Mochtar Apin dan Alm. Dr.Sanento Yuliman merupakan mentor-mentor terbaik saya. Sewaktu saya menjabat Presiden KMSR…pernah terlibat diskusi, ‘ini diskusi antara Susiawan dan Sudjoko, titik !’ tandasnya serius.
Bahkan dengan beliau, kami sempat membahas coretan-coretan iseng mahasiswa-mahasiswa di kamar kecil SR-ITB. Yang mengesankan ketika beliau secara khusus mengkritisi coretan mahasiswa yang berbunyi "Merdeka tapi bingung", "Lapar menyebabkan Perang, Perang menyebabkan Kelaparan", lalu ada yang menjawab "Lapar dan Perang dibuat-buat !" Ditimpa dengan coretan "Siapa dong yang kenyang ?". Ha ha ha ha...menggelikan sekali, kadang-kadang saya terbahak-bahak sambil kencing !
Beliau heran, setiap tembok WC itu diputihkan kembali, esoknya tumbuh coretan-coretan lagi hingga penuh ! Beberapa teman sampai-sampai ketagihan ke WC hanya ingin baca 'pemikiran-pemikiran baru' itu. "Ada yang baru nggak ?" Bahkan di 'edisi 1978' tembok WC itu penuh coretan-coretan yang politis.
Dilain pihak, pak Djoko heran dan bertanya-tanya dengan sinis "Mengapa WC itu penuh dengan coretan-coretan yang kadang sangat cerdas atau filosofis, tapi rata-rata tulisan mahasiswa di skripsi mereka kosong gagasan-gagasan baru ?" "Kalau diformalisir mereka jadi 'gagu', tapi kalau 'lepas pengawasan' justru banyak yang menunjukkan kualitasnya," tambahnya. Itu kata-kata beliau yang tak mudah saya lupakan. Entah, mengapa beliau menyempatkan diri ke WC mahasiswa sambil baca 'buku tembok itu ?
Terima kasih, Mas Susiawan.
Selamat jalan, Pak Djoko.
Kalau saja saya tinggal di Bandung, rasanya saya akan ikut kepingin menikmati isi “buku tembok” WC kampus ITB saat itu. Adik saya juga belum mengirimkan hasil pemotretannya. Ataukah mungkin tembok WC ITB itu kini sudah diputihkan sehingga steril dengan gagasan-gagasan baru ?
Saya yakin, isi tembok WC yang dilukiskan oleh Susiawan itu jauh lebih inspiratif dan humoristis daripada lelucon yang membuat gerombolan demi gerombolan mahasiswa kita ibarat useful idiot yang gagu isi kepalanya, yang bangga memakai jaket alma maternya, tetapi riuh rendah tertawa-tawa hanya dicekoki sajian low comedy yang mekanistis, repetitif sekaligus dangkal, di pelbagai acara televisi kita selama ini.
Tanya kenapa !
Wonogiri, 12/8-9/9/2007
ke






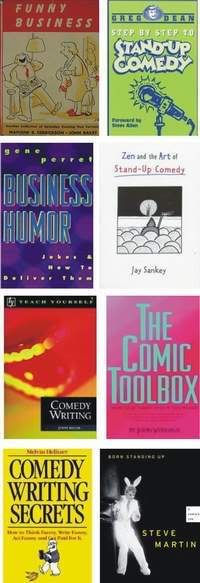
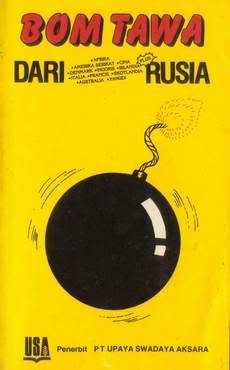
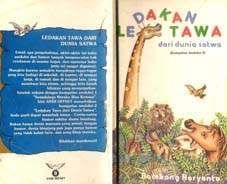



Menurut saya sih salah satu penyebab utamanya memang karena sistem yang membuat batasan formalnya bersifat mengekang, alih-alih membebaskan. Jadinya kreativitas selalu tersalur melalui jalur alternatif. Paling populer ya tembok WC umum.
ReplyDeleteSekalangan teman SR ITB memiliki media yang bernama komik hujat, di mana mereka bisa bebas berkreasi dalam bentuk komik. Ide maupun humor di dalamnya sering kali mengagumkan. Padahal hanya membahas topik remeh-temen, seperti kebiasaan teman-teman atau kejadian sehari-hari.
Sayangnya, ide dan humor seperti itu malah justru jarang saya temukan pada komik terbitan lokal. Dengan kata lain, para pencipta atau pelaku humor kita mungkin tidak terbiasa untuk memanfaatkan batasan formal (suatu industri, misalnya) dalam menghasilkan karya yang menghibur. Mereka bisa kala bebas menciptakan batasan mereka sendiri.
Ini mungkin bisa dikaitkan dengan sistem pendidikan formal yang membentuk orang-orang seperti itu: hanya bisa berkreasi penuh ketika mencipta batasan sendiri. Padahal, kita tahu bahwa di dunia nyata, semua bidang atau industri memiliki batasan formalnya sendiri. Dalam industri buku: ada batasan kualitas, kategori, hingga tren pasar. Dalam humor tentunya ada batasan materi hingga wadah.
Jadi intinya, ini mungkin bermuara pada sistem pendidikan formal umumnya yang tidak mengajarkan berpikir kreatif. Fokus terlalu banyak pada berpikir teoretis. Sering kali bahkan belum cukup kritis. Atau bahkan praktis.
Mengenai sistem pendidikan ini sendiri, di ITB pernah ada pertanyaan yang belum terjawab: bagaimana cara mengajarkan berpikir kreatif, ketika semua pengajarnya adalah hasil didikan sistem yang tidak mengajarkan untuk berpikir kreatif?
Solusinya tentu saja mudah: harus ada yang memulai dengan cara berbeda. Karena lingkaran setan tidak bisa dipatahkan hanya dengan mengikuti arus dan berharap bisa mengubah dari dalam.
Intinya:
1) Kita terkondisikan untuk berpikir teknis, dan lemah untuk berkreasi dalam batasan
2) Ini hasil didikan sistem yang menitikberatkan pada teori dan penggunaannya. Bukan pada inovasi dan kreasi.
3) Humor adalah pendobrakan batas dan pengejutan suatu pola/persepsi. Karena itu inovasi dan kreasi dalam batasan justru merupakan dua hal penting.
Thanks, Isman. Saya setuju dengan opinimu. Pendidikan kita terlalu dicengkeram oleh dominannya para "guru kurikulum" dan kurang atau tak ada tempat untuk para "guru inspiratif" seperti ditulis oleh Rhenald Kasali di Kompas waktu yang lalu. Maka, kita masih tunggu kiprah para mahasiswa yang berani "memberontak," membawa keluar apa yang ia goreskan di WC-WC kampusnya, ke panggung lawakan. Hallo, bisakah ITB memulainya ?
ReplyDeletewc seni rupa sekarang sudah bersih, jadi sekarang wilayah mahasiswa untuk 'mengamuk' pun sudah ditekan...hehehehe jad bingung mahasiswa harus mengamuk dimana
ReplyDeletesempat sih si wc informatika muncul coreatn "KITA SATU ITB", tampaknya frustasi dengan kondisi kemahasiswaan ITB sendiri, paling ynag masih sedikit rame itu di gku barat dan timur itupun warisan tahun 90'an
ReplyDelete