Oleh : Harry Tekssi*
PKJT Sasonomulyo Solo
I
MENDIANG PRESIDEN KENNEDY yang konon pernah digunjing akibat kisah-kisah asmaranya, baik ketika hidup mau pun sesudah mengalami hari naas di Dallas, kisahnya tak luput dijadikan bahan humor. Ketika masih hidup, antara lain pada suatu jumpa pers 15 Februari 1962, beliau mengkhawatirkan akan timbulnya suatu gegeran sosial di negerinya akibat otomatisasi.
“Tantangan di dalam negeri yang besar pada tahun enampuluhan ini”, begitu kata dia, “adalah usaha mempertahankankan secara penuh lapangan kerja apabila otomatisasi telah menggantikan kerja-kerja manusia”
Di sini sang dedengkot The New York Times, James Reston, nyeletuklah : “Mesin-mesin nampaknya akan menggantikan segalanya di negeri ini kecuali mungkin hanya cewek-cewek cakep body asoy dan Presiden Kennedy sangat mengkhawatirkan hal ini”
Cerita lain diambil dari satu adegan film Nashville karya sutradara Robert Altman : ketika tiba-tiba seorang penyanyi di panggung ditembak mati oleh seorang gila. Sang korban itu, anehnya, beberapa saat kemudian terbangun lagi, hidup kembali. Malah teriak keras-keras, “Saudara-saudara, ini bukanlah Dallas. Ini Nashville”
HUMOR-HUMOR DARI NEGERI SAYAP KIRI juga ada. Banyak. Dan terutama yang berasal dari balik Tirai Besi pada hemat saya adalah lebih kaya dan lebih menggelitik. Lebih manjur, cespleng begitulah, yang mungkin karena mereka mempunyai basis penguat ! Humor-humor mereka adalah justru berangkat dari kesedihan, barangkali hidup yang pahit. “Rusia sebegitu jauh telah menghapus Tuhan, tetapi Tuhan sebegitu jauh masih lebih toleran”
Yah, memang. Seperti halnya Mark Twain yang dikutip Alfons Taryadi dalam Kompas, “sumber tersembunyi humor bukanlah keriangan melainkan kesedihan. Di Sorga tak ada humor” – (maka) di negeri “agama adalah candu” rasanya kita bisa menerima bahwa humor relevan subur bermunculan. Terlebih lagi, mungkin (!), ini akibat Rusia sendiri telah menghapus Tuhan, sementara yang namanya Sorga bukankah cuman hak patent milik Tuhan ? Di Sorga toh tak ada humor.
“Kalau bangsa Amerika memiliki Mafia, kami bangsa Rusia juga mempunyainya. Namanya : Pemerintah”
Atau yang jenis ini, satu lagi pil pahit. Bungkusnya tentu saja humor. Suatu malam pintu rumah seorang petani Rusia terdengar diketuk orang. “Siapa di luar ?”, sapa Pak Tani dengan cemas. Was-was. “Saya Malaikat Pencabut Nyawa !” Dada Pak Tani terasa longgar kemudian melepaskan nafas panjang, nafas lega. “Sokurlah, sokurlah, mari silakan masuk. Saya kira Anda polisi rahasia”
HUMOR MENGENAI FILSAFAT DASAR NEGERI RUSIA ? Mari, dan dimulai dengan mengutip apa yang dicatat oleh The Listener dari Inggris, saya baca kemudian dari majalah Readers Digest :
Apa itu filsafat ? Ialah kucing hitam di dalam kamar gelap. Lalu, apa itu filsafat Marxist ? Ialah kamar yang gelap di mana Anda mencari kucing hitam, sedang kucing tersebut sebenarnya tidak ada. Kalau filsafat Marxist-Leninist bagaimana pula ? Jawabnya : adalah kamar yang gelap di mana Anda mencari kucing hitam di dalamnya sedang kucing itu sebenarnya tidak ada – tetapi Anda tetap berteriak keras-keras : ‘Ini kucingnya, aku mendapatkannya !’ “
RUSIA DAN PULA ISRAEL, ras bangsa Skot atau pun negeri Cina merupakan bangsa-bangsa yang sering kita dengar punya humor-humor khas yang sanggup membuat perut kita keras. Ini lagi satu kisah dari negeri ketua Mao ketika mendapat kunjungan Presiden Amerika. Kalu tak khilap, Presiden Eisenhower.
Beliau asal negeri Sayap Kanan ini memang disambut hangat ketika mendarat di ibukota negeri Sayap Kiri ala Mao itu, Peking. Tetapi di antara sambutan hangat itu ada sesuatu yang aneh : penduduk Peking menyambut tanpa disertai secercah pun sungging senyum. “Mengapa begitu, Komrade ?” tanya pak Eisenhower.
A-ha, Ketua Mao rupanya sudah siaga kung-fu untuk melakukan loncatan jauh ke depan, memberi tendang balas yang jitu. “Waktu jaman Long March dahulu demi untuk menghilangkan rasa kelaparan, rakyat kami selalu saja berusaha tertawa. Dan sekarang ? Anda kini jadi saksi, mereka tidak tertawa lagi”
II
BAGAIMANA TENTANG BANGSA KITA ? Adalah pak Mochtar Lubis yang baru-baru saja meletuskan humor tentang Indonesia. Bahwa nabi Adam dan Ibu Hawa itu orang asli Indonesia. Punya ciri kuat sebagai jembel, hanya punya tiga hal –buah khuldi, ular dan telanjang—tetapi mengira bahwa hidupnya sudah kayak di Firdaus saja.
Atau lagi, bahwa orang Indonesia masa kini, kata orang, punya tiga kecenderungan serentak : memakai pakaian model masa lampau, memakai mobil model masa kini, menghabiskan biaya masa depan.
Pengin dengar humor tentang Indonesia yang rodo-rodo memakai unsur internasional ? Ini dia. Adalah kata sahibul hikayat berbincanglah tiga orang : Amerika, Jepang dan Indonesia. Bertiga saling pamer kelebihan negeri masing-masing.
“Neil Armstrong yang mendarat di bulan adalah lambang supremasi kesuperioran negeri kami”, si Amerika memulai. “Ia bisa mendarat dengan tepat di permukaan bulan pada satu tempat yang sudah lama direncanakan”
“Apa memang tepat benar ?”, sanggah si Jepang dan Indonesia getas.
“Yeaah. Ya tidak tepat benar”, kilah Paman Sam. “Selisih jarak lokasi yang didarati dan yang direncanakan ada sekitar seratus meter”
Gantian si Jepang. “Negeri Anda berdua punya bullet train ? “. Si Indonesia gemas. Si Amerika gemas. “Kereta kami itu sanggup berangkat dari satu stasiun dan secara otomatis nanti kembali tepat pada lokasi ketika berangkatnya !”
“Apa memang tepat benar ?”, kini Amerika menyerbu. Indonesia diam.
“Ah, ya memang tidak tepat benar”, elak si Jepang. “Selisihnya ada sekitar barang dua-tiga meter”.
Kini, ini dia, Indonesia ganti berdiri. “Anda berdua pernanh dengar bahwa di Indonesia ada orang sanggup melahirkan anak lewat dubur ?”. Paman Sam kaget. Si Jepang kaget. Sama-sama setengah mati. Was-was. Kalau-kalau teknologi medis mereka telah tersaingi.
“Apa memang tepat benar itu ?” Paman Sam menyerbu dengan tinju, Jepang dengan mawashi-geri model karate. Si Indonesia sih kalem-kalem saja : “Ya, tidaklah tepat benar. Ada selisih kurang dari sepersepuluh meter”.
III
SEBEGITU JAUH JENIS HUMOR YANG LAIN, misal tentang pemerintah atau kebijaksanaan politiknya, adalah masih tabu. Atau terbatas, terisolir di antara gedung-gedung parlemen. Atau mungkin karena terlalu riskan.
Contoh kita selama ini yang berani ambil resiko adalah dramawan Rendra. Ia “maestro”, walau ia diperbolehkan berbagi humor dengan publik cuman di kawasan “bagian Republik Indonesia yang paling merdeka” : TIM, Jakarta. Bahkan sebelum masa akhir-akhir ini, ia dilarang meledek di kota asalnya : Yogya. Malah di kota tempat lahirnya, Solo, poster wajahnya kena coret. Di-la-rang !
Sokur saja humor itu sendiri tetap ada. Kita tahu sendiri, kita mengalami sendiri. Baik karton crude Johnny Hidayat di (majalah) STOP mau pun jenis model reog BKAK di televisi. Atau, kita kenal akan tokoh Pak Basiyo dari Yogya yang hemat saya benar-benar “maestro” plus piawai berhumor sealur logika bisosiasi yang ditawarkan oleh seorang Arthur Koestler. Silakan dengar seri kasetnya, sayang hanya dalam bahasa Jawa, untuk berhura-hura.
KITA KINI MEMANG JADI SAKSI, kita tahu sendiri : yang sangat laris adalah humor dalam peran sebagai alat penghibur. Sebagai jongos, kata pak Arwah Setiawan. Alias penekunan humor sebagai salah satu di antara tiga kawasan kreativitas, di samping kesenian dan ilmu pengetahuan, masih ngenas. Sisi peran humor yang antara lain sebagai alat koreksi, kritik, rupanya memang masih dililit masalah di sana-sini.
Kenapa ?
Atau memang, kita-kita ini tidak percaya dan tidak peka terhadap humor dalam peran sebagai kritik ? Siapa bisa menjawab. Tetapi semoga saya diijinkan untuk condong meng-ya-kan, bahwa kita toh masih punya humor, humor soliloquy, humor percakapan sendiri. Dengan arti, betahlah untuk sementara (atau selamanya ?) kita-kita ini untuk sabar terpusar dalam situasi “katastrophe” yang tersurat dari puisi Taufik Ismail :
PENDERITAAN
Berakit-rakit ke hulu
berenang-renang ke tepian,
Bersakit-sakit dahulu,
bersakit-sakit berkepanjangan
Hingga dalam melulu “bersakit-sakit berkepanjangan” itu toh otomatis kita masih terus bisa berhumor bukan ? Sebab, di sorga tak ada humor. Di sorga tak perlu ada kritik. Dengan humorlah kita bisa menyalurkan rasa bersakit-sakit seirama buku biru Arthur Koestler, The Act of Creation, yang pernyataannya senada Freud : humor justru merupakan pengganti kekerasan, penyalur nafsu-nafsu agresif dalam jiwa manusia.
MARI BERHIMPUN. HIDUP LHI. MARI TERTAWA, tertawa itu pengobat paling mujarab, kata Readers Digest. Dan lagi, menertawai diri sendiri kata petuah, merupakan satu kebajikan.
Ini dia, lagi puisi Taufik Ismail yang lain, kiranya bisa berjasa mengendorkan saraf-saraf kita, jidat kerut merut kita dewasa ini :
BAGAIMANA KALAU
Bagaimana kalau dulu bukan khuldi yang dimakan Adam, tapi buah alpukat.
Bagaimana kalau bumi bukan bulat, tetapi segi empat.
Bagiamana kalau lagu Indonesia Raya kita rubah, dan kepada Koes Plus kita beri mandat.
Bagaimana kalau ibukota Amerika Hanoi, dan ibukota Indonesia Monaco.
Bagaimana kalau malam nanti jam sebelas, salju turun di Gunung Sahari.
Bagiamna kalau bisa dibuktikan bahwa Ali Murtopo, Ali Sadikin dan Ali Wardhana ternyata pengarang-pengarang lagu pop.
Bagaimana kalau hutang-hutang Indonesia dibayar dengan pementasan Rendra.
Bagaimana kalau segala yang kita angankan terjadi, dan segala yang terjadi pernah kita rancangkan.
Bagaimana kalau akustik dunia jadi sedemikian sempurnanya sehingga di kamar tidur kau sampai deru bom Vietnam, gemersik sejuta kaki pengungsi, gemuruh banjir dan gempa bumi serta suara-suara percintaan anak muda, juga bunyi industri persisi dan margasatwa Afrika.
Bagaimana kalau pemerintah diizinkan protes dan rakyat kecil mempertimbangkan protes itu.
Bagaimana kalau kesenian dihentikan saja sampai di sini dan kita pelihara ternak sebagai pengganti.
Bagaimana kalau sampai waktunya kita tidak perlu bertanya bagaimana lagi.
(1971)
BAGAIMANA KALAU sampai waktunya kita tidak perlu bertanya bagaimana lagi ? Tertawa saja hingga dunia ikut tertawa, sebab menangislah maka kamu akan menangis sendirian saja.
Bagaimana kalau sampai waktunya kita tidak perlu bertanya bagaimana kok tidak tertawa lagi ? Mari menangis, dalam tertawa. Atau : kita pilih serempak diam bagai mulut botol kena sumbat ? Tetapi ingat, diam jenis ini adalah “sunyi bagai dunia bisik”.
Atau mungkin kita lebih memilih : kritik yang tanpa kata. Atau, situasi sebar luasnya virus apatis yang nurut kata sementara Bapak ia berbahaya bagi kesinambungan dan kelanggengan hidup bernegara. Atau, pilih saja pola kebudayaan sas-sus hingga kita biar mudah terseret dalam situasi absurd ?
Memang. Apabila dalam situasi serba rancau bahasa, absurd, jelasnya bila menurut dramawan Eugene Ionesco adalah situasi tragedi bahasa, kritik atau pun kritik humor rasanya orang sangat ciut nyali untuk mendendangkannya. Maka adalah seorang Martin Esslin ketika memperbincangkan ihwal Teater Absurd ia mengutip apa arti “absurd” sebagaimana yang dikatakan oleh Ionesco, sebagai berikut :
What is sometimes labeled the absurd, is only denunciation or the ridiculous nature of language which is empty substance, made up cliches and slogans.
Ya. Betapa mengerikan bila bahasa telah hanya merupakan bangunan klise-klise dan slogan-slogan belaka.
Adalah Goenawan Mohamad mengatakan di antara bagian kredonya yang terkenal, Potret Seorang Penyair Muda Sebagai Si Malin Kundang, berkenaan situasi tragedi bahasa atau “...suatu bahasa otomatik yang dimaksudkan Ionesco (adalah sbb : - HT) dengan apa pembicaraan dari hati ke hati menjadi sulit, dengan apa diskusi menjadi kandas, dengan apa telaah perundang-undangan hampir mustahil...Tapi apa lagikah yang tinggal apabila kata kontra revolusioner (bisa diganti : subversif, mengganggu kestabilan nasional, etc – HT) yang tak jelas pengertiannya itu sudah cukup untuk membunuh orang ?”
ITULAH MAKANYA, dalam situasi tersebut –sesudah semacam keterusterangan dan semacam humor alegori—satu kritik, kritik humor besar kemungkinan mudah ditarik ke dalam pengertian “lebih condong kepada baik buruknya konotasi daripada kepersisan definisi” : mengganggu kestabilan nasional.
Seseorang di Surabaya, Aceh, Sangir talaud, Bandung, Yogya atau Jakarta sesudah sama-sama membaca kisah Nasarudin Hoja pada majalah anak-anak Kawanku, lalu sama-sama berbincang kejenakaannya, sama serentak terbahak, dalam kemelut tragedi bahasa mungkin sekali semua himpunan pencandu Hoja bisa kena vonis yang mengecutkan hati itu.
Semoga saja tidak. Atau, belum tidak ? Kalau pun ya, ya memang sudah suratan nasib : kita semua akan menikmati seperti apa yang dimaui oleh seorang jenderal Amerika, Phillip H. Sheridan (1855) mengenai negeri Texas. “Bila saja aku memiliki Texas dan sekaligus Neraka, maka Texas akan aku sewakan saja dan aku lebih baik tinggal berdiam di Neraka”
IV
INDONESIA 1978 TENTU SAJA BUKAN TEXAS 1855. Bukan pula neraka. Melainkan, Come ! Beautiful Islands. And the welcome await you when you make trip to Indonesia, begitu iklan GIA di Time. Dan sementara iklan di AI (Amnesty International) dan IPI (International Press Institute), pfuah, itu urusan orang lain yang usil.
Bagi kita, yang sudah terbiasa “penderitaan dan kemiskinan adalah pengalaman sehari-hari. Asketisme (yang bukan a la biara) ini sudah mendarah daging” (T.H. Sumartana, “Cara Kita Menahan Derita”, TEMPO, 15 Oktober 1977), negeri kita (sekali lagi) bukan Texas-nya Sheridan di atas. Kita semua nampak masih sabar menunggu, masih nampak sabar selalu, merasa betah dengan hidup ini. Dan kata orang, itulah optimisme !
Jadi umpama pun kena serbu senewen-senewen dikit, tak apalah, pusing-pusing sedikit, bukankah “Keluarga Sejahtera Indonesia 1978” menawarkan Inza ? Mules-mules dikit akibat HO atau KM ? Kencangin ikat pinggang ! Dan bila pun tuli-tuli sedikit, apa “Keluarga Sejahtera Indonesia 1978” tidak kenal King Aid ?
Ya. Sebab kita semua maklum bahwa para guru pengambil kebijaksanaan, yang di atas-atas sana itu atau paduka-paduka semacamnya itu, sudah sangat pasti bahwa beliau-beliau perlu diberi kasihan. Karena lebih dulu dan lebih banyak kena serbu macam-macam rasa tak enak ketimbang kita yang biasa-biasa saja ini.
Adalah cerita Marie Fraser di Indiana Teacher, saya temui di Readers Digest (1966). Ini dia :
Di luar bangunan Istana Christianborg, yaitu Gedung Parlemen Denmark di Kopenhagen, terdapat tiga patung yang mengawal pintu gerbangnya. Patung tersebut melambangkan tokoh : orang yang lagi pusing-pusing kepalanya, orang yang mulas-mulas perutnya, dan orang yang tuli (!) pendengarannya.
“Ketiga patung tersebut menyarankan pada Anda”, tutur orang Denmark sambil senyum sayur asam, “Bahwa bila Anda memasuki kancah politik maka Anda pasti akan mengidap penyakit itu ketiga-tiganya”.
* Harry Tekssi adalah nama aktivis kesenian dari Bambang Haryanto pada tahun 1970-an, di lingkungan PKJT (Pusat Kebudayaan Jawa Tengah), Sasonomulyo, Solo. Artikel ini telah dimuat di majalah Semangat (Yogyakarta), No. 10, Juni 1978 : 18-20.
Wonogiri, 18-19 Mei 2005
Subscribe to:
Post Comments (Atom)






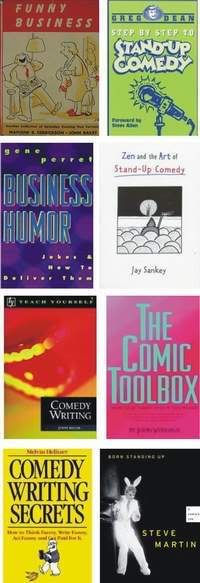
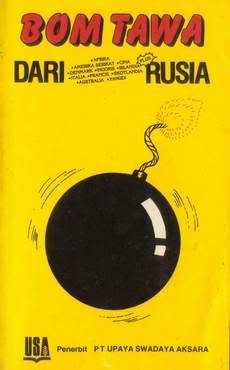
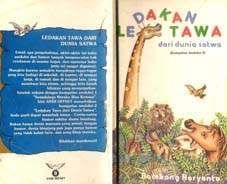



wkwk... lucu gan.
ReplyDeleteterapi alat vital
türkçe porno
ReplyDelete